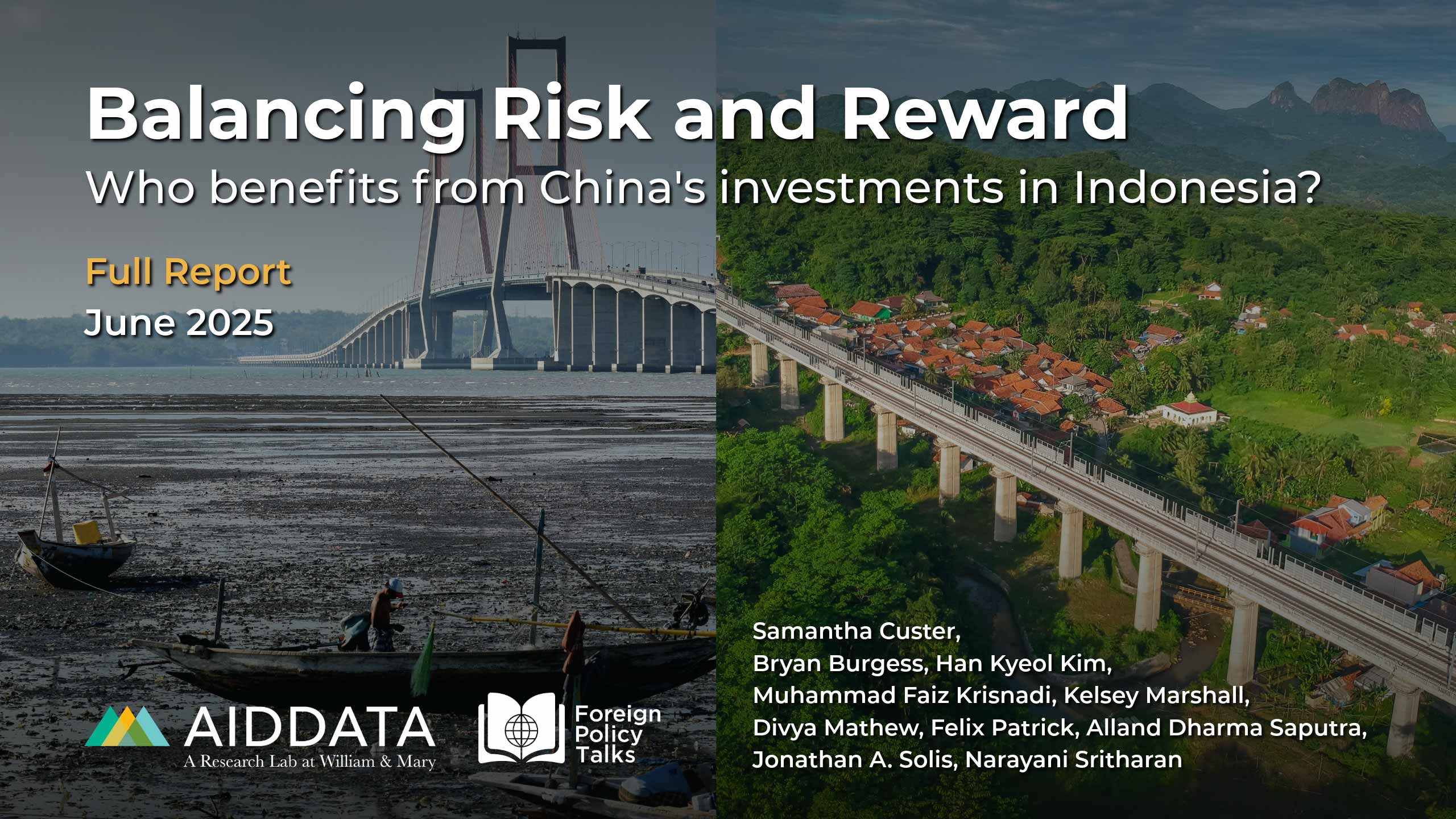
Antara Risiko dan Imbal Hasil
Siapa yang Diuntungkan dari Investasi Tiongkok di Indonesia?
Samantha Custer, Bryan Burgess, Han Kyeol Kim, Muhammad Faiz Krisnadi, Kelsey Marshall, Divya Mathew, Felix Patrick, Alland Dharma Saputra, Jonathan A. Solis, Narayani Sritharan
Juni 2025
Ucapan Terima Kasih
Laporan ini disusun oleh Samantha Custer, Bryan Burgess, Han Kyeol Kim, Muhammad Faiz Krisnadi, Kelsey Marshall, Divya Mathew, Felix Patrick, Alland Dharma Saputra, Jonathan A. Solis, dan Narayani Sritharan. John Custer dan Sarina Patterson memberikan dukungan dalam tata letak, penyuntingan, dan visual publikasi ini. Desain sampul dibuat oleh Sarina Patterson, dengan foto Jembatan Suramadu (kiri) dan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (kanan) masing-masing oleh Dodo Hawe dan Habib Farindra, melalui Adobe Stock, digunakan dengan lisensi Standar.
Kajian ini dilakukan oleh AidData, sebuah laboratorium riset yang berbasis di Amerika Serikat di bawah Global Research Institute, William & Mary, bekerja sama dengan Foreign Policy Talks Indonesia. Kami menyampaikan penghargaan kepada Noto Suoneto atas tinjauan dan masukan yang memperkuat analisis dan temuan laporan ini.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tujuh pakar Indonesia dari kalangan media, lembaga pemikir, pemerintahan, masyarakat sipil, dan akademisi yang telah dengan sukarela berbagi wawasan melalui wawancara latar belakang.
Penelitian ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Temuan dan kesimpulan dalam laporan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab para penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan dari para pemberi dana maupun mitra kami.
Sitasi
Custer, S., Burgess, B., Kim, H.K., Krisnadi, M.F., Marshall, K., Mathew, D., Patrick, F., Saputra, A.D., Solis, J.A., and N. Sritharan. (2025). Antara Risiko dan Imbal Hasil: Siapa yang Diuntungkan dari Investasi Tiongkok di Indonesia? . Williamsburg, VA: AidData at William & Mary.
1.1 Hubungan Indonesia–Tiongkok: Sebuah narasi yang terus berkembang
1.2 Melacak strategi ekonomi Beijing di Indonesia
2.1.1 Bagaimana posisi Beijing dibandingkan dengan mitra pembangunan lain?
2.1.1.1 Perbandingan syarat bantuan Beijing dengan pihak lain
2.1.1.2 Perbandingan tren bantuan Beijing dengan pihak lain
2.1.1.3 Perbandingan fokus sektoral Beijing dengan pihak lain
2.1.2 Bagaimana variasi aliran pembiayaan pembangunan Tiongkok di Kawasan ASEAN?
2.2 Bagaimana variasi pembiayaan Beijing di bawah tiap pemerintahan?
2.2.1 Abdurrahman Wahid (1999–2001)
2.2.2 Megawati Soekarnoputri (2001–2004)
2.2.3 Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014)
2.3 Komunitas mana yang menjadi lokasi investasi Tiongkok dan apa alasannya?
3.1 Sisi penawaran: Siapa yang mendanai dan melaksanakan proyek pembangunan yang didukung RRT?
3.1.1 Pandangan terhadap pelaksana proyek asal Tiongkok di Indonesia
3.2 Sisi permintaan: Siapa penerima utama proyek investasi RRT di Indonesia?
3.2.1 Perusahaan dan lembaga mana yang paling terdampak oleh keterlibatan Beijing?
4.1. Sejauh mana Tiongkok merealisasikan investasi yang dijanjikan tepat waktu dan sesuai komitmen?
4.1.1 Dari janji ke pelaksanaan: Seberapa cepat aliran dana terjadi?
4.1.2 Gagal terealisasi? Penangguhan dan pembatalan proyek
4.2.1 Indikator dini risiko ESG dalam proyek pembiayaan RRT
4.2.2 Paparan terhadap Risiko Kinerja dalam Proyek yang Dibiayai Tiongkok
4.3 Bagaimana pembiayaan Tiongkok memengaruhi persepsi dan hasil pembangunan di Indonesia?
4.3.1 Memenangkan hati dan pikiran? Persepsi dan pembiayaan
4.3.2 Manfaat publik atau kerugian publik? Dampak pembiayaan Tiongkok
4.3.2.1 Pembiayaan RRT dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia
4.3.2.2 Pembiayaan RRT dan dampaknya terhadap lingkungan Indonesia
4.3.2.3 Pembiayaan RRT dan dampaknya terhadap aspek sosial dan tata kelola di Indonesia
5.1 Prioritas yang terungkap: Proyek apa, kapan, dan di mana?
5.2 Jaringan pengaruh: Siapa saja aktornya, apa perannya, dan mengapa?
Tabel 2.1: Total komitmen pembiayaan resmi dari mitra pembangunan utama ke Indonesia, 2000–2023
Gambar 2.2: Total komitmen pembiayaan resmi dari Tiongkok ke Indonesia, 2000–2023
Tabel 2.4: Sepuluh sektor utama proyek pembangunan yang didanai RRT di Indonesia, 2000–2023
Tabel 2.6: Total komitmen pembiayaan pembangunan RRT ke negara-negara ASEAN, 2000–2021
Gambar 2.7: Proyek pembangunan yang didanai RRT di Indonesia, 2000–2023
Tabel 2.8: Tren utama proyek pembangunan yang didanai RRT berdasarkan pemerintahan di Indonesia
Kotak 1. Jembatan Surabaya–Madura (Suramadu)
Kotak 2. Kereta Cepat Jakarta–Bandung (HSR)
Gambar 2.9: Proyek pembangunan yang didanai Tiongkok di Indonesia berdasarkan provinsi, 2000–2023
Tabel 2.10: Proyek resmi RRT di Indonesia berdasarkan provinsi, 2000–2023
Gambar 2.11: FDI masuk dari Tiongkok dan dunia ke Indonesia, 2010–2024
Tabel 2.12: FDI masuk dari Tiongkok dan dunia ke Indonesia, 2010–2024
Gambar 2.13: Pangsa FDI Tiongkok terhadap total FDI di Indonesia, 2010–2024
Peta 2.14: FDI masuk dari Tiongkok ke Indonesia menurut wilayah, 2010–2024
Tabel 2.15: FDI masuk dari Tiongkok ke Indonesia menurut wilayah, 2010–2024
Kotak 4. Sinergi antara pembiayaan pembangunan dan FDI Tiongkok di Sumatra
Tabel 2.16: Sektor-sektor terpilih, FDI masuk dari Tiongkok dan dunia ke Indonesia, 2010–2024
Tabel 3.2: Sepuluh pendana utama proyek pembangunan yang didanai Tiongkok di Indonesia, 2000–2023
Gambar 3.3: Pendana utama asal Tiongkok dan penerima di Indonesia, 2000–2023
Tabel 3.5: Sembilan pelaksana utama proyek pembangunan yang didanai Tiongkok di Indonesia, 2000–2023
Gambar 3.6: Penerima dan pelaksana proyek pembangunan yang didanai Tiongkok di Indonesia, 2000–2023
Gambar 3.9: Penerima pendanaan Tiongkok di Indonesia menurut sektor, 2000–2023
Tabel 3.10: Penerima proyek pembangunan yang didanai Tiongkok di Indonesia
Tabel 4.1: Rata-rata waktu antar tahap proyek pembangunan yang didanai RRT di Indonesia, 2000–2022
Tabel 4.6: Risiko ESG dalam proyek yang didanai RRT di Indonesia menurut sektor, 2000–2021
Tabel 4.7: Risiko kinerja dan pelaksana proyek pembangunan asal Tiongkok di Indonesia, 2000–2023
Tabel 4.8: Sepuluh pelaksana berisiko tinggi asal RRT berdasarkan jumlah dan nilai proyek, 2000–2023
Tabel 4.12: Pembiayaan pembangunan dan FDI Tiongkok serta hasil ekonomi di Indonesia, 2001–2023
Ringkasan Eksekutif
Sejak awal 2000-an, peran dana dari Tiongkok dalam pertumbuhan Indonesia telah berubah drastis, dari sekadar pelengkap menjadi salah satu pemain utama. Pemerintah, BUMN, hingga perusahaan swasta asal Tiongkok menggelontorkan investasi besar ke berbagai proyek di Indonesia, mulai dari pembangunan jalan raya, pembangkit listrik, hingga pabrik pengolahan nikel. Meski nilainya besar, arus dana ini tidak selalu stabil. Ada kalanya melonjak tajam di tahun-tahun awal, lalu turun drastis di tahun berikutnya. Buku ini mengajak pembaca menelusuri aliran dana tersebut, melihat hubungan yang terjalin, dan menimbang hasil yang tercapai selama kurang lebih dua dekade pembiayaan pembangunan dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) serta investasi asing langsung dari sektor swasta.
Uang: Proyek apa saja yang dibiayai oleh RRT, di mana, kapan, dan kenapa?
Beijing menggelontorkan dana untuk proyek-proyek besar berisiko tinggi di Indonesia, terutama di sektor energi, transportasi, dan ekstraktif. Proyek-proyek ini bukan hanya berpeluang memberikan keuntungan komersial, tetapi juga sejalan dengan tujuan Belt and Road Initiative (BRI) serta menjawab kepentingan politik dalam negeri mereka. Di sisi lain, Tiongkok juga melengkapi investasi skala raksasa itu dengan proyek-proyek sosial yang lebih kecil sebagai bentuk diplomasi goodwill.
Secara strategis, Beijing mengalokasikan sumber daya negara senilai 69,6 miliar dolar AS dalam bentuk pembiayaan resmi dari tahun 2000 hingga 2023. Langkah ini bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat citra positif yang diharapkan dapat memicu masuknya investasi asing langsung (FDI) dari Tiongkok. Hasilnya, pada periode 2010 hingga 2024, FDI dari Tiongkok mencapai 94,1 miliar dolar AS, jumlah yang setara dengan seperempat dari total belanja modal asing baru di Indonesia.
Sebagai penyandang dana pembangunan terbesar, Beijing lebih berperan sebagai pemberi pinjaman komersial ketimbang donor tradisional. Sekitar 90 persen pembiayaan disalurkan dalam bentuk utang, bukan hibah. Dibandingkan negara-negara ASEAN lain, Indonesia menjadi tujuan utama modal Tiongkok, baik dalam bentuk pinjaman maupun hibah. Sebagian besar pembiayaan pembangunan itu terserap di Jawa dan Sumatra, namun daerah kaya sumber daya alam seperti Papua Barat dan Sulawesi Tengah juga mendapat perhatian, bahkan menikmati pembiayaan per kapita yang jauh lebih tinggi.
Hubungan: Siapa saja aktornya, berapa jumlahnya, dan apa peran mereka?
Proyek pembiayaan pembangunan Tiongkok di Indonesia bukanlah semata-mata hasil kerja dalam negeri mereka, melainkan buah dari keterlibatan jaringan global yang luas. Jaringan ini mencakup 439 entitas dari 35 negara. Dari pihak Tiongkok sendiri, ada 58 entitas, termasuk bank kebijakan, bank komersial milik negara, lembaga pemerintah, dan perwakilan diplomatic, yang menjadi penyandang dana utama. Mereka bekerja sama dengan 208 lembaga pembiayaan bersama (co-financier) dari Asia, Eropa, hingga Amerika Utara untuk menggalang modal dan membagi risiko.
Badan usaha milik negara (BUMN) Tiongkok mendominasi sebagai pelaksana proyek. Dari 213 pelaksana, 14 di antaranya pernah dijatuhi sanksi akibat praktik keuangan yang dianggap tidak etis. Meski demikian, BUMN Tiongkok bukanlah satu-satunya pemain. Hampir separuh pelaksana proyek Tiongkok di Indonesia justru berasal dari entitas lokal, mulai dari perusahaan independen hingga mitra dalam usaha patungan ( joint venture ) dan perusahaan tujuan khusus ( special purpose vehicle ).
Untuk proyek di sektor sosial, Tiongkok memanfaatkan legitimasi dan jaringan distribusi organisasi keagamaan Islam serta universitas-universitas di Indonesia demi mendapatkan dukungan publik. Ada enam penerima dana yang mendapat kucuran besar dan berulang dari Tiongkok: Pemerintah Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Garuda Indonesia, serta dua perusahaan telekomunikasi, Smartel dan Smartfren, yang kini bergabung dengan XL Axiata di bawah Grup Sinar Mas. Selain BUMN, konglomerat swasta besar juga masuk daftar penerima, di antaranya Grup Bakrie melalui Bumi Resources, Bakrie Telecom, dan Bakrie Autoparts, serta anak perusahaan CT Corp milik Chairul Tanjung, seperti Trans Retail Indonesia dan Trans Media Corpora.
Hasil: Bagaimana Beijing menindaklanjuti dan mengelola risiko, serta apa dampaknya?
Di seluruh Indonesia, proyek-proyek yang dibiayai oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) rata-rata membutuhkan waktu sekitar dua setengah tahun untuk beralih dari tahap komitmen dana ke pelaksanaan. Angka ini tergolong lambat, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain seperti Filipina. Di antara berbagai sektor, energi dan transportasi menjadi yang paling berisiko: sering mengalami keterlambatan hingga lebih dari seribu hari, sekaligus memiliki potensi tinggi terhadap risiko lingkungan dan sosial.
Pemilihan pelaksana proyek menjadi faktor krusial karena berpengaruh langsung pada keberhasilan proyek dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sayangnya, lebih dari 40 persen portofolio pembiayaan pembangunan RRT, setara 30 miliar dolar AS, bergantung pada pelaksana yang dianggap berisiko tinggi. Mereka memiliki catatan keterlibatan dalam masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola ( ESG ), atau pernah terkena sanksi akibat praktik bisnis yang tidak etis. Beberapa di antaranya bahkan terlibat berulang kali dalam proyek-proyek serupa.
Bagi Beijing, tantangan besarnya adalah mengubah investasi besar menjadi keuntungan reputasi. Tingkat dukungan publik terhadap kepemimpinan RRT di Indonesia cenderung menurun seiring semakin besarnya keterlibatan ekonomi mereka. Meski kalangan elit di sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil mengakui pengaruh Beijing terhadap arah pembangunan Indonesia, mereka juga menyimpan kekhawatiran yang semakin besar.
Secara keseluruhan, kontribusi modal Tiongkok terhadap pembangunan Indonesia memberikan hasil yang beragam. Dari sisi ekonomi, provinsi yang menerima lebih banyak investasi asing langsung ( FDI ) dari Tiongkok umumnya memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi, sementara wilayah yang memperoleh pembiayaan pembangunan lebih besar dari Beijing cenderung memiliki tingkat pengangguran lebih rendah. Namun, tidak semua dampaknya positif. Peningkatan polusi dan berkurangnya vegetasi memang tidak selalu sejalan dengan besarnya modal Tiongkok yang masuk, tetapi kawasan seperti Morowali menjadi contoh nyata bagaimana proyek tertentu dapat membawa konsekuensi lingkungan yang berat.
Pada akhirnya, ada tanda-tanda bahwa masyarakat Indonesia tengah merumuskan ulang pandangan mereka tentang arti keberhasilan demokrasi, lebih menekankan pada pembangunan ekonomi daripada hak-hak politik. Menariknya, arah pandangan ini sejalan dengan narasi dan nilai yang kerap diusung oleh Beijing.
1. Pendahuluan
P ertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, serta populasi muda yang besar menjadikannya magnet bagi para mitra ekonomi dunia (ITA, 2023; UNDP, 2024). Secara geostrategis, Indonesia berada di jalur perdagangan maritim utama dan membentang di pesisir barat Selat Malaka, posisi yang sejak lama menjadi incaran banyak kekuatan ekonomi besar (China Power, 2017). Menyadari potensi ini, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengerahkan strategi ekonomi luar negerinya lewat perdagangan, bantuan luar negeri, dan investasi asing langsung ( foreign direct investment / FDI), dengan tujuan memposisikan diri sebagai penyedia modal utama untuk mendorong laju pertumbuhan Indonesia. Banyak kesepakatan baru diumumkan dengan sorotan media yang besar, namun tidak jarang minim transparansi dan mengundang kontroversi.
Kurangnya informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai apa yang diinvestasikan Beijing, di mana lokasinya, dan bagaimana dampaknya, membuat masyarakat maupun pemimpin Indonesia kesulitan menilai secara tepat untung-rugi dari kemitraan ini. Ketimpangan informasi seperti ini membuka ruang bagi munculnya narasi yang menyesatkan, baik yang terlalu memuji maupun yang terlalu mengkhawatirkan. Dengan latar tersebut, momen ini menjadi saat yang tepat untuk meninjau ulang arah hubungan ekonomi kedua negara, terutama seiring dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024 yang sedang merumuskan prioritas kebijakan luar negeri Indonesia.
Laporan Antara Risiko dan Imbal Hasil: Siapa yang Diuntungkan dari Investasi Tiongkok di Indonesia? menyajikan analisis mendalam berdasarkan data dari berbagai sumber untuk memetakan aliran dana, jejaring para pelaku, serta hasil dari dua dekade pembiayaan pembangunan yang diarahkan oleh negara RRT dan FDI dari sektor swasta (2000–2023). Penelitian ini disusun oleh AidData, laboratorium riset berbasis di Amerika Serikat di bawah Global Research Institute, William & Mary, bekerja sama dengan Foreign Policy Talks, sebuah organisasi terkemuka asal Indonesia yang menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan diskusi lintas batas di bidang kebijakan luar negeri.
Dengan memadukan analisis keuangan historis, kajian literatur, dan wawancara pakar di Indonesia, laporan ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama:
- Pendanaan: Proyek apa saja yang dibiayai RRT di Indonesia, di mana lokasinya, kapan dijalankan, dan melalui instrumen apa, baik pembiayaan pembangunan negara maupun FDI sektor swasta?
- Relasi: Siapa saja aktor yang terlibat, apa peran mereka, dan apakah ada pihak yang memegang kendali lebih besar dibanding yang lain?
- Dampak: Sejauh mana Beijing memenuhi komitmennya, bagaimana mereka mengelola risiko, dan apa saja dampaknya di tingkat lokal maupun nasional?
1.1 Hubungan Indonesia–Tiongkok: Sebuah narasi yang terus berkembang
Hubungan Indonesia–Tiongkok tidak selalu mulus. Tujuh belas tahun setelah menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jakarta secara dramatis memutuskan hubungan itu pada tahun 1967. Alasannya: tuduhan bahwa Beijing mendukung upaya kudeta yang dilakukan Partai Komunis Indonesia. Kudeta tersebut gagal, dan belakangan diketahui bahwa keterlibatan RRT sebenarnya sangat terbatas (Zhou, 2019). Meski begitu, peristiwa itu memicu kejatuhan Presiden Sukarno dan membuka jalan bagi transisi kepemimpinan. Butuh lebih dari dua dekade ketegangan sebelum kedua negara kembali duduk bersama dan memulihkan hubungan diplomatik pada 1990.
Di periode yang sama, RRT di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping melakukan perubahan besar dalam kebijakan luar negerinya. Fokusnya bergeser pada liberalisasi dan stabilisasi ekonomi demi menarik modal internasional, sekaligus meninggalkan dukungan terhadap gerakan komunis di luar negeri (Visscher, 1993). Reformasi ini membantu memulihkan hubungan dengan Indonesia pada dekade 1990-an, mempercepat industrialisasi, mendorong pertumbuhan berbasis ekspor, dan membuka jalan bagi keanggotaan RRT di Organisasi Perdagangan Dunia. Perubahan ini juga memperkuat posisi Beijing sebagai mitra yang kredibel ketika Indonesia berusaha bangkit dari krisis ekonomi pasca-Krisis Keuangan Asia 1997.
Selama tiga dekade terakhir, para pemimpin dan pejabat tinggi dari kedua negara melakukan berbagai kunjungan tingkat tinggi untuk membangun kembali kepercayaan. Pada 2005, hubungan kedua negara naik kelas menjadi “Kemitraan Strategis,” lalu pada 2013 menjadi “Kemitraan Strategis Komprehensif.” [1] Indonesia pun bergabung dalam Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN [2] –Tiongkok pada 2010, menjadi anggota pendiri Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) [3] pada 2015, dan secara resmi ikut serta dalam Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) pada 2017.
Meski hubungan ekonomi semakin erat, Jakarta tetap berhati-hati, terutama terkait sengketa maritim di Laut Natuna (Nabbs-Keller, 2020; Asia Maritime Transparency Initiative, 2024). Kedua negara memiliki klaim yang tumpang tindih atas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif di sekitar Pulau Natuna (Darmawan, 2020; 2024). Indonesia memperkuat kehadiran militernya di kawasan itu dan mengirim nota protes diplomatik (Nabbs-Keller, 2020). Namun, sikap ini mulai melunak setelah Presiden Subianto dan Presiden Xi Jinping mengumumkan pada November 2024 bahwa kedua negara akan bersama-sama mengembangkan wilayah tersebut (Darmawan, 2024).
Di sisi lain, elite politik dan ekonomi Indonesia mengkhawatirkan masuknya barang-barang Tiongkok yang lebih murah atau berkualitas rendah [4] , serta ketergantungan berlebihan pada investasi Tiongkok di sektor strategis seperti nikel (Nabbs-Keller, 2020; Sritharan & Rizkallah, 2024). Dalam lima tahun terakhir, berbekal investasi dan teknologi dari Tiongkok, Indonesia berhasil menjadi pemain dominan di industri nikel global, menyumbang 63 persen pasokan dunia (Forbes, 2025). Namun, kekhawatiran muncul karena Tiongkok menguasai sekitar tiga perempat operasi peleburan nikel di Indonesia (Reuters, 2025), sektor yang krusial bagi produksi baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik. [5]
Pidato dan kunjungan kenegaraan awal Presiden Subianto menunjukkan komitmen untuk mempererat kerja sama ekonomi dan keamanan dengan Tiongkok (Liu & Rayi, 2024; Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2025). [6] Namun, ia juga aktif menjalin hubungan dengan berbagai pihak lain, mulai dari Rusia dan Amerika Serikat hingga negara-negara Timur Tengah dan Turki (King, 2025). Usai kunjungan perdananya ke Tiongkok, Subianto langsung terbang ke Washington, sebuah isyarat bahwa pemerintahannya ingin merangkul kedua kekuatan besar tersebut secara bersamaan (Reuters, 2024).
1.2 Melacak strategi ekonomi Beijing di Indonesia
Selama tiga belas tahun berturut-turut, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menjadi mitra dagang terbesar Indonesia, tujuan utama ekspor, sekaligus pemasok barang impor terbesar. [7] Nilai perdagangan kedua negara yang pada 1990 hanya sekitar 1,18 miliar dolar AS kini telah melonjak pesat, mencapai 135 miliar dolar AS pada 2024 (Kedutaan Besar Tiongkok, 2004; Kementerian Perdagangan RI, 2025).
Antara 2000 hingga 2023, Indonesia menarik pembiayaan senilai sekitar 69,6 miliar dolar AS dari RRT untuk lebih dari 400 proyek pembangunan. Pasca krisis keuangan global 2008, Beijing tampil sebagai salah satu penyedia pembiayaan pembangunan terkemuka bagi Indonesia. [8] Skala proyeknya beragam, mulai dari program sosial berskala kecil seperti dukungan untuk sekolah dan organisasi masyarakat sipil, hingga megaproyek infrastruktur yang memanfaatkan melimpahnya cadangan nikel Indonesia.
Selain perdagangan dan bantuan, Tiongkok juga menjadi salah satu sumber investasi terbesar bagi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (2025) mencatat investasi langsung Tiongkok senilai 8,1 miliar dolar AS dalam 21.464 proyek pada 2024 saja. [9] Dalam sepuluh tahun terakhir, total investasi langsung Tiongkok mencapai 45 miliar dolar AS, tersebar dalam 43.702 proyek, dengan fokus pada sektor infrastruktur fisik dan digital strategis seperti energi, pertambangan, konstruksi, transportasi, dan telekomunikasi. [10]
Bab 2 buku ini menelusuri aliran dana tersebut untuk mengungkap prioritas Beijing: proyek apa yang mereka biayai, kapan, dan di mana lokasinya di Indonesia. Pembiayaan pembangunan yang diarahkan oleh negara RRT hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari hibah, pinjaman, instrumen utang, hingga bantuan teknis bagi sektor publik dan swasta. Ini mencakup Official Development Assistance (ODA), hibah dan pinjaman lunak yang tergolong “bantuan”, serta Other Official Flows (OOF), yakni pinjaman non-konsesional dan kredit ekspor yang tergolong “utang.” Selain itu, dibahas pula investasi asing langsung ( Foreign Direct Investment / FDI) Tiongkok, yaitu investasi dengan kepemilikan saham minimal 10 persen pada perusahaan di Indonesia, yang mencerminkan kepentingan jangka panjang dan kendali operasional.
Analisis ini didasarkan pada tiga sumber utama: (i) AidData’s Global Chinese Development Finance Dataset, Versi 3.0, yang memuat data proyek bantuan dan pembiayaan utang Tiongkok periode 2000–2021; (ii) riset tambahan untuk memetakan proyek yang diumumkan atau masih berjalan setelah 2021; dan (iii) data FDI masuk dari Tiongkok berdasarkan platform fDi Markets dari Financial Times Ltd. untuk periode 2010–2024.
Bab 3 mengulas aktor-aktor di balik pembiayaan pembangunan dari Beijing: berapa jumlahnya, siapa saja mereka, apa perannya, dan apakah ada yang lebih dominan dibanding lainnya. Dari sisi penawaran, kami memetakan jaringan lintas batas antara pendana, ko-pendana, dan pelaksana proyek yang mendukung pembangunan di Indonesia melalui pembiayaan RRT. Dari sisi permintaan, kami melihat komunitas, lembaga, dan organisasi mana yang paling banyak atau justru paling sedikit menerima dana tersebut, beserta alasannya.
Transparansi menjadi kunci. Tanpa bukti yang jelas dan meyakinkan, pembuat kebijakan, jurnalis, maupun publik akan kesulitan memahami dampak jangka panjang dari kemitraan dengan investor negara asing yang tidak selalu terbuka seperti RRT. Bab 4 kemudian menilai kinerja Beijing: sejauh mana janji investasi dipenuhi, bagaimana risiko publik dikelola, dan apa indikasi awal dari dampaknya di masyarakat.
Analisis ini menggunakan berbagai survei pihak ketiga dan data subnasional mengenai indikator ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola dari sumber-sumber terpercaya seperti Gallup World Poll, Varieties of Democracy, Bank Dunia, BPS, dan Asian Barometer, serta wawancara daring dengan para pakar yang dilakukan oleh AidData dan Foreign Policy Talks. [11]
Bab 5 merangkum temuan-temuan utama dari penelitian ini, sementara Lampiran Teknis menyediakan penjelasan rinci mengenai metode, asumsi, dan sumber data yang digunakan.
2. Pendanaan
Temuan utama bab ini:
- Beijing menerapkan strategi “dua jalur” di Indonesia: mengimbangi investasi raksasa yang berisiko tinggi di infrastruktur keras dengan banyak proyek pembangunan sosial berskala kecil.
- Dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia menonjol karena mampu menarik porsi pembiayaan pembangunan dan investasi asing langsung ( Foreign Direct Investment / FDI) dari Tiongkok yang relatif lebih besar.
- Proyek-proyek yang didanai RRT di sektor energi, transportasi, dan pengolahan mineral strategis dirancang untuk menghasilkan keuntungan komersial. Pendanaan ini memadukan dana publik dan swasta, serta diarahkan untuk mewujudkan ambisi Belt and Road Initiative (BRI) sembari merespons prioritas politik domestik Beijing.
Selama dua dekade terakhir, aliran dana dari Tiongkok di Indonesia berkembang pesat, dari sekadar catatan kecil dalam buku sejarah ekonomi menjadi salah satu sorotan utama dalam perjalanan pertumbuhan negeri ini. Lembaga pemerintah, badan usaha milik negara, dan perusahaan swasta asal Tiongkok telah menggelontorkan dana besar untuk membangun jalan raya, pembangkit listrik, hingga pabrik di berbagai daerah. Meski begitu, arus dana ini tidak selalu stabil: kadang melonjak tajam di satu tahun, lalu turun drastis pada tahun berikutnya.
Bab ini menelusuri jejak pendanaan tersebut untuk memahami prioritas strategis Beijing, dengan melihat pola pembiayaan pembangunan yang diarahkan negara dan FDI dari sektor swasta RRT. Kami memetakan bagaimana keterlibatan Tiongkok di Indonesia berubah dari waktu ke waktu, baik dibandingkan dengan donor lain maupun dengan negara-negara ASEAN tetangga (Bagian 2.1), serta bagaimana pola ini bergeser di bawah lima pemerintahan presiden (Bagian 2.2).
Kami juga mengupas wilayah dan komunitas mana yang paling banyak menerima investasi Tiongkok (Bagian 2.3), serta membandingkan pola FDI Tiongkok dengan pembiayaan pembangunan yang diarahkan negara berdasarkan sektor dan lokasi geografis (Bagian 2.4). Semua ini memberi gambaran utuh tentang bagaimana modal Tiongkok mengalir, di mana ia berlabuh, dan apa yang menjadi tujuan akhirnya.
2.1 Bagaimana perkembangan pembiayaan pembangunan RRT dari waktu ke waktu dan dibandingkan dengan alternatif lainnya?
Dalam dua dekade terakhir, pembiayaan pembangunan Tiongkok untuk Indonesia berkembang pesat. Namun, perjalanannya tidak selalu mulus atau berjalan lurus. Komitmen pendanaan dari Beijing naik-turun tajam, dipengaruhi oleh dinamika politik dan ekonomi kedua negara, serta ketidakpastian di panggung global.
Kondisi ini memunculkan tiga pertanyaan penting yang menjadi benang merah pembahasan di bagian berikut:
- Bagaimana tawaran pembiayaan pembangunan dari Beijing dibandingkan dengan opsi lain yang dimiliki Indonesia?
- Apakah pola keterlibatan ekonomi Beijing di Indonesia serupa atau berbeda dengan yang terlihat di negara-negara ASEAN lainnya?
- Sejauh mana kebijakan domestik dan aturan yang berlaku di Indonesia membentuk, atau justru membatasi, arus pembiayaan pembangunan dari RRT?
Ketiga pertanyaan ini akan kita telusuri satu per satu untuk memahami dengan lebih jelas arah, peluang, dan batasan dari hubungan finansial kedua negara.
2.1.1 Bagaimana posisi Beijing dibandingkan dengan mitra pembangunan lain?
Untuk melihat peran Tiongkok dalam konteks yang lebih luas, kami membandingkannya dengan enam mitra pembangunan lain yang juga aktif di Indonesia: Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia (World Bank/WB), Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Keenam mitra ini secara rutin melaporkan data pembiayaan pembangunan mereka—termasuk negara tujuan, sektor, jenis pendanaan, dan tahun, kepada Creditor Reporting System milik Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Analisis ini mencakup Official Development Assistance (ODA), hibah dan pinjaman berbunga rendah atau tanpa bunga, serta Other Financial Flows , yaitu pinjaman dan kredit ekspor dengan suku bunga pasar. Fokus pembahasan diarahkan pada komitmen pendanaan, agar perbandingan bisa dilakukan secara setara.
Hasilnya, antara tahun 2000 dan 2023, Indonesia menerima sekitar 69,6 miliar dolar AS pembiayaan pembangunan resmi dari Republik Rakyat Tiongkok, menjadikan Beijing mitra bilateral terbesar Indonesia (lihat Tabel 2.1). Jumlah ini bahkan melampaui total kontribusi gabungan dari empat donor bilateral besar lainnya: [12] Jepang (29,3 miliar dolar AS), Korea Selatan (15,7 miliar dolar AS), Australia (10,3 miliar dolar AS), dan Amerika Serikat (7,97 miliar dolar AS). Tak hanya itu, pembiayaan pembangunan dari RRT juga melampaui dua lembaga multilateral utama, Bank Dunia (47,7 miliar dolar AS) dan ADB (36,6 miliar dolar AS).
2.1.1.1 Perbandingan syarat bantuan Beijing dengan pihak lain
Jika dibandingkan dengan donor bantuan tradisional, Beijing lebih mirip pemberi pinjaman dan pengembang komersial. Lebih dari 90 persen pembiayaan pembangunan yang mereka salurkan berbentuk utang, mulai dari pinjaman non-konsesional hingga kredit ekspor, sementara hanya sekitar 3 persen yang berbentuk pinjaman konsesional (bunga rendah atau tanpa bunga) dan hibah. Akses ke pendanaan ini sering disertai syarat penggunaan kontraktor, rantai pasokan, atau skema pembiayaan bersama dari Tiongkok. Selama dua dekade terakhir, profil bantuan Beijing di Indonesia pun semakin berorientasi komersial, dengan fokus pada proyek-proyek yang bertujuan menghasilkan keuntungan dan kerap melibatkan pinjaman kepada perusahaan Indonesia atau lembaga tujuan khusus ( special purpose vehicle / SPV) (Gelpern et al., 2021).
Di ujung spektrum yang lebih dermawan, Jepang menyalurkan 100 persen pembiayaan pembangunannya dalam bentuk hibah atau pinjaman sangat lunak. [13] Australia dan Amerika Serikat juga memberikan pinjaman lunak dan hibah, meski fokus mereka lebih banyak pada sektor sosial seperti tata kelola, pendidikan, dan kesehatan. Perlu dicatat, analisis ini dilakukan sebelum pemangkasan anggaran bantuan oleh AS dan sejumlah donor Eropa pada 2024–2025 (Custer et al., 2025a & 2025b).
Korea Selatan menunjukkan pola yang lebih mendekati Tiongkok, yakni mengutamakan pinjaman terikat secara komersial untuk proyek-proyek yang dinilai layak secara ekonomi, meski skalanya jauh lebih kecil. Korea memadukan bantuan teknis dari Korea International Cooperation Agency dengan pinjaman dari Economic Development Cooperation Fund, yang mendukung perusahaan-perusahaan asal Korea. Total bantuan Korea Selatan ke Indonesia relatif kecil: hanya setengah dari nilai bantuan Jepang dan kurang dari seperempat komitmen Tiongkok. Salah satu proyeknya yang paling menonjol adalah Karian Serpong Water Supply Project (Susanty, 2017).
Sebagai negara berpendapatan menengah, Indonesia tidak lagi menikmati syarat pinjaman lunak yang biasa diberikan lembaga pembangunan multilateral seperti ADB dan Bank Dunia kepada negara berpendapatan rendah. Misalnya, pinjaman ADB senilai 331,3 juta euro untuk program kesehatan memiliki masa pelunasan 12,5 tahun dengan masa tenggang tujuh tahun (ADB, 2023). [14] Namun, dalam situasi darurat, lembaga-lembaga ini dapat menawarkan syarat lebih lunak, seperti bantuan pasca gempa dan tsunami Sulawesi 2018, ketika WB dan ADB memberikan total 1 miliar dolar AS dengan masa pelunasan 32 tahun dan masa tenggang delapan tahun (Tang, 2018).
Jika dibandingkan, rata-rata syarat utang dari Beijing lebih ketat daripada pinjaman serupa dari lembaga pembangunan multilateral. Untuk proyek-proyek yang datanya lengkap, [15] pinjaman Tiongkok ke Indonesia selama periode tersebut memiliki rata-rata masa pelunasan 8,6 tahun dengan masa tenggang 3,6 tahun. Meski begitu, ada pengecualian, terutama ketika Beijing harus bersaing dengan penyedia pembiayaan lain. Contoh paling terkenal adalah proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, di mana Tiongkok menawarkan syarat jauh lebih lunak karena bersaing ketat dengan Jepang. [16] Untuk proyek ini, Beijing memberikan pinjaman sebesar 4,5 miliar dolar AS dengan bunga dua persen, masa pelunasan 40 tahun, dan masa tenggang 10 tahun (Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022). Skema yang digunakan adalah business-to-business, dengan konsesi pengoperasian selama 50 tahun, yang kemudian diperpanjang menjadi 80 tahun akibat pembengkakan biaya (Mahardhika & Wibawa, 2023).
Tabel 2.1: Total komitmen pembiayaan resmi dari mitra pembangunan utama ke Indonesia, 2000–2023
Tabel dapat diurutkan dengan mengeklik kolom. Pada layar kecil, gulir secara horizontal untuk melihat kolom tersembunyi.
Mitra Pembangunan |
Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) |
Aliran Resmi Lainnya (OOF) |
Tidak Jelas (tingkat konsesionalitas tidak dapat ditentukan) |
|---|---|---|---|
|
Tiongkok (Total: 69,6 miliar dolar AS; ODA 3%) |
2,08 |
64,93 |
2,61 |
|
Asian Development Bank (Total: 36,6 miliar dolar AS; ODA 4%) |
1,29 |
35,36 |
N/A |
|
Australia (Total: 10,3 miliar dolar AS; ODA 97%) |
10,03 |
0,27 |
N/A |
|
Jepang (Total: 29,3 miliar dolar AS; ODA: 100%) |
29,34 |
0,00 |
N/A |
|
Korea Selatan (Total: 15,7 miliar dolar AS; ODA: 14%) |
2,18 |
13,51 |
N/A |
|
Amerika Serikat (Total: 7.97 miliar dolar AS; ODA: 100%) |
7,97 |
0,01 |
N/A |
|
Bank Dunia (Total: 47.7 miliar dolar AS; ODA: 0%) |
0,00 |
47,66 |
N/A |
Catatan: Seluruh angka disajikan dalam miliar dolar AS konstan tahun
2024. Tim peneliti melengkapi data pembiayaan RRT dengan riset
tambahan terbatas dan tinjauan artikel media untuk mengidentifikasi
proyek serta rincian tambahan pada tahun 2022 dan 2023. Data untuk dua
tahun terakhir ini sebaiknya diperlakukan sebagai data sementara.
Sumber:
OECD CRS Database, 2000–2023 dan AidData’s Global Chinese
Development Finance Dataset, Versi 3.0 untuk periode 2000–2021
(Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022).
2.1.1.2 Perbandingan tren bantuan Beijing dengan pihak lain
Beijing tidak selalu berada di posisi teratas dalam pembangunan Indonesia (lihat Gambar 2.3). Sebelum krisis keuangan global 2008, pembiayaan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sekitar 7,3 miliar dolar AS, masih setara dengan kontribusi lembaga multilateral seperti ADB (6,9 miliar dolar AS) dan Bank Dunia (5,3 miliar dolar AS) dalam komitmen yang tercatat antara 2000 hingga 2007. Saat itu, ketiganya masih jauh tertinggal dari mitra pembangunan utama Indonesia, yakni Jepang, yang mencatat komitmen hingga 13,3 miliar dolar AS. Ada dua pengecualian menarik pada periode ini, yaitu di tahun 2003 dan 2006, ketika pembiayaan pembangunan Tiongkok melonjak sementara dan membuat Beijing menjadi donor terbesar Indonesia pada tahun-tahun tersebut.
Situasi berubah drastis setelah 2008. RRT melesat menjadi penyedia pembiayaan pembangunan terbesar bagi Indonesia, mempertahankan posisi itu dari 2011 hingga 2018. Namun, selama pandemi COVID-19, [17] pembiayaan dari Tiongkok menurun tajam, mengikuti tren penurunan pinjaman secara global. Dalam periode tersebut, peran lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan ADB kembali mencuat, mengucurkan ratusan juta dolar untuk memperkuat infrastruktur kesehatan (lihat Gambar 2.3).
Memasuki 2023, tanda-tanda peningkatan mulai terlihat. Berdasarkan tinjauan awal proyek-proyek yang diumumkan, Beijing berencana menggelontorkan sekitar 4,2 miliar dolar AS untuk 18 proyek di sektor energi dan industri. [18] Meski terdengar menjanjikan, belum ada kepastian bahwa seluruh rencana ini akan terwujud. Kasus proyek Kayan Cascade menjadi contoh nyata: PowerChina sempat mengumumkan pendanaan senilai 17,8 miliar dolar AS untuk proyek tersebut, namun akhirnya mundur, menjadikan pengumuman awalnya lebih sebagai sensasi ketimbang komitmen nyata ( Koswaraputra , 2024). [19]
Gambar 2.2: Total komitmen pembiayaan resmi dari Tiongkok ke Indonesia, 2000–2023
Catatan: Seluruh angka disajikan dalam satuan miliar dolar AS konstan
tahun 2024. Tim peneliti melengkapi data pembiayaan RRT dengan riset
tambahan terbatas dan peninjauan artikel media untuk mengidentifikasi
proyek-proyek serta rincian tambahan pada tahun 2022 dan 2023. Data
untuk kedua tahun tersebut sebaiknya dianggap sebagai data
sementara.
Sumber: AidData’s Global Chinese Development
Finance Dataset, Versi 3.0 untuk periode 2000–2021 (Custer et
al., 2023; Dreher et al., 2022).
Gambar 2.3: Komitmen pembiayaan resmi per tahun dari mitra pembangunan utama kepada Indonesia, 2000–2023
Catatan: Tim peneliti melengkapi data pembiayaan RRT dengan riset
tambahan terbatas dan peninjauan artikel media untuk mengidentifikasi
proyek-proyek serta rincian tambahan pada tahun 2022 dan 2023. Data
untuk kedua tahun tersebut sebaiknya diperlakukan sebagai data
sementara.
Sumber: OECD CRS Database, 2000–2023 dan
AidData’s Global Chinese Development Finance Dataset, Versi 3.0
untuk periode 2000–2021 (Custer et al., 2023; Dreher et al.,
2022).
2.1.1.3 Perbandingan fokus sektoral Beijing dengan pihak lain
Selama lebih dari dua dekade, pembiayaan pembangunan Tiongkok untuk Indonesia konsisten diarahkan pada tiga prioritas utama: mengamankan pasokan sumber daya alam, memperluas kapasitas industri, serta memperkuat konektivitas fisik dan digital.
Di sektor energi, Tiongkok telah mengucurkan sekitar 20,12 miliar dolar AS untuk 56 proyek. Pada awalnya, investasi ini banyak berfokus pada pembangkit listrik tenaga batu bara, sebelum kemudian bergeser dan meluas ke proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air.
Di sektor industri, pertambangan, dan konstruksi, nilai investasi mencapai 17,44 miliar dolar AS untuk 65 proyek. Tujuannya jelas: membuka jalan dan mengurangi hambatan bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia.
Sektor transportasi dan pergudangan juga menjadi fokus penting, dengan total investasi sekitar 9,38 miliar dolar AS untuk 37 proyek, mulai dari pembangunan kereta cepat hingga jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi.
Jika digabungkan, ketiga sektor ini menyerap lebih dari 70 persen dari total pembiayaan pembangunan Tiongkok ke Indonesia sepanjang 2000 hingga 2023 (lihat Tabel 2.4). [20]
Tabel 2.4: Sepuluh sektor utama proyek pembangunan yang didanai RRT di Indonesia, 2000–2023
Per juta dolar AS |
Per jumlah proyek |
|||
Energi |
20.122 |
Industri, pertambangan, dan konstruksi |
65 |
|
|
Industri, pertambangan, dan konstruksi |
17.441 |
Energi |
56 |
|
Transportasi dan pergudangan |
9.378 |
Emergency response |
47 |
|
Multisektor lain |
5.837 |
Jasa bisnis dan jasa lain |
42 |
|
Komunikasi |
4.314 |
Transportasi dan pergudangan |
37 |
|
|
Tidak dialokasikan / tidak ditentukan |
1.888 |
Tidak dialokasikan / tidak ditentukan |
32 |
|
Jasa bisnis dan jasa lain |
1.614 |
Pendidikan |
28 |
|
Perbankan dan jasa keuangan |
1.029 |
Komunikasi |
21 |
|
|
Pertanian, kehutanan, dan perikanan |
615 |
Kesehatan |
20 |
|
|
Kebijakan dan regulasi perdagangan |
590 |
Tindakan terkait utang |
16 |
Catatan: Tabel ini menunjukkan 10 sektor teratas dari proyek pembangunan
yang didanai RRT pada periode 2000 hingga 2023 (mencakup bantuan dan
instrumen utang) dalam jutaan dolar AS konstan tahun 2024 (kiri) dan
jumlah proyek (kanan). Tim peneliti melengkapi data pembiayaan RRT
dengan riset tambahan terbatas dan peninjauan artikel media untuk
mengidentifikasi proyek serta rincian tambahan pada tahun 2022 dan 2023.
Data untuk dua tahun terakhir ini sebaiknya diperlakukan sebagai data
sementara. Kategori “Tidak dialokasikan/tidak ditentukan”
mengindikasikan kurangnya rincian untuk menetapkan sektor proyek.
Sumber:
AidData’s Global Chinese Development Finance Dataset, Versi 3.0
untuk periode 2000–2021 (Custer et al., 2023; Dreher et al.,
2022).
Di panggung global, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menerapkan model pembangunan “dua jalur”: di satu sisi menanamkan investasi besar pada infrastruktur yang diharapkan memberi imbal hasil komersial, di sisi lain membiayai proyek-proyek goodwill bernilai kecil untuk membangun reputasi (Custer et al., 2025). Pola ini juga terlihat jelas di Indonesia.
Beijing tidak hanya menggelontorkan dana untuk proyek-proyek besar, tapi juga mengirimkan bantuan pangan, tim pencarian dan penyelamatan, serta tenaga medis untuk membantu Indonesia menghadapi bencana alam. Kategori tanggap darurat ini menjadi yang ketiga terbanyak dalam jumlah proyek, meskipun sebagian besar terkonsentrasi pada peristiwa gempa bumi dan tsunami Desember 2004. [21] Meski dana yang dialokasikan biasanya lebih kecil dibandingkan mitra pembangunan lain, Tiongkok tetap berkontribusi pada sektor sosial, termasuk melalui 28 proyek pendidikan dan 20 proyek kesehatan.
Meski kerap dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur, terutama karena dominasi narasi Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI), istilah “infrastruktur” di sini mencakup banyak aspek penting bagi pertumbuhan dan kesejahteraan suatu negara. Dalam laporan ini, kami menelusuri sejauh mana kontribusi Beijing terhadap pengembangan infrastruktur Indonesia di berbagai bidang, jika dibandingkan dengan mitra pembangunan lain:
- Infrastruktur ekonomi dan informasi (perbankan, jasa keuangan, jasa bisnis, telekomunikasi, infrastruktur dan layanan ekonomi)
- Infrastruktur konektivitas fisik (kebijakan dan regulasi perdagangan, transportasi, pergudangan)
- Infrastruktur utilitas, pangan, dan energi (pertanian, kehutanan, perikanan, energi, industri, pertambangan, konstruksi, sektor produksi, penyediaan air bersih dan sanitasi)
- Infrastruktur sosial dan lingkungan (pendidikan, perlindungan lingkungan, pemerintahan dan masyarakat sipil, kesehatan, layanan sosial, kebijakan dan program kependudukan, kesehatan reproduksi)
Jika melihat polanya, Korea Selatan (92 persen), Tiongkok (76 persen), dan Jepang (56 persen) menunjukkan preferensi kuat pada infrastruktur keras seperti konektivitas fisik, utilitas, pangan, dan energi. Sebaliknya, Australia dan Amerika Serikat justru menempatkan lebih dari setengah portofolio pembiayaan pembangunan mereka (masing-masing 58 persen) untuk mendukung infrastruktur sosial dan lingkungan di Indonesia.
Tabel 2.5: Total Komitmen Pembiayaan Resmi dari Mitra Pembangunan Utama kepada Indonesia Berdasarkan Sektor, 2000–2023
Tabel dapat diurutkan dengan mengeklik kolom. Pada layar kecil, gulir secara horizontal untuk melihat kolom tersembunyi.
Sektor |
RRT |
ADB |
Australia |
Bank Dunia |
Jepang |
Korea Selatan |
AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pengurangan risiko bencana, tanggap darurat |
0,08 |
0,00 |
0,36 |
0,28 |
0,61 |
0,02 |
1,42 |
|
Infrastruktur ekonomi dan informasi |
6,96 |
5,68 |
0,12 |
6,65 |
0,08 |
0,55 |
0,15 |
|
Infrastruktur konektivitas fisik |
9,97 |
1,75 |
0,79 |
3,31 |
7,81 |
1,92 |
0,15 |
|
Infrastruktur sosial dan lingkungan |
0,43 |
14,53 |
5,95 |
23,71 |
2,72 |
0,64 |
4,60 |
|
Infrastruktur utilitas, pangan, dan energi |
42,88 |
10,98 |
1,08 |
8,92 |
8,58 |
12,44 |
0,51 |
Lainnya |
9,30 |
3,71 |
2,00 |
4,79 |
9,54 |
0,11 |
1,13 |
Catatan: Komitmen dinyatakan dalam miliar dolar AS konstan tahun 2024.
Warna yang lebih gelap menunjukkan volume pembiayaan yang lebih tinggi
dari donor tertentu pada suatu sektor. Tim peneliti melengkapi data
pembiayaan RRT dengan riset tambahan terbatas dan peninjauan artikel
media untuk mengidentifikasi proyek serta rincian tambahan pada tahun
2022 dan 2023. Data untuk dua tahun terakhir ini sebaiknya
diperlakukan sebagai data sementara.
Sumber: OECD CRS Database
2000–2023 dan AidData’s Global Chinese Development Finance
Dataset, Versi 3.0 untuk periode 2000–2021 (Custer et al., 2023;
Dreher et al., 2022).
Tidak mengherankan, Amerika Serikat—yang secara historis dikenal sebagai penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di dunia (Custer et al., 2025)—mengalokasikan porsi yang lebih besar dari portofolio pembiayaannya untuk dana pengurangan risiko dan tanggap darurat. Proporsinya mencapai 18 persen, lebih tinggi dibandingkan donor lain.
Dua bank pembangunan multilateral, yakni Bank Dunia ( World Bank / WB) dan Asian Development Bank (ADB), berada di posisi tengah. Proyek infrastruktur keras masih menyumbang seperempat hingga sepertiga dari total pembiayaan mereka di Indonesia. Sama seperti RRT, kedua lembaga ini juga menunjukkan minat besar pada proyek-proyek di bidang ekonomi dan informasi. Namun, Bank Dunia (50 persen) dan ADB (40 persen) jauh lebih aktif daripada Tiongkok dalam mendukung pembangunan infrastruktur sosial dan lingkungan di Indonesia. Sebagai gambaran, antara 2002 hingga 2023, Bank Dunia mengalokasikan sekitar 23,71 miliar dolar AS untuk sektor ini—jumlah yang 54 kali lipat lebih besar daripada kontribusi Tiongkok yang hanya mencapai 430 juta dolar AS.
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) juga turut berperan, terutama di masa pandemi COVID-19. Sebagai bagian dari paket penyelamatan, AIIB menyalurkan pinjaman senilai 1,5 miliar dolar AS kepada Indonesia, [22] bekerja sama dengan ADB dan Bank Dunia dalam kerangka inisiatif dukungan COVID-19 yang lebih luas. Secara keseluruhan, sepanjang 2020 hingga 2024, Indonesia menerima lebih dari 4,19 miliar dolar AS dari AIIB, dengan proyek yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari energi, layanan kesehatan, hingga komunikasi satelit. [23]
2.1.2 Bagaimana variasi aliran pembiayaan pembangunan Tiongkok di Kawasan ASEAN?
Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia menonjol sebagai penerima terbesar pembiayaan pembangunan dari Beijing antara 2000 hingga 2021. Minat global Tiongkok dalam menggunakan pembiayaan pembangunan untuk membuka pasar baru bagi perusahaan-perusahaannya tampaknya menjadi salah satu alasan kuat di balik ketertarikan terhadap Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara sekaligus simpul penting konektivitas kawasan. Komposisi sektor pembiayaan yang mengalir ke transportasi, energi, dan industri ekstraktif sejalan dengan kepentingan Beijing dalam mengamankan pasokan energi dan mineral, sekaligus mencerminkan prioritas pembangunan nasional Indonesia.
Indonesia juga menjadi mitra utama Tiongkok dalam mewujudkan ambisi infrastruktur kawasan lewat inisiatif Belt and Road (BRI). Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung bahkan menjadi proyek BRI terbesar di ASEAN. Selain itu, Indonesia menjadi tuan rumah bagi proyek-proyek lain yang didukung Beijing, mulai dari jaringan digital, pelabuhan, hingga industri ekstraktif. Semua ini merupakan bagian dari strategi Digital Silk Road Tiongkok untuk memperluas infrastruktur data dan platform e-commerce di kawasan (Rakhmat, 2022). Upaya tersebut dibiayai lewat berbagai instrumen, termasuk pinjaman konsesional dan pinjaman komersial dari China Development Bank dan China Eximbank.
Lebih luasnya, variasi portofolio pembiayaan pembangunan Beijing di ASEAN dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Dari sisi permintaan, prioritas pembangunan dan kerangka regulasi suatu negara bisa membuat kerja sama dengan Tiongkok lebih atau kurang menarik bagi anggota ASEAN. Dari sisi penawaran, Beijing juga menilai sejauh mana suatu negara memiliki nilai geostrategis dan keselarasan diplomatik dengan kebijakan luar negerinya sebelum mengucurkan pembiayaan.
Di Asia Tenggara daratan, Laos (23,8 miliar dolar AS, 306 proyek) dan Kamboja (19,8 miliar dolar AS, 369 proyek) juga menjadi penerima utama dana pembangunan Tiongkok dalam dua dekade terakhir. Meski ekonominya jauh lebih kecil, kedua negara ini memiliki hubungan politik yang erat dengan Beijing dan aktif dalam kerangka kerja BRI. Portofolio infrastruktur mereka mencakup koridor transportasi berskala besar, pembangkit listrik, dan proyek tenaga air, sebagian besar dibiayai melalui pinjaman bank kebijakan Tiongkok. Menariknya, aliran dana ini biasanya tidak disertai syarat kebijakan yang ketat, sesuatu yang membedakannya dari pembiayaan pembangunan multilateral.
Vietnam (32,4 miliar dolar AS, 178 proyek) dan Malaysia (17,9 miliar dolar AS, 162 proyek) mengambil pendekatan yang lebih selektif dan hati-hati. Keduanya memanfaatkan modal Tiongkok untuk membiayai proyek strategis, namun tetap menekankan uji kelayakan regulasi dan kerap menegosiasikan ulang ketentuan pembiayaan agar selaras dengan prioritas politik dan fiskal dalam negeri. Vietnam, meski menjadi penerima kedua terbesar dari sisi nilai proyek, masih tertinggal dalam pelaksanaan dibandingkan negara-negara Mekong—sebagian karena skeptisisme Hanoi terhadap hubungan yang terlalu erat dengan Beijing (Ha, 2022). Faktor sejarah dan sengketa maritim di Laut China Selatan membuat Vietnam berhati-hati, terutama di sektor-sektor yang sensitif secara politik. Malaysia pun menerapkan strategi serupa, termasuk dengan merestrukturisasi sejumlah proyek besar BRI seperti East Coast Rail Link.
Tabel 2.6: Total komitmen pembiayaan pembangunan RRT ke negara-negara ASEAN, 2000–2021
Negara |
Komitmen (dolar AS 2024) |
Jumlah proyek |
Indonesia |
61,7 miliar |
400 |
Vietnam |
32,4 miliar |
178 |
Laos |
23,8 miliar |
306 |
Kamboja |
19,8 miliar |
369 |
Malaysia |
17,9 miliar |
162 |
Myanmar |
16,3 miliar |
444 |
Filipina |
9,1 miliar |
219 |
Thailand |
5,8 miliar |
99 |
Brunei Darussalam |
2,4 miliar |
51 |
Catatan: Data pembiayaan pembangunan Tiongkok yang dapat dibandingkan
antarnegara hanya tersedia hingga tahun 2021, sehingga total nilai
komitmen RRT kepada Indonesia dalam bagian ini lebih rendah
dibandingkan bagian lain dalam laporan yang mencakup hingga tahun
2023.
Sumber: AidData's Global Chinese Development Finance
Dataset, Versi 3.0
Jika dibandingkan dengan Indonesia, volume pembiayaan pembangunan Tiongkok yang diterima Filipina dan Thailand jauh lebih kecil—masing-masing sekitar 9,1 miliar dolar AS untuk 219 proyek dan 5,8 miliar dolar AS untuk 99 proyek.
Di Filipina, pergantian kepemimpinan politik dan perubahan arah kebijakan luar negeri terbukti berpengaruh besar pada arus investasi (Custer et al., 2024). Di era Presiden Rodrigo Duterte, hubungan diplomatik yang lebih hangat dengan Beijing memicu lonjakan jumlah proyek yang disetujui. Namun, tidak sedikit dari proyek tersebut yang kemudian tersendat atau mengalami keterlambatan pencairan dana.
Thailand mengambil jalur berbeda. Sebagai negara berpendapatan menengah dengan perekonomian yang relatif matang dan sumber investasi yang beragam, Negeri Gajah Putih memilih menjaga portofolio proyek pembiayaan Tiongkok dalam skala yang lebih konservatif. Modal dari Beijing berfungsi sebagai pelengkap, bukan sebagai tumpuan utama bagi pembangunan nasionalnya.
2.2 Bagaimana variasi pembiayaan Beijing di bawah tiap pemerintahan?
Pembiayaan pembangunan dari Beijing ke Indonesia menunjukkan pola yang naik-turun di bawah setiap pemerintahan presiden. Pada era Megawati Soekarnoputri (2000–2004), jumlahnya meningkat secara bertahap. Memasuki masa Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014), fluktuasinya menjadi lebih tajam. Rekor tertinggi terjadi di masa jabatan pertama Joko Widodo (2014–2019), sebelum turun cukup drastis selama dan setelah pandemi COVID-19 (2019–2024) (lihat Gambar 2.2). Jumlah proyek pun ikut berfluktuasi, baik antarperiode maupun di dalam satu periode kepemimpinan yang sama (Gambar 2.7).
Jika dilihat secara keseluruhan, pola ini tidak membentuk tren kenaikan yang lurus. Ada masa-masa ekspansi strategis, ketika Beijing secara oportunistis menyesuaikan diri dengan prioritas pemimpin Indonesia, diikuti periode penyesuaian ulang yang cukup signifikan. Lonjakan proyek dan investasi kadang bertepatan dengan momen diplomatik besar seperti kunjungan kenegaraan atau pertemuan bilateral tingkat tinggi, meski tidak selalu demikian. Menariknya, investasi dari Tiongkok tidak serta-merta meningkat saat Indonesia memimpin ASEAN pada 2011 atau menjadi tuan rumah KTT ke-18 dan ke-19.
Penurunan volume pembiayaan negara dari Tiongkok ke Indonesia antara 2019 dan 2022 sejalan dengan tren global yang dicatat AidData, di mana Beijing mulai memfokuskan dana pada pembiayaan darurat untuk negara-negara mitra BRI yang kesulitan membayar utang (Parks et al., 2023). Meski nilai pembiayaan turun cukup tajam, jumlah proyeknya tidak mengalami penurunan sebesar itu. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya pergeseran fokus ke proyek-proyek goodwill yang kecil namun berdampak besar (small but beautiful), sembari mendorong keterlibatan lebih besar dari sektor swasta, termasuk dari Hong Kong (Yeung, 2024). [24]
Tren penurunan ini juga bisa mencerminkan meningkatnya kehati-hatian dalam negeri terhadap pembiayaan Tiongkok, perubahan prioritas politik nasional, dan kekhawatiran global yang lebih luas mengenai keberlanjutan utang.
Gambar 2.7: Proyek pembangunan yang didanai RRT di Indonesia, 2000–2023
Catatan: Tim peneliti melengkapi data pembiayaan RRT dengan riset
tambahan terbatas dan peninjauan artikel media untuk mengidentifikasi
proyek serta rincian tambahan pada tahun 2022 dan 2023. Data untuk
kedua tahun ini sebaiknya diperlakukan sebagai data sementara.
Sumber:
AidData’s Global Chinese Development Finance Dataset, Versi 3.0
untuk periode 2000–2021 (Custer et al., 2023; Dreher et al.,
2022).
Tabel 2.8: Tren utama proyek pembangunan yang didanai RRT berdasarkan pemerintahan di Indonesia
Pemerintahan |
Tren |
Contoh proyek |
|
Megawati Soekarnoputri (2001-2004) |
Proyek energi dan infrastruktur |
Proyek Gas Alam Cair Tangguh dan Jembatan Suramadu |
|
Susilo Bambang Yudhoyono, |
Bantuan bencana dan proyek energi |
Tsunami Samudra Hindia 2004 dan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW I |
|
Susilo Bambang Yudhoyono, |
Diversifikasi ke industri strategis, telekomunikasi, dan pembiayaan sektor swasta |
Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW II dan Palapa Ring |
|
Joko Widodo, |
Transportasi dan infrastruktur, energi, serta pembiayaan BUMN |
Kereta Cepat Jakarta–Bandung |
|
Joko Widodo, |
Pemulihan pasca-COVID-19 serta industri dan investasi hilirisasi |
Kawasan Industri Morowali |
2.2.1 Abdurrahman Wahid (1999–2001)
Satu dekade setelah hubungan diplomatik Indonesia–Tiongkok kembali terjalin, Presiden Abdurrahman Wahid menempatkan stabilitas dan rekonsiliasi sebagai inti pendekatannya terhadap Beijing. Pemerintahannya membuka jalan bagi normalisasi hubungan kedua negara, termasuk mencabut berbagai pembatasan yang selama ini membatasi komunitas Tionghoa-Indonesia dalam menjalankan tradisi keagamaan, budaya, dan bahasa, seperti perayaan Tahun Baru Imlek. Wahid juga secara resmi mengakui Konfusianisme sebagai agama, dan mengangkat ekonom Tionghoa-Indonesia, Kwik Kian Gie, sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sebuah langkah simbolis yang kuat dalam mendorong inklusivitas.Walau keterlibatan ekonomi langsung dengan Beijing pada masa itu masih terbatas, kebijakan Wahid meletakkan fondasi penting bagi kerja sama bilateral yang lebih erat di masa depan.
Masa jabatannya memang singkat, hanya 21 bulan, tetapi ia memanfaatkannya dengan aktif di panggung diplomasi. Hampir seperempat waktunya dihabiskan untuk kunjungan kenegaraan, [25] dan Tiongkok menjadi negara pertama yang ia sambangi pada 1999. Kunjungan ini menghasilkan Komunike Bersama [26] yang menegaskan niat memperkuat hubungan.
Krisis Keuangan Asia 1997 memberi peluang bagi Tiongkok untuk mengubah pemulihan hubungan diplomatik menjadi dukungan nyata, meski sebagian besar disalurkan melalui jalur multilateral ketimbang bilateral. Sebagai tanda itikad baik, Beijing mengucurkan pinjaman siaga sebesar 400 juta dolar AS dalam paket penyelamatan IMF untuk Indonesia, fasilitas kredit ekspor senilai 200 juta dolar AS, hibah obat-obatan senilai 3 juta dolar AS, dan 50.000 ton beras. [27] Dukungan ini membantu membangun citra positif Tiongkok di mata publik Indonesia (Sukma, 2009).
Meski begitu, pembiayaan pembangunan langsung dari Beijing pada periode ini tetap relatif kecil, kemungkinan dipengaruhi oleh sensitivitas politik pasca-kerusuhan 1998, yang dampaknya dirasakan secara tidak proporsional oleh warga Tionghoa-Indonesia.
2.2.2 Megawati Soekarnoputri (2001–2004)
Menggantikan Abdurrahman Wahid pasca pemakzulan pada 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri melanjutkan proses normalisasi hubungan Indonesia–Tiongkok secara bertahap. Pemerintahannya secara resmi menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Hubungan dagang dan investasi pun tumbuh stabil, dengan nilai perdagangan kedua negara mencapai 8,7 miliar dolar AS pada 2004, [28] hampir setara dengan volume perdagangan Indonesia–Amerika Serikat di tahun yang sama (Badan Pusat Statistik, 2025).
Dukungan Tiongkok kepada Indonesia di masa ini tidak hanya berbentuk kerja sama ekonomi. Beijing mengirim bantuan kemanusiaan pasca Bom Bali 2002, gempa bumi di Nabire, dan wabah flu, bahkan menyumbangkan sepeda motor untuk Kepolisian RI pada 2003. Namun, sebagian besar pembiayaan pembangunan dari Tiongkok, sekitar 2,18 miliar dolar AS, tetap berfokus pada proyek infrastruktur keras dengan tujuan pengembalian komersial. [29]
Masa pemerintahan Megawati menandai pergeseran dari pendekatan simbolis ke strategi yang lebih terarah dan sektoral dalam pembiayaan pembangunan RRT. Dana mulai diarahkan untuk kerja sama ekonomi jangka panjang, terutama di sektor energi dan infrastruktur. Meski nilainya masih jauh dibawah periode-periode berikutnya, dukungan finansial Tiongkok di era ini mencerminkan kesediaan mereka berinvestasi dalam agenda pemulihan dan pembangunan pasca-krisis Indonesia.
Sektor energi menjadi pilar utama. Dorongannya datang dari meningkatnya kebutuhan energi Tiongkok, yang sejak 1993 telah menjadi importir bersih produk minyak dan sejak 1996 importir minyak mentah. China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) bahkan menjadi produsen minyak lepas pantai terbesar di Indonesia setelah mengakuisisi lima aset minyak dan gas milik Repsol-YPF Group senilai 585 juta dolar AS (Offshore Magazine, 2002). [30] Pemerintah Indonesia pun aktif menjajaki kontrak ekspor energi jangka panjang, termasuk melalui pembicaraan langsung dengan Perdana Menteri Zhu Rongji (Tempo, 2002).
Dalam kunjungan kenegaraan Megawati ke Beijing pada Maret 2002, Presiden Jiang Zemin menjanjikan hibah senilai 6 juta dolar AS dan pinjaman lunak sebesar 400 juta dolar AS [31] untuk membangun jaringan kereta api di Jawa Timur dan Jawa Barat (Liputan 6, 2002). Kunjungan ini juga menghasilkan kesepakatan kerja sama antara Pertamina dan PetroChina (Weaver, 2002), sekaligus membuka jalan bagi Forum Energi Indonesia–Tiongkok pertama di tahun yang sama. Dari forum tersebut lahir kontrak ekspor LNG senilai 8,5 miliar dolar AS selama 25 tahun dari Blok Tangguh Indonesia ke Provinsi Fujian, Tiongkok (People’s Daily, 2002). [32]
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral saat itu menyebut kontrak LNG ini sebagai “proyek terbesar sejak era Orde Baru,” menandakan betapa pentingnya kesepakatan tersebut bagi pemulihan ekonomi pasca-krisis (People’s Daily, 2002). Meski begitu, pemerintahan-pemerintahan setelahnya mengkritik dan berupaya menegosiasikan ulang kontrak ini karena dianggap merugikan Indonesia (Oster, 2006; Detik, 2008; Cahyafitri, 2014; Kementerian ESDM, 2014). Megawati membela perjanjian tersebut dengan alasan bahwa kesepakatan ini membuka jalan bagi investasi Tiongkok yang lebih besar di sektor infrastruktur dan peningkatan kapasitas pemrosesan domestik.
Selain sektor energi, Beijing juga membiayai proyek infrastruktur unggulan Jembatan Surabaya–Madura (Suramadu) dengan total dana 575,5 juta dolar AS melalui dua skema kredit pembeli preferensial dari China Eximbank. Dengan biaya sekitar 4,5 triliun rupiah (setara 466,6 juta dolar AS saat ini) dan panjang 5.400 meter, Suramadu menjadi salah satu proyek infrastruktur paling ambisius di masanya. Proyek ini tidak hanya menjadi tonggak penting hubungan Indonesia–Tiongkok, tetapi juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk meningkatkan konektivitas antarpulau (The Jakarta Post, 2009).
2.2.3 Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014)
Kurang dari dua bulan setelah dilantik pada 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dihadapkan pada bencana dahsyat: gempa bumi dan tsunami berkekuatan 9,3 magnitudo yang melanda Aceh dan Nias di Sumatra Utara. Operasi bantuan menjadi rumit karena kekhawatiran terhadap kehadiran warga asing di Aceh, wilayah konflik yang saat itu masih berada dalam ketegangan antara militer Indonesia dan gerakan separatis (Fox News, 2005). Meski begitu, Yudhoyono membuka pintu bagi bantuan internasional, keputusan yang kemudian ia sebut ikut memuluskan jalan menuju perjanjian damai yang mengakhiri konflik selama 30 tahun (Yudhoyono, 2025).
Tiongkok merespons cepat. Awalnya, Beijing menyalurkan bantuan senilai 2,6 juta dolar AS untuk negara-negara terdampak tsunami, sebelum Perdana Menteri Wen Jiabao meningkatkan komitmen menjadi 60 juta dolar AS untuk bantuan darurat dan rekonstruksi di negara-negara ASEAN. [33] Saat kunjungan kenegaraan ke Jakarta, Presiden Tiongkok Hu Jintao menaikkan status hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis (Qin, 2005), menjanjikan tambahan bantuan 3,63 juta dolar AS, serta pinjaman 300 juta dolar AS untuk membangun infrastruktur dan mendukung rekonstruksi wilayah terdampak tsunami (China Daily, 2005). [34][35] Bantuan bencana dari Beijing juga mengalir untuk merespons gempa di Alor (2004), Nabire (2005), dan Yogyakarta (2006).
Dari titik awal kerja sama kemanusiaan ini, hubungan Indonesia–Tiongkok di era Yudhoyono berkembang menjadi kemitraan ekonomi yang lebih mendalam. Perdagangan bilateral meningkat, bergeser dari ekspor bahan mentah menuju investasi di sektor pengolahan sumber daya alam dalam negeri. Periode ini bahkan kerap disebut sebagai fase “bulan madu” (The Jakarta Post, 2008). Modal Tiongkok mengalir tidak hanya ke proyek pemerintah, tetapi juga ke sektor swasta, mulai dari pertambangan hingga produksi barang konsumsi.
Meski jumlah pembiayaan pembangunan dari Beijing masih di bawah Korea Selatan dan Jepang, Tiongkok mengarahkan investasinya ke prioritas strategis Indonesia, seperti industri, transportasi, telekomunikasi, dan terutama energi. Sejalan dengan peta jalan pembangunan nasional 20 tahun Yudhoyono, [36] sebagian besar pembiayaan diarahkan untuk memperluas infrastruktur energi, termasuk transisi pembangkit listrik dari minyak ke batu bara—guna membantu PLN mengatasi kendala rantai pasok dan biaya produksi tinggi (Sambodo dan Oyama, 2010; Ali dan Wulandari, 2008). [37]
Pada 2006, Yudhoyono menandatangani Nota Kesepahaman senilai 3,56 miliar dolar AS dalam Forum Energi Indonesia–Tiongkok di Shanghai (Detik, 2006; Antara, 2006). [38] Kebijakan energinya bertumpu pada Program Percepatan Pembangkit Listrik 10.000 MW ( Fast Track Program / FTP), [39] yang mencakup 10 proyek pembangkit di Jawa (7.430 MW) dan 25 di luar Jawa (2.121 MW), dengan biaya sekitar 98,1 triliun rupiah. [40]
PLN menanggung 15 persen dari total biaya, sisanya berasal dari pinjaman luar negeri (MEMR, 2008). Tiongkok bergerak cepat, menawarkan pendanaan besar untuk mendukung 22 proyek pada fase pertama FTP, hampir 90 persen di antaranya dibiayai dari Beijing (Detik, 2009; Kompas, 2009).
Pada 2009, bersamaan dengan peresmian Jembatan Suramadu, Yudhoyono mengumumkan tambahan pendanaan 761 juta dolar AS dari Tiongkok [41] untuk proyek PLN. Komitmen ini mencakup 468 juta dolar AS [42] dari China Development Bank untuk PLTU Adipala di Cilacap, dan 293 juta dolar AS [43] dari China Eximbank untuk PLTU Pacitan (Alfian, 2009).
Fokus pada energi berlanjut di periode kedua Yudhoyono. Ia memperoleh 3,6 miliar dolar AS pembiayaan Tiongkok untuk 10 proyek, termasuk pinjaman 883 juta dolar AS [44] untuk perluasan kedua PLTU Cilacap (660 MW) dan 147,6 juta dolar AS untuk Bendungan PLTA Jatigede (110 MW) dari China Eximbank. [45] Sebagian proyek diarahkan untuk kebutuhan industri tertentu ( captive power ), seperti PLTU untuk kawasan industri di Morowali.
Kerja sama juga merambah sektor pengolahan dan manufaktur. Pada 2013, China Development Bank memberikan pinjaman 2,3 miliar dolar AS kepada PT OKI Pulp and Paper Mills, anak perusahaan Asia Pulp and Paper, untuk membangun salah satu pabrik kertas terbesar di Indonesia (Antara, 2013). [46] Pinjaman ini merupakan bagian dari hampir 20 perjanjian yang ditandatangani saat kunjungan Presiden Xi Jinping ke Indonesia pada tahun 2013, [47] senilai total 28,2 miliar dolar AS. [48] Bidang kerja sama meliputi pengolahan mineral kritis, transportasi, telekomunikasi, pelatihan SDM, perbankan, dan perkebunan.
Konektivitas digital juga menjadi fokus. Pinjaman buyer’s credit membiayai akuisisi peralatan dan layanan dari ZTE dan Huawei untuk perusahaan seperti Axis, Smart Telecom, Indosat, dan Telkom Indonesia. Prioritas ini sejalan dengan target Yudhoyono untuk menghubungkan seluruh desa di Indonesia ke internet pada 2010, melalui program Desa Internet, Desa Berdering, dan Palapa Ring.
Pasca keberhasilan Suramadu, investasi Tiongkok di infrastruktur transportasi dan logistik semakin beragam, jalan tol, rel kereta, dan jembatan. Pinjaman usaha pun melonjak, dengan 36 kesepakatan bernilai hampir 1 miliar dolar AS, [49] termasuk untuk Merpati Airlines yang membeli 15 pesawat MA60 dari Xi’an Aircraft. Namun, kesulitan membayar utang membuat maskapai ini bangkrut pada 2014.
Hubungan bilateral mencapai puncaknya di akhir masa Yudhoyono. Kunjungan kenegaraan Presiden Xi pada 2013 menjadi momen bersejarah, ditandai dengan pidato di parlemen Indonesia yang mengumumkan “Jalur Sutra Maritim Abad ke-21,” pendirian Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan penandatanganan Kemitraan Strategis Komprehensif. Selain proyek besar, Beijing juga membiayai program goodwill seperti kursus bahasa Mandarin, pendirian Institut Konfusius di enam universitas, dan beasiswa pelajar Indonesia ke Tiongkok.
Namun, hubungan ini tidak lepas dari masalah. Ada keterlambatan pencairan dana, yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan proyek, [50] isu utang dalam dolar AS yang berpotensi membebani keuangan negara, [51] serta kontroversi di proyek-proyek energi seperti PLTU Parit Baru dan PLTU Celukan Bawang karena persoalan tenaga kerja dan lingkungan. Kasus besar juga terjadi di proyek pinjaman sindikasi Krakatau Steel, yang mengalami pembengkakan biaya dan dinyatakan tidak layak hanya enam bulan setelah selesai, berujung pada penangkapan sejumlah eksekutif senior [52] dan kerugian negara 6,9 triliun rupiah (Tempo, 2022). [53]
2.2.4 Joko Widodo (2014–2024)
Ketika mulai menjabat pada 2014, Presiden Joko Widodo mewarisi hubungan Indonesia–Tiongkok yang tengah berada pada tren positif. Setahun sebelumnya, kedua negara telah menandatangani Kemitraan Strategis Komprehensif, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping memilih Jakarta sebagai lokasi peluncuran Prakarsa Sabuk dan Jalan ( Belt and Road Initiative / BRI) serta Bank Investasi Infrastruktur Asia ( Asian Infrastructure Investment Bank / AIIB). Meski begitu, kerja sama ini tetap dibayangi sengketa maritim, terutama terkait hak penangkapan ikan di sekitar Kepulauan Natuna (Lalisang dan Candra, 2020).
Pendekatan Widodo terhadap Beijing bersifat pragmatis: melihat Tiongkok sebagai mitra strategis yang dapat membantu mewujudkan ambisi pembangunan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Gagasannya untuk menempatkan Indonesia sebagai simpul utama perdagangan dan keamanan maritim global ia wujudkan melalui konsep “Poros Maritim Dunia” ( Global Maritime Fulcrum / GMF).
Pemerintahannya menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama agenda sembilan poin presiden atau NawaCita. [54] Program ini mencakup pengembangan sistem transportasi massal terintegrasi, laut, udara, dan darat, untuk memperkuat konektivitas nasional. Pada 2018, Indonesia dan Tiongkok menandatangani Nota Kesepahaman ( Memorandum of Understanding / MoU) yang menggabungkan unsur BRI dan GMF dalam kerja sama infrastruktur maritim dan logistik. Tujuannya adalah memperkuat konektivitas antarpulau, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi permintaan domestik yang meningkat, sambil mengelola risiko [55] dan meredam kekhawatiran soal utang serta ketergantungan yang kerap membayangi proyek BRI di negara lain (Bisnis.com, 2019; Cheang, 2019b).
Dukungan pembiayaan pembangunan dari Tiongkok pada masa Widodo mencapai rekor tertinggi, baik dari jumlah proyek (233) maupun nilai investasi (40,3 miliar dolar AS), untuk menopang agenda ambisius di bidang infrastruktur. Menariknya, sebagian besar investasi ini terkonsentrasi di masa jabatan pertamanya dan lebih banyak menggunakan skema berbasis utang dibandingkan bantuan hibah. Tahun-tahun awal pemerintahannya juga menjadi titik kembalinya investasi energi berskala besar dari Tiongkok ke Indonesia.
Dalam kerangka NawaCita , Widodo menargetkan tambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW di 210 lokasi dalam lima tahun. [56] Dari pembiayaan Tiongkok yang difokuskan pada sektor energi, tiga proyek utama masing-masing bernilai lebih dari 1 miliar dolar AS: (1) Perluasan Tahap 3 PLTU Cilacap (1.000 MW), (2) PLTU Mulut Tambang Bangko Tengah (1.200 MW), dan (3) PLTU Jawa-7 (2.100 MW). Sebagian kecil pembiayaan juga dialokasikan untuk proyek energi panas bumi dan gas, meski dalam skala lebih kecil.
Sektor transportasi dan logistik pun menjadi sorotan Beijing. Proyek terbesar adalah Kereta Cepat Jakarta–Bandung (HSR), proyek pertama jenisnya di Indonesia dan Asia Tenggara (lihat Box 3 di bawah). [57] Proyek ini sempat memicu persaingan sengit antara Jepang dan Tiongkok sebelum akhirnya Indonesia memilih tawaran Beijing. Pendanaan HSR berasal dari China Development Bank dengan komposisi 75 persen utang dan 25 persen ekuitas (Brummitt dan Chatterjee, 2015). Selain itu, pembiayaan Tiongkok juga mengalir ke 16 proyek jalan tol (2,45 miliar dolar AS), empat proyek perkeretaapian (414,1 juta dolar AS), serta penyewaan dua pesawat 737-800 oleh BOC Aviation Limited untuk PT Lion Mentari Airlines.
Seperti di era Yudhoyono, pemerintahan Widodo juga menyerap pembiayaan besar dari Tiongkok untuk sektor industri, pertambangan, dan konstruksi, mencapai 6,5 miliar dolar AS. Mineral kritis menjadi fokus, sejalan dengan kebutuhan industri Tiongkok dan target Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah ekspor. Di antaranya, pinjaman 1,26 miliar dolar AS untuk Pabrik Baja Nirkarat Terintegrasi Xiamen Xiangyu di Sulawesi Selatan, dan pendanaan 2,8 miliar dolar AS untuk berbagai proyek di Kawasan Industri Morowali, mulai dari smelter, pabrik baja, hingga pembangkit listrik batu bara captive. Ada pula proyek pengolahan lithium dan kobalt, serta bahan baku dasar seperti semen.
Selama pandemi COVID-19, pembiayaan Tiongkok ke Indonesia difokuskan untuk penanggulangan krisis, mulai dari APD, vaksin, oksigen cair, hingga peralatan medis, dengan total nilai sekitar 85 juta dolar AS. Beijing juga menyuntikkan modal ke Bank Rakyat Indonesia pada Oktober 2020, memungkinkan restrukturisasi lebih dari 2,9 juta debitur dengan total pinjaman mencapai 190 triliun rupiah (Sidik, 2020).
Dengan masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan beberapa bulan, gambaran tentang arah pembiayaan pembangunan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) masih bersifat perkiraan awal. Pemerintahan Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi ambisius sebesar 8 persen dan menempatkan Beijing sebagai salah satu mitra ekonomi kunci (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2025). Dari pihak Tiongkok, Indonesia kerap digambarkan secara hangat sebagai mitra teladan di Global South sekaligus bagian penting dari rantai nilai industri mereka (Liu dan Rayi, 2024).
Sejak Januari 2025, Indonesia juga resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang bergabung dalam BRICS+ , [58] sebuah langkah strategis yang dinilai sebagai antisipasi terhadap ketidakpastian kebijakan tarif Amerika Serikat (King, 2025).
Meski demikian, Subianto tampaknya tidak serta-merta merangkul Beijing sepenuhnya. Pendekatan luar negerinya cenderung melanjutkan pola pendahulunya, Joko Widodo, yang menganut prinsip pragmatic equidistance (Laksmana, 2017): menyeimbangkan hubungan dengan berbagai kekuatan besar yang saling bersaing, tanpa berpihak sepenuhnya, demi memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga otonomi diplomatik.
Pola seperti ini sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Sebagai salah satu pelopor Gerakan Non-Blok, Indonesia sudah lama mengedepankan kemandirian kolektif dan solidaritas antarnegara berkembang untuk mencapai tujuan ekonomi bersama (Pedersen, 2021). Di sisi lain, Beijing juga memposisikan dirinya sebagai sesama negara berkembang demi memperoleh simpati dan dukungan dari mitra-mitra seperti Indonesia (Strangio, 2025).
2.3 Komunitas mana yang menjadi lokasi investasi Tiongkok dan apa alasannya?
Bagian ini membahas apakah, dan sejauh mana, pembiayaan pembangunan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berbeda dari sisi geografis. Untuk menjawabnya, kami menggunakan data proyek AidData terkait pembiayaan pembangunan Tiongkok, guna memetakan distribusi kegiatan Beijing di Indonesia hingga tingkat provinsi—mencakup 36 provinsi dan dua daerah istimewa: DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.
Antara 2000 dan 2023, [59] Beijing menyalurkan pendanaan ke wilayah besar maupun kecil. Meski sebagian besar dana mengalir ke provinsi berpenduduk padat seperti Jawa dan Sumatra, Tiongkok juga membiayai proyek di daerah berpenduduk jarang seperti Papua Barat, demi mengakses mineral strategis atau jalur perairan penting.
Pulau Jawa menjadi penerima terbesar pembiayaan pembangunan Beijing yang dapat dilacak hingga tingkat subnasional, baik dari sisi nilai komitmen (47 persen) maupun jumlah proyek (43 persen). [60] Aktivitas ini tersebar cukup merata di empat provinsi utama dan dua daerah khusus: Jawa Barat (6,58 miliar dolar AS, 24 proyek), Jawa Tengah (5,56 miliar dolar AS, 12 proyek), Banten (4,28 miliar dolar AS, 22 proyek), DKI Jakarta (3,53 miliar dolar AS, 21 proyek), dan Jawa Timur (3,42 miliar dolar AS, 22 proyek). DI Yogyakarta menjadi pengecualian—meski hanya menerima 10 juta dolar AS, provinsi ini tetap menjadi lokasi lima proyek yang mencerminkan hubungan diplomasi tingkat menengah. Rincian proyek di seluruh provinsi dapat dilihat pada Gambar 2.9 dan Tabel 2.10.
Sebagai pusat ekonomi dan wilayah berpenduduk padat, Jawa menawarkan peluang pasar yang sangat menarik bagi perusahaan Tiongkok. Kedekatannya dengan pusat pemerintahan, serta statusnya sebagai daerah asal beberapa presiden Indonesia, memberi peluang tambahan bagi Beijing untuk membangun pengaruh politik dengan elite lokal. [61] Keterlibatan ekonomi Tiongkok di Jawa mengikuti pola two-track development model : di satu sisi, pembiayaan proyek infrastruktur besar berorientasi komersial seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung; di sisi lain, proyek sosial berskala kecil sebagai bentuk goodwill untuk mempererat hubungan masyarakat. Contohnya, sebagian besar bantuan Tiongkok untuk penanganan COVID-19—mulai dari tim medis, donasi alat kesehatan, hingga vaksin—terpusat di Jakarta dan sekitarnya.
Setelah Jawa, Sumatra menjadi wilayah dengan konsentrasi kegiatan terbesar kedua, karena memiliki beberapa kota besar. [62] Pulau ini menerima sekitar seperempat pembiayaan pembangunan Beijing, baik dari sisi nilai maupun jumlah proyek di 10 provinsinya. Sumatra Selatan menyerap porsi terbesar: lebih dari 7 miliar dolar AS, atau setara hampir 800 dolar AS per penduduk. Sebagian besar pembiayaan ini diarahkan untuk proyek infrastruktur besar seperti produksi pulp kertas, telekomunikasi, dan pembangkit listrik. Sebaliknya, Sumatra Utara dan Aceh menerima lebih banyak proyek secara jumlah, tetapi dengan nilai pendanaan yang relatif lebih kecil.
Gambar 2.9: Proyek pembangunan yang didanai Tiongkok di Indonesia berdasarkan provinsi, 2000–2023
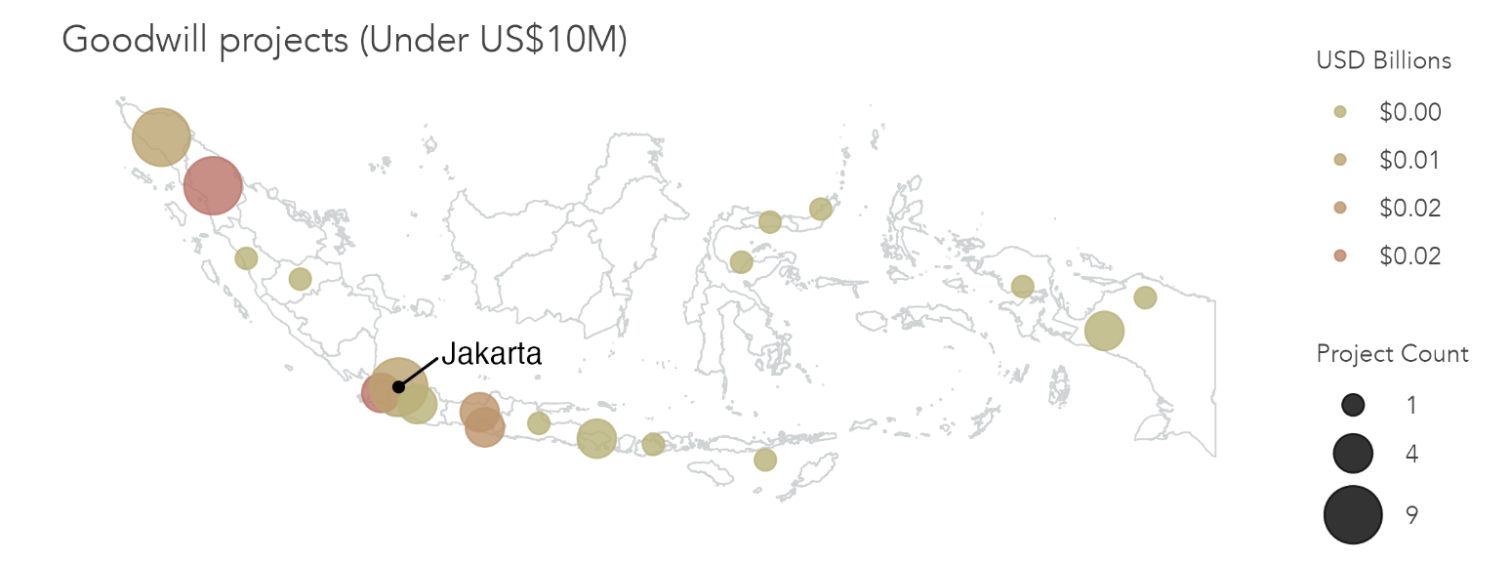
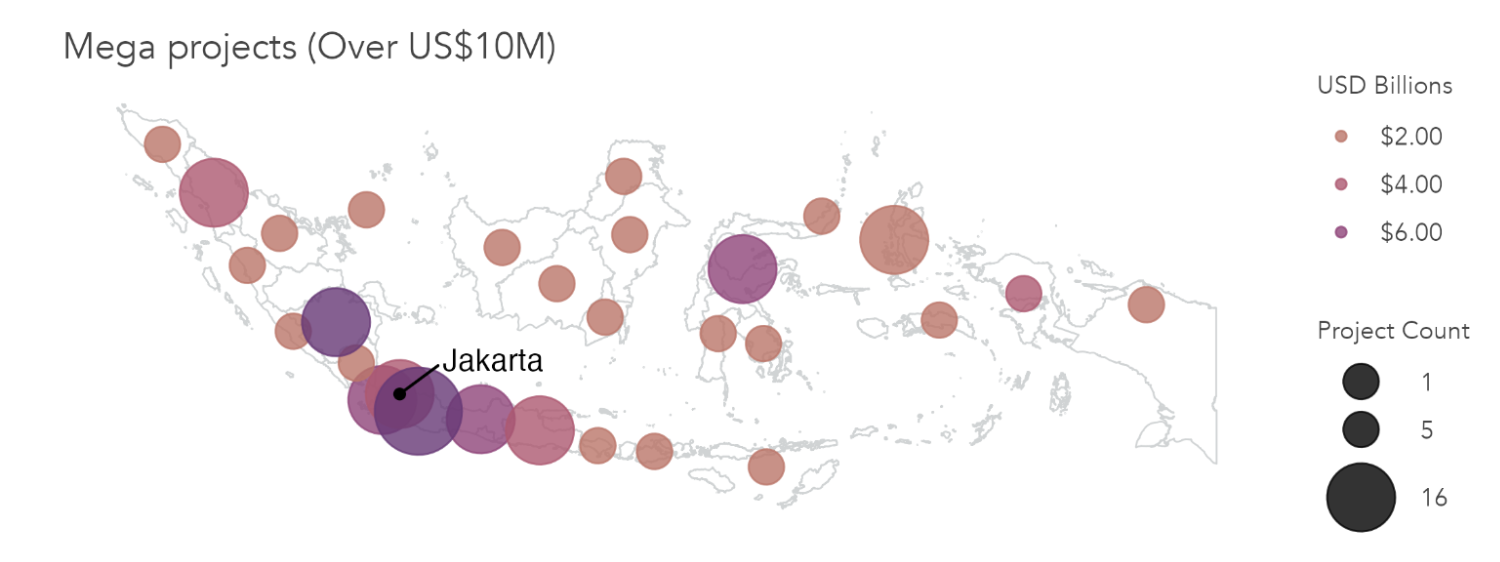
Catatan: Peta-peta ini menunjukkan jumlah total dan nilai dolar dari
proyek pembangunan yang didanai oleh RRT di Indonesia yang telah
diakumulasikan pada tingkat provinsi. Beberapa proyek RRT tidak dapat
dikaitkan dengan wilayah tertentu, baik karena proyek tersebut
bersifat nasional maupun karena terdapat keterbatasan informasi untuk
menentukan lokasi secara tepat. Tim peneliti melengkapi data
pembiayaan RRT dengan riset pustaka terbatas dan tinjauan artikel
media guna mengidentifikasi proyek tambahan dan detail untuk tahun
2022 dan 2023. Data untuk tahun-tahun tambahan ini perlu dianggap
sebagai data sementara.
Sumber: AidData’s Global Chinese
Development Finance Dataset, Versi 3.0 untuk 2000–2021 (Custer
et al., 2023; Dreher et al., 2022).
Jika dilihat dari jumlah proyek dan nilai absolut, Papua memang hanya menerima porsi kecil dari pembiayaan pembangunan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Namun, gambaran itu berubah drastis ketika dihitung dari sisi investasi per kapita. Papua Barat adalah contoh yang menonjol. Selama periode yang dikaji, provinsi ini hanya menarik lima proyek senilai total 3,69 miliar dolar AS. Meski begitu, jumlah itu setara dengan lebih dari tiga ribu dolar per penduduk—angka yang menunjukkan tingginya perhatian Beijing pada wilayah kaya sumber daya alam ini.
Fokus investasi RRT di Papua Barat terutama tertuju pada eksplorasi cadangan gas alam, yang dimulai sejak 2006 melalui keterlibatan konsorsium bank-bank Tiongkok [63] dalam Proyek Tangguh Liquified Natural Gas (LNG). Lebih dari 3 miliar dolar AS digelontorkan untuk eksplorasi dan eksploitasi ladang gas di Teluk Bintuni. Minat investasi kembali meningkat pada 2016, ketika Bank of China dan China Construction Bank mengucurkan 415,6 juta dolar AS untuk ekspansi tahap ketiga lapangan gas Tangguh.
Dorongan ini tak lepas dari meningkatnya kebutuhan energi dan bahan mentah Tiongkok, sekaligus dari ambisi memperkuat kapasitas ekspor LNG Indonesia. Namun, proyek-proyek tersebut sejatinya bersifat multinasional, bukan murni investasi Tiongkok. Japan International Finance Management Corporation menjadi penerima langsung investasi 2016, sementara entitas-entitas RRT ikut dalam skema pembiayaan sindikasi bersama bank-bank dari Brasil, Tiongkok, dan Jepang. Di luar Papua Barat, perhatian Beijing terhadap provinsi-provinsi lain di Papua, termasuk Maluku, Kalimantan, dan Nusa Tenggara, terbilang sangat minim.
Di sisi lain, Sulawesi menempati posisi menengah dalam peta tujuan pembiayaan pembangunan RRT. Enam provinsinya menyerap 17 persen dari total nilai investasi Beijing dan 12 persen dari jumlah proyek. Distribusi ini, bagaimanapun, tidak merata. Sulawesi Tengah mendominasi dengan portofolio senilai 5,76 miliar dolar AS untuk 15 proyek, mayoritas berfokus pada peningkatan kapasitas ekspor industri. Kawasan Industri Morowali menjadi pusatnya, dengan konsorsium pemberi pinjaman asal Tiongkok membiayai Proyek Pembangkit Listrik Tambang Sulawesi senilai 2,5 miliar dolar AS antara 2013 hingga 2018.
Investasi di Morowali diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi baja dan nikel dari smelter-smelter di kawasan tersebut, sekaligus membangun basis industri bagi salah satu pusat pengolahan nikel terbesar di Indonesia (lihat Kotak 3 di atas).
Tabel 2.10: Proyek resmi RRT di Indonesia berdasarkan provinsi, 2000–2023
Tabel dapat diurutkan dengan mengeklik kolom. Pada layar kecil, gulir secara horizontal untuk melihat kolom tersembunyi.
Nama provinsi |
Wilayah |
Nilai proyek per miliar dolar AS konstan 2024 |
Jumlah proyek |
Dolar AS per kapita |
|---|---|---|---|---|
Aceh |
Sumatra |
0,23 |
12 |
42,20 |
Bali |
Nusa Tenggara |
0,60 |
7 |
135,07 |
|
Kepulauan Bangka Belitung |
Sumatra |
0,00 |
0 |
0,00 |
Banten |
Jawa |
4,28 |
22 |
344,05 |
Bengkulu |
Sumatra |
0,36 |
3 |
168,86 |
Jawa Tengah |
Jawa |
5,56 |
12 |
146,75 |
Kalimantan Tengah |
Kalimantan |
0,03 |
1 |
11,01 |
Papua Tengah |
Papua |
0,00 |
2 |
Data populasi nihil |
Sulawesi Tengah |
Sulawesi |
5,76 |
15 |
1.844,92 |
Jawa Timur |
Jawa |
3,42 |
22 |
81,90 |
Kalimantan Timur |
Kalimantan |
0,27 |
5 |
66,51 |
Nusa Tenggara Timur |
Nusa Tenggara |
0,02 |
2 |
4,28 |
Gorontalo |
Sulawesi |
0,00 |
1 |
1,30 |
Papua Pegunungan |
Papua |
0,00 |
0 |
Data populasi nihil |
DKI Jakarta |
Jawa |
3,53 |
21 |
330,54 |
Jambi |
Sumatra |
0,00 |
1 |
0,43 |
Lampung |
Sumatra |
0,03 |
2 |
3,24 |
Maluku |
Kepulauan Maluku |
0,02 |
1 |
12,38 |
Kalimantan Utara |
Kalimantan |
0,02 |
1 |
21,32 |
Maluku Utara |
Kepulauan Maluku |
0,71 |
6 |
523,21 |
Sulawesi Utara |
Sulawesi |
0,42 |
6 |
155,90 |
Sumatra Utara |
Sumatra |
3,17 |
25 |
203,56 |
Papua |
Papua |
0,02 |
2 |
5,31 |
Riau |
Sumatra |
0,30 |
2 |
44,36 |
Kepulauan Riau |
Sumatra |
0,26 |
1 |
117,18 |
Kalimantan Selatan |
Kalimantan |
0,41 |
4 |
94,78 |
Papua Selatan |
Papua |
0,00 |
0 |
Data populasi nihil |
Sulawesi Selatan |
Sulawesi |
0,58 |
5 |
61,32 |
Sumatra Selatan |
Sumatra |
7,04 |
9 |
797,14 |
Sulawesi Tenggara |
Sulawesi |
1,46 |
2 |
521,81 |
Papua Barat Daya |
Papua |
0,00 |
0 |
Data populasi nihil |
|
Daerah Istimewa Yogyakarta |
Jawa |
0,01 |
5 |
2,68 |
Java Barat |
Jawa |
6,58 |
24 |
130,79 |
Kalimantan Barat |
Kalimantan |
0,53 |
6 |
93,18 |
Nusa Tenggara Barat |
Nusa Tenggara |
0,06 |
3 |
11,28 |
Papua Barat |
Papua |
3,69 |
5 |
3.063,52 |
Sulawesi Barat |
Sulawesi |
0,00 |
0 |
0,00 |
Sumatra Barat |
Sumatra |
0,23 |
2 |
39,97 |
Catatan: Tabel ini menampilkan proyek-proyek pembangunan yang didanai
oleh Tiongkok berdasarkan provinsi antara tahun 2000 hingga 2023
(mencakup instrumen hibah dan utang), berdasarkan jumlah proyek, nilai
dolar, dan nilai dolar per kapita, menggunakan statistik populasi
tahun 2024. Tim peneliti melengkapi data pembiayaan dari RRT dengan
riset terbatas melalui kajian pustaka dan tinjauan artikel media untuk
mengidentifikasi proyek tambahan serta detail proyek pada tahun 2022
dan 2023. Data untuk dua tahun terakhir ini harus dianggap bersifat
sementara.
Sumber: AidData’s Global Chinese Development
Finance Dataset, Versi 3.0 untuk tahun 2000–2021 (Custer et al.,
2023; Dreher et al., 2022) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia,
2024.
2.4 Bagaimana perkembangan investasi langsung Tiongkok (FDI) dari waktu ke waktu, baik secara absolut maupun dibandingkan dengan pembiayaan pembangunan RRT?
Selama lima belas tahun terakhir (2010–2024), Tiongkok menjadi sumber terbesar investasi langsung asing (FDI) ke Indonesia, dengan total mencapai 94,1 miliar dolar AS, jauh melampaui pembiayaan pembangunan yang diarahkan langsung oleh pemerintah Beijing. [64] Berbeda dengan pembiayaan pembangunan, FDI melibatkan kepemilikan atau kepentingan finansial lintas negara yang bersifat lebih tahan lama di tangan investor korporasi (OECD, n.d.a dan n.d.b). [65]
Jika digabungkan dengan investasi dari Hong Kong, perusahaan-perusahaan Tiongkok menyumbang hampir seperempat dari seluruh belanja modal asing ( capital expenditures / capex ) baru di Indonesia. Namun, arus modal ini memiliki dinamika berbeda dari pembiayaan pembangunan. Kadang keduanya saling melengkapi, tapi di lain waktu bergerak secara terpisah.
Secara umum, FDI Tiongkok mengikuti pola pasar modal global. Arus modal masuk dari semua negara ke Indonesia mencapai puncak pada awal 2015, dengan nilai transaksi baru 14,7 miliar dolar AS (Gambar 2.11). Pada periode yang sama, FDI Tiongkok ke Indonesia juga menyentuh titik tertinggi, yakni 20,8 miliar dolar AS. Namun, ada juga saat-saat ketika investor Tiongkok justru menahan diri, bahkan ketika pasar global sedang bergairah. Misalnya, FDI baru dari Tiongkok ke Indonesia anjlok 98 persen antara 2011–2012 dan turun 83 persen dari 2018 ke 2019, sementara FDI dari semua negara sumber hanya turun sedikit atau bahkan stabil. [66]
Setelah perlambatan global akibat pandemi COVID-19, minat terhadap investasi luar negeri di Indonesia kembali menguat. Investor Tiongkok terlihat sangat agresif, menyumbang sepertiga dari setiap dolar FDI baru yang masuk ke Indonesia pada 2023, setara lebih dari 20 miliar dolar AS dalam belanja modal baru (Gambar 2.11). Lonjakan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Pasar ASEAN lain seperti Vietnam, Filipina, dan Thailand bahkan masih menarik FDI Tiongkok dalam jumlah yang lebih besar secara total (IMF, 2024).
Gambar 2.11: FDI masuk dari Tiongkok dan dunia ke Indonesia, 2010–2024
Catatan: Gambar ini menunjukkan komitmen tahunan investasi langsung
asing (FDI) masuk yang baru ke Indonesia dari tahun 2010 hingga 2024.
Garis merah menunjukkan sumber dari Tiongkok, sedangkan garis biru
menunjukkan semua sumber (termasuk Tiongkok). Nilai FDI dinyatakan
dalam bentuk belanja modal (capital expenditures/capex) dalam miliar
dolar AS tahun 2024.
Sumber: fDi Markets, dari Financial Times
Ltd.
Setidaknya ada dua faktor yang diduga menjadi pendorong utama lonjakan ini: pertama, kebijakan “Zero-COVID” Beijing yang menekan peluang di pasar domestik; [67] dan kedua, memburuknya hubungan Tiongkok–Amerika Serikat yang mendorong perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk mendiversifikasi kegiatan manufaktur ke luar negeri.
Tabel 2.12: FDI masuk dari Tiongkok dan dunia ke Indonesia, 2010–2024
Tahun |
Belanja modal semua sumber, Miliar dolar AS kostan 2024 |
Belanja modal Tiongkok, Miliar dolar AS kostan 2024 |
Persen Belanja modal Tiongkok |
|---|---|---|---|
2010 |
19,32 |
1,55 |
8,02% |
2011 |
34,09 |
6,87 |
20,14% |
2012 |
20,44 |
0,12 |
0,57% |
2013 |
31,14 |
10,17 |
32,68% |
2014 |
25,62 |
5,47 |
21,35% |
2015 |
53,92 |
14,72 |
27,31% |
2016 |
31,58 |
5,93 |
18,76% |
2017 |
13,45 |
4,48 |
33,32% |
2018 |
29,36 |
6,06 |
20,63% |
2019 |
17,20 |
1,01 |
5,86% |
2020 |
24,28 |
6,46 |
26,61% |
2021 |
10,33 |
1,28 |
12,40% |
2022 |
25,52 |
5,39 |
21,12% |
2023 |
61,83 |
20,77 |
33,59% |
2024 |
14,71 |
3,87 |
26,32% |
Catatan: Tabel ini menunjukkan total komitmen investasi langsung asing
(FDI) baru yang masuk dari Tiongkok dan dari semua sumber ke Indonesia
pada periode 2010 hingga 2024. Nilai FDI dinyatakan dalam bentuk belanja
modal (capital expenditures/capex) dalam miliar dolar AS tahun 2024.
Sumber:
fDi Markets, dari Financial Times Ltd.
Gambar 2.13: Pangsa FDI Tiongkok terhadap total FDI di Indonesia, 2010–2024
Catatan: Gambar ini menunjukkan proporsi komitmen investasi langsung
asing (FDI) baru yang berasal dari Tiongkok terhadap total FDI masuk
tahunan di Indonesia pada periode 2010 hingga 2024. Nilai FDI
dinyatakan sebagai belanja modal (capital expenditures/capex) dalam
miliar dolar AS tahun 2024.
Sumber: fDi Markets, dari Financial
Times Ltd., perhitungan oleh AidData.
Peta 2.14: FDI masuk dari Tiongkok ke Indonesia menurut wilayah, 2010–2024
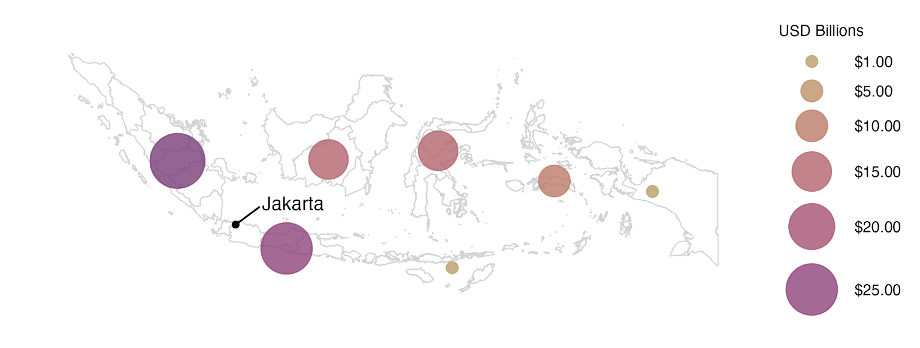
Catatan: Peta ini menunjukkan total komitmen investasi langsung asing
(FDI) baru yang berasal dari Tiongkok di Indonesia pada periode 2010
hingga 2024. Nilai FDI dinyatakan sebagai belanja modal (capital
expenditures/capex) dalam miliar dolar AS tahun 2024. Beberapa proyek
FDI tidak memiliki lokasi yang ditentukan secara spesifik.
Sumber:
fDi Markets, dari Financial Times Ltd.
Seperti halnya pembiayaan pembangunan yang diarahkan langsung oleh pemerintah Beijing, investasi langsung Tiongkok (FDI) juga tidak mengalir merata ke seluruh wilayah Indonesia. Namun, ada perbedaan mencolok yang menunjukkan bahwa arus investasi ini tidak bersifat tunggal atau seragam.
Pulau Jawa (20,8 miliar dolar AS) dan Sumatra (26,1 miliar dolar AS) menjadi magnet utama FDI Tiongkok, mengikuti pola yang mirip dengan penyaluran pembiayaan pembangunan RRT (Tabel 2.15). Tetapi jika dilihat dari proporsinya terhadap total FDI di masing-masing wilayah, dominasinya berbeda jauh: di Sumatra, investor Tiongkok menguasai hingga 56 persen, sedangkan di Jawa hanya sekitar 11 persen.
Sementara itu, Sulawesi berada di posisi menengah, menarik FDI Tiongkok dalam jumlah yang relatif moderat, meski secara per kapita wilayah ini menerima pembiayaan pembangunan dari RRT dalam tingkat yang sangat tinggi (Tabel 2.15).
Tabel 2.15: FDI masuk dari Tiongkok ke Indonesia menurut wilayah, 2010–2024
Wilayah tujuan |
Provinsi-provinsi |
Belanja modal semua sumber, miliar dolar AS konstan 2024 |
Belanja modal Tiongkok, miliar dolar AS konstan 2024 |
Jawa |
Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat |
181,10 |
20,75 |
Kalimantan |
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat |
28,07 |
11,21 |
Maluku |
Maluku, Maluku Utara |
12,87 |
7,58 |
Nusa Tenggara |
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur |
10,01 |
0,77 |
Papua |
Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Barat |
2,62 |
0,60 |
Sulawesi |
Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat |
36,01 |
13,24 |
Sumatra |
Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Sumatra Barat |
46,70 |
26,06 |
Tidak diterangkan |
- |
95,41 |
13,92 |
Catatan: Tabel ini menunjukkan total komitmen masuk investasi langsung
asing (FDI) baru dari Tiongkok di Indonesia selama periode 2010 hingga
2024 berdasarkan wilayah. Data tidak dilaporkan pada tingkat provinsi
secara spesifik. Nilai FDI dinyatakan dalam bentuk belanja modal
(capital expenditures/capex) dalam miliar dolar AS tahun 2024.
Beberapa proyek FDI tidak memiliki lokasi yang ditentukan secara
spesifik.
Sumber: fDi Markets, dari Financial Times Ltd.
Sama seperti pola pada pembiayaan pembangunannya, FDI Tiongkok di Indonesia juga cenderung berat ke sektor ekstraktif, manufaktur, dan konstruksi, dibandingkan sektor lain (Tabel 2.16). [68] Berdasarkan data dari fDi Markets , perusahaan-perusahaan Tiongkok menguasai 98 persen investasi baru di sektor mineral, serta setengah dari total belanja modal yang masuk ke industri logam. Bahkan di sektor-sektor dengan nilai total investasi relatif kecil, dominasi Tiongkok tetap terlihat. Misalnya, mereka memegang 95 persen FDI di produk kayu dan 62 persen di keramik serta kaca.
Jika ditelusuri lebih rinci per sektor dan wilayah, terlihat adanya sinergi antara FDI Tiongkok dan pembiayaan pembangunan yang diarahkan oleh pemerintahnya. Beijing kerap menggunakan sumber daya negara untuk membangun fondasi awal, seperti infrastruktur dan jaringan hubungan, di wilayah yang dianggap strategis. Fondasi ini kemudian membuka jalan bagi masuknya FDI Tiongkok, yang memanfaatkan peluang pasar tersebut untuk berkembang dan memperbesar skala investasi (lihat Kotak 4).
Satu investasi FDI Tiongkok sering kali bisa menjadi pemicu masuknya gelombang investasi lain. Pada 2022, Xinyi Glass Holdings yang berbasis di Hong Kong mendapatkan konsesi selama 80 tahun untuk membangun pabrik kaca fotovoltaik senilai 11,6 miliar dolar AS di Rempang—menjadikannya proyek FDI Tiongkok terbesar di Indonesia hingga saat ini (Hodge dan Septiari, 2023). Setahun kemudian, para mitra proyek mengumumkan rencana menjadikan konsesi tersebut sebagai pondasi pembangunan “Kawasan Industri Rempang Eco-City,” yang ditargetkan mampu mengekspor energi terbarukan dalam skala gigawatt setiap tahunnya (Soeriaatmadja, 2023).
Ditunjuk sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, rencana pembangunan ini memicu kontroversi. Pemerintah melakukan penggusuran terhadap penduduk lama Rempang demi membuka lahan untuk kawasan industri, yang memicu penolakan dan sorotan publik (Rahayu, 2025; Jong, 2023; Irham dan Ajengrastri , 2023).
Potensi skala besar FDI Tiongkok jelas menjadi daya tarik bagi mitra Indonesia. Namun, janji investasi tidak selalu berakhir sesuai rencana. Contohnya adalah rencana investasi Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)—perusahaan Tiongkok yang dikenal sebagai produsen baterai litium -ion terbesar di dunia—untuk menanam modal hampir 6 miliar dolar AS di sektor pengolahan nikel domestik, sebuah bidang yang menjadi prioritas strategis pemerintah Indonesia.
Investasi ini mencakup proyek-proyek turunan seperti penambangan dan pengolahan nikel, produksi material baterai, pembuatan baterai, hingga fasilitas daur ulang (Shanghai Nonferrous Metals Network, 2022). [69] Namun, pada awal 2025, CATL mengumumkan pengurangan pendanaan dengan alasan melemahnya permintaan global (Juwita, 2025). Kejadian ini menjadi pengingat akan risiko yang dihadapi Indonesia jika terlalu bergantung pada modal Tiongkok untuk mengembangkan infrastruktur strategis, khususnya di sektor logam dan mineral yang krusial bagi transisi menuju energi hijau.
Tabel 2.16: Sektor-sektor terpilih, FDI masuk dari Tiongkok dan dunia ke Indonesia, 2010–2024
Tabel dapat diurutkan dengan mengeklik kolom. Pada layar kecil, gulir secara horizontal untuk melihat kolom tersembunyi.
Sektor |
Belanja modal semua sumber, miliar dolar AS konstan 2024 |
Belanja modal Tiongkok, miliar dolar AS konstan 2024 |
Persen Belanja Modal Tiongkok |
|---|---|---|---|
Logam |
83,47 |
41,55 |
50% |
Mineral |
12,06 |
11,78 |
98% |
Komponen elektronik |
31,07 |
8,84 |
28% |
Batu bara, minyak, dan gas |
67,72 |
7,14 |
11% |
Properti |
34,65 |
6,14 |
18% |
OEM otomotif |
18,69 |
2,42 |
13% |
Material bangunan |
5,9 |
2,23 |
38% |
Hotel dan pariwisata |
10,84 |
2,13 |
20% |
Energi terbarukan |
22,81 |
2,11 |
9% |
Karet |
8,62 |
2,09 |
24% |
Keramik dan kaca |
1,66 |
1,03 |
62% |
Peralatan industri |
1,79 |
0,65 |
36% |
Produk kayu |
0,19 |
0,18 |
95% |
Farmasi |
0,48 |
0,14 |
30% |
Catatan: Tabel ini menunjukkan sektor-sektor terpilih untuk (i) total
investasi langsung asing (FDI) Tiongkok yang masuk dan (ii) FDI dari
semua sumber, termasuk Tiongkok, di Indonesia dari tahun 2010 hingga
2024. Nilai FDI dinyatakan sebagai belanja modal (capex) dalam miliar
dolar AS nilai tahun 2024. Tabel ini mencakup sektor-sektor dengan
capex tertinggi dari Tiongkok, atau sektor-sektor di mana persentase
capex global dari Tiongkok melebihi 20 persen. Pewarnaan selaras
dengan masing-masing kolom.
Sumber: fDi Markets, dari Financial
Times Ltd. Untuk rincian sektor lengkap, silakan lihat Tabel C-3 dalam
Lampiran Teknis.
3. Relasi
Wawasan utama bab ini:
- Pembiayaan pembangunan Beijing di Indonesia bertumpu pada jaringan global yang melibatkan 208 lembaga pembiaya utama dan mitra pembiaya, untuk menghimpun modal sekaligus menyebarkan risiko.
- Ketergantungan pada BUMN Tiongkok membawa risiko tersendiri, mengingat 14 di antaranya pernah terlibat dalam praktik keuangan yang dipertanyakan.
- Proyek-proyek Beijing tidak sepenuhnya “buatan Tiongkok”: perusahaan Indonesia kerap menjadi pelaksana atau terlibat dalam usaha patungan (joint venture) dan kendaraan tujuan khusus (special purpose vehicle).
- Universitas dan organisasi Islam di Indonesia memberi Beijing peluang untuk meminjam kredibilitas sekaligus memanfaatkan jaringan distribusi yang ada, demi memenangkan hati dan pikiran masyarakat.
RRT memang menjadi salah satu pemasok pembiayaan pembangunan terbesar di Indonesia, tetapi jelas bukan satu-satunya pemain. Jika pada awalnya hanya melibatkan segelintir bank kebijakan dan BUMN Tiongkok, kini ekosistemnya telah berkembang menjadi jaringan yang luas dan beragam, dengan reputasi yang berbeda-beda dalam hal transparansi, pelaksanaan, dan hasil.
Perlu diingat, pembangunan internasional memiliki dua sisi: sisi pasokan dan sisi permintaan. Setiap proyek yang didanai Beijing di Indonesia membutuhkan penerima manfaat, pelaksana, dan seringkali mitra pembiayaan yang bersedia bekerja sama.
3.1 Sisi penawaran: Siapa yang mendanai dan melaksanakan proyek pembangunan yang didukung RRT?
Dukungan Beijing terhadap proyek-proyek pembangunan di Indonesia bukanlah urusan sederhana, melainkan sebuah operasi yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Antara 2000 hingga 2023, tercatat setidaknya 439 entitas berbeda yang terlibat dalam pembiayaan, pembiayaan bersama, atau pelaksanaan proyek di Indonesia. Jauh dari kesan seragam, para pemain ini tersebar di 35 negara atau wilayah (lihat Gambar 3.1). Sebagian besar memang berbasis di Tiongkok (168 entitas) atau Indonesia (158 entitas), tetapi sekitar seperempatnya berasal dari kawasan Asia, Pasifik, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Utara.
Karena fokus studi ini adalah investasi pembangunan yang dibiayai oleh RRT, semua dari 58 pembiayaan utama berasal dari institusi Tiongkok. Mereka mencakup bank komersial milik negara, bank kebijakan, kementerian, dan perwakilan diplomatik. Sebanyak 52 entitas berbasis di Tiongkok daratan, sementara enam lainnya merupakan bank atau lembaga pemerintah Tiongkok yang beroperasi di Indonesia, Singapura, dan Taiwan. [70]
Menariknya, tingkat keterlibatan para pembiayan ini sangat bervariasi. Sepuluh pembayaran utama tercatat mendanai delapan proyek atau lebih (lihat Gambar 3.2), namun 34 pembiaya lainnya hanya terlibat dalam satu proyek saja selama dua dekade terakhir.
Empat dari lima pembiayaan terbesar, dilihat dari jumlah proyek, berasal dari dua kelompok bank komersial milik negara (Bank of China dan Industrial and Commercial Bank of China) serta dua bank kebijakan milik negara (Export-Import Bank of China dan China Development Bank). Keempatnya memiliki kapasitas mobilisasi pendanaan berskala besar untuk proyek infrastruktur bernilai jutaan dolar. Selain menjadi pembiaya utama, masing-masing beserta anak perusahaannya juga sering berperan sebagai pembiaya bersama. Tercatat, Bank of China mendanai 39 proyek, Industrial and Commercial Bank of China 35 proyek, China Development Bank 15 proyek, dan China Eximbank sembilan proyek. Beberapa contoh proyek yang menggambarkan peran mereka dibahas setelah Gambar 3.1.
Gambar 3.1: Kantor pusat pendana, ko-pendana, dan pelaksana proyek pembangunan yang dipimpin RRT di Indonesia, 2000–2023
Catatan: Gambar ini menggambarkan jumlah pemberi dana utama, pemberi
dana bersama, dan pelaksana (yaitu pihak dari sisi penawaran) dari
proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh Tiongkok di Indonesia,
beserta lokasi kantor pusat mereka. Tim peneliti melengkapi data
pembiayaan Tiongkok dengan riset meja terbatas dan tinjauan artikel
media untuk mengidentifikasi proyek tambahan dan detail terkait pada
tahun 2022 dan 2023. Data untuk dua tahun terakhir ini harus dianggap
sebagai data sementara.
Sumber: AidData’s Global Chinese
Development Finance Dataset, Versi 3.0 untuk 2000–2021 (Custer
et al., 2023; Dreher et al., 2022).
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) mengucurkan dana 50 juta dolar AS untuk proyek penghubung antara Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Stasiun Kereta Manggarai. Bersama anak perusahaannya, ICBC tercatat terlibat dalam pembiayaan atau pembiayaan bersama sedikitnya 157 proyek di Indonesia, termasuk pinjaman sindikasi untuk sektor telekomunikasi seperti Paket Timur Palapa Ring, dan sektor perumahan melalui fasilitas kredit 1 triliun rupiah kepada Bank Tabungan Negara untuk Program Satu Juta Rumah.
China Development Bank (CDB) menyalurkan pinjaman 150 juta dolar AS untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kendari-3 berkapasitas 100 MW, serta turut membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dan Kawasan Industri Morowali. Bank of China (BOC) aktif dalam berbagai pinjaman sindikasi untuk proyek jalan tol bersama PT Wijaya Karya, dan memberikan pinjaman 1 triliun rupiah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur untuk memperkuat pembiayaan infrastruktur nasional.
China Eximbank mendukung proyek-proyek berskala besar di sektor energi dan air, bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
Berbeda dari bank kebijakan dan komersial milik negara yang memiliki modal besar, entitas diplomatik seperti Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta serta Konsulat di Surabaya dan Medan berperan di garis depan strategi “merebut hati dan pikiran” masyarakat. Mereka mendanai berbagai kegiatan yang bernilai simbolis tinggi namun berbiaya rendah, mulai dari bantuan sekolah dan rumah sakit (seperti buku dan tablet untuk Institut Teknologi Bandung, serta masker dan kendaraan untuk penanggulangan COVID-19), bantuan pascabencana (misalnya 35.000 dolar AS untuk wilayah terdampak tsunami 2018), hingga diplomasi budaya seperti menghadiahkan dua panda untuk Taman Safari Bogor atau mengadakan acara buka puasa bersama selama Ramadan. Kantor konsuler juga sering menjadi penghubung kerja sama berbasis hibah yang dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri RI atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Salah satu penyandang dana utama untuk kerja sama pendidikan adalah Center for Language Education and Cooperation (CLEC, sebelumnya Hanban), [71] yang bermitra dengan universitas-universitas Indonesia untuk mendukung pengajaran bahasa Mandarin, pengembangan keterampilan, dan pertukaran internasional melalui program unggulan Institut Konfusius. Di Indonesia, CLEC bermitra dengan Universitas Negeri Surabaya, Universitas Kristen Maranatha, Universitas Hasanuddin, Universitas Tanjungpura, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Al-Azhar, bekerja sama dengan universitas mitra di Tiongkok seperti Hainan Normal University, melalui skema hibah multi-tahun.
Kementerian Perdagangan Tiongkok (MOFCOM) juga punya peran penting, terutama pada awal 2000-an dan pascatsunami Aceh 2004. Salah satu program andalannya adalah Proyek Kerja Sama Teknik Padi Hibrida Tiongkok–Indonesia yang diluncurkan pada 2008, melatih lebih dari 40 petugas pertanian Indonesia dan memperkenalkan varietas padi Tiongkok berproduktivitas tinggi di tujuh provinsi. MOFCOM juga mengkoordinasikan paket rekonstruksi Aceh pascatsunami , termasuk hibah 60 juta yuan (sekitar 7,5 juta dolar AS) untuk membangun kembali sekolah dan kantor pemerintahan—skema yang terbilang dermawan dibanding praktik pembiayaan Tiongkok yang umumnya berbasis pinjaman berbunga pasar.
Berbeda dengan banyak donor dan pemberi pinjaman bilateral lainnya, Tiongkok tidak memublikasikan aktivitas pembiayaan pembangunannya di portal internasional seperti Sistem Pelaporan Kreditur OECD atau International Aid Transparency Initiative (IATI). Untuk menutup celah ini, AidData menggabungkan berbagai sumber data guna melacak aliran bantuan dan utang dari Tiongkok ke Indonesia. [72] Keterbatasan informasi publik membuat identitas pemberi dana utama kadang sulit diketahui, tak heran jika “Lembaga Pemerintah Tiongkok yang tidak disebutkan secara spesifik” menjadi pemberi dana yang paling sering muncul setelah entitas besar lainnya (lihat Tabel 3.2).
Tabel 3.2: Sepuluh pendana utama proyek pembangunan yang didanai Tiongkok di Indonesia, 2000–2023
Pendana |
Jumlah Proyek |
|
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) [73] |
122 |
|
Institusi BUMN Tiongkok yang tak disebutnya. |
80 |
|
Bank of China (BOC) [74] |
78 |
China Development Bank |
58 |
|
Export-Import Bank of China (China Eximbank) |
55 |
|
Kedutaan dan Konsulat Jenderal Tiongkok |
21 |
|
China Construction Bank Corporation (CCB) [75] |
16 |
|
Hanban (Confucius Institute Headquarters) dan Center for Language Education and Cooperation (CLEC) [76] |
13 |
|
Kementerian Perdagangan Tiongkok |
9 |
|
China CITIC Bank Corporation Limited [77] |
8 |
Catatan: Gambar ini menggambarkan jumlah proyek yang melibatkan masing-masing dari 10 lembaga pembiayaan utama dalam proyek pembangunan yang didanai oleh Tiongkok di Indonesia. Jumlah proyek telah diakumulasi berdasarkan cabang dari lembaga yang sama (rincian terdapat dalam catatan kaki).
Sumber: AidData’s Global Chinese Development Finance Dataset, Versi 3.0, untuk periode 2000–2021 (Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022). Dilengkapi dengan riset pustaka terbatas dan peninjauan artikel media untuk mengidentifikasi proyek tambahan dan detail untuk tahun 2022–2023.
Pendanaan bersama menjadi salah satu ciri khas pembangunan yang didukung RRT di Indonesia. Skema ini memungkinkan bank kebijakan Tiongkok membagi risiko kredit sekaligus memanfaatkan keahlian dari mitra internasional. Jumlah ko-pendana di tiap proyek bervariasi—ada yang melibatkan belasan lembaga untuk proyek berskala besar, ada pula yang sama sekali tanpa mitra pendanaan.
Dalam kajian ini, kami mengidentifikasi 208 ko-pendana yang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan yang didanai Tiongkok di Indonesia. Menariknya, 63 persen di antaranya berasal dari entitas sektor swasta. Temuan ini sejalan dengan tren global di mana Tiongkok semakin sering bekerja sama dengan bank komersial Barat dan lembaga multilateral dalam skema pinjamannya (Parks et al., 2023). [78]
Gambar 3.3: Pendana utama asal Tiongkok dan penerima di Indonesia,
2000–2023 

|
|
|
Bank Kebijakan Milik Negara |
|
|
|
|
Bank Komersial Milik Negara |
|
|
|
|
Lembaga Pemerintah |
|
|
|
|
Pemerintah Indonesia |
|
|
|
|
Penerima Lainnya |
|
Catatan: Ketebalan garis menunjukkan jumlah proyek. Gambar ini
menggambarkan tren umum dalam hubungan antara para lembaga pembiayaan
utama Tiongkok untuk proyek-proyek pembangunan dan para penerimanya di
Indonesia. Gambar ini tidak mewakili keseluruhan data mengenai lembaga
pembiayaan dan penerima proyek-proyek pembangunan yang didanai
Tiongkok di Indonesia.
Sumber: AidData’s Global Chinese
Development Finance Dataset, Versi 3.0 untuk tahun 2000–2021
(Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022). Dilengkapi dengan riset
dokumenter terbatas dan ulasan artikel media untuk mengidentifikasi
proyek-proyek tambahan dan detail lainnya untuk tahun 2022–2023.
Selain mitra dari kawasan Asia, lembaga-lembaga asal Jerman (9), Amerika Serikat (7), dan Inggris (5) juga aktif menjadi pembiaya bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang didanai Tiongkok di Indonesia. Mayoritas berasal dari sektor jasa keuangan—bank komersial dan investasi—dengan jaringan internasional luas dan kapasitas pembiayaan yang besar. Meski ada beberapa lembaga yang kerap terlibat berulang, sekitar sepertiga di antaranya hanya terlibat dalam satu proyek saja di Indonesia.
Berdasarkan jumlah proyek yang diikuti, para pembiaya bersama paling aktif terlibat dalam 20 proyek atau lebih sepanjang 2000–2023 (lihat Tabel 3.4). Daftar ini mencakup nama-nama besar perbankan global seperti Standard Chartered Bank dari Inggris, BNP Paribas dari Belgia, dan Citibank dari Amerika Serikat. Dari kawasan regional, terlihat pemain penting seperti Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC Group) dari Jepang, DBS Bank dari Singapura, ANZ Group dari Australia, serta Cathay Bank dan CTBC dari Taiwan. Dari dalam negeri, Indonesia Eximbank dan Bank Mandiri menjadi dua lembaga pembiayaan bersama yang paling aktif. Beragamnya asal dan besarnya jumlah lembaga ini mencerminkan betapa terintegrasinya pembiayaan pembangunan internasional saat ini.
Keterlibatan berulang dari jaringan lembaga multinasional ini menunjukkan bagaimana pembiayaan pembangunan Tiongkok telah berevolusi. Beijing kini banyak mengadopsi model pembiayaan sindikasi, di mana bank kebijakan dan bank komersial milik negara tetap menjadi pilar utama untuk proyek berskala besar, namun secara rutin berbagi risiko dengan lembaga perbankan internasional di berbagai belahan dunia. Kombinasi modal negara dan pembiayaan bersama berbasis pasar ini memungkinkan RRT memperbesar skala proyek, mendiversifikasi risiko kredit, dan mengamankan dukungan negara tuan rumah melalui keterlibatan bank-bank domestik.
Tabel 3.4: Lima belas ko-pendana utama proyek pembangunan yang didanai Tiongkok di Indonesia, 2000–2023
Ko-pendana |
Jumlah proyek |
|---|---|
|
Sumitomo Mitsui Banking Corporation [79] |
48 |
|
DBS Bank [80] |
47 |
|
MUFG Bank, Ltd. (Formerly Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU)) |
40 |
|
Bank of China (BOC) [81] |
39 |
|
Standard Chartered Bank PLC [82] |
36 |
|
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) [83] |
35 |
|
Oversea-Chinese Banking Corporation, Limited (OCBC Bank) |
35 |
|
BNP Paribas S.A. [84] |
31 |
|
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk [85] |
30 |
|
CTBC Bank [86] |
26 |
|
Citibank N.A. [87] |
24 |
|
Indonesia Eximbank [88] |
23 |
|
Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) [89] |
22 |
|
United Overseas Bank Limited (UOB) [90] |
22 |
Cathay United Bank |
20 |
Catatan: Tabel ini mencantumkan jumlah proyek yang melibatkan 15
lembaga pembiayaan teratas untuk proyek pembangunan yang didanai oleh
Tiongkok di Indonesia. Jumlah proyek telah digabungkan dari seluruh
cabang lembaga yang sama (rincian terdapat dalam catatan kaki).
Sumber:
AidData’s Global Chinese Development Finance Dataset, Versi 3.0
untuk tahun 2000–2021 (Custer et al., 2023; Dreher et al.,
2022). Dilengkapi dengan riset dokumenter terbatas dan tinjauan
artikel media untuk mengidentifikasi proyek-proyek tambahan dan
rincian lainnya untuk tahun 2022–2023.
Setelah membahas bagaimana struktur pembiayaan proyek pembangunan Tiongkok bekerja, kini kita beralih ke para pelaku yang berada di garis depan pelaksanaan proyek: para mitra pelaksana. Di Indonesia, kelompok ini mencakup 213 pelaksana yang berhasil diidentifikasi, berasal dari 12 negara.
Tiongkok dikenal dengan praktik circular lending , yakni menggunakan perusahaan, tenaga kerja, dan rantai pasokan milik sendiri untuk menjalankan proyek pembangunan di luar negeri (Horn et al., 2019). Karena itu, tidak mengejutkan jika pelaksana terbesar kedua di Indonesia berasal dari Tiongkok, dengan total 92 entitas.
Namun menariknya, ketergantungan pada pelaksana asal Tiongkok di Indonesia tidak sebesar yang sering diasumsikan. Alih-alih didominasi penuh oleh kontraktor dari Negeri Tirai Bambu, komposisinya justru hampir seimbang: 90 entitas pelaksana dari Tiongkok dan 102 dari dalam negeri, meskipun perusahaan-perusahaan milik negara Tiongkok cenderung mendominasi daftar pelaksana secara global. [91]
Dari pelaksana asal Tiongkok, sekitar 55 persen adalah BUMN. Pola ini sejalan dengan desain Belt and Road Initiative (BRI) yang bertujuan menyalurkan kelebihan kapasitas di sektor konstruksi, baja, dan semen Tiongkok ke proyek-proyek luar negeri—mendukung kepentingan nasional sekaligus membuka pasar baru (Mathew & Custer, 2023). Beberapa nama yang paling sering muncul adalah China MCC17 Group (jasa konstruksi rekayasa) dan ZTE Corporation (solusi telekomunikasi). Pelaksana lain mencakup Sinohydro (pembangkit listrik tenaga air) hingga lembaga pemerintah seperti Kementerian Perdagangan Tiongkok (MOFCOM), Administrasi Penerbangan Sipil, dan Dewan Beasiswa Tiongkok.
Banyak BUMN Tiongkok dalam daftar ini berada di bawah pengawasan State-Owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) milik Dewan Negara RRT, yang pada akhirnya diarahkan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT). SASAC memegang peran penting dalam perekonomian terencana Tiongkok, mengatur arah dan produktivitas perusahaan-perusahaan milik negara yang memiliki total aset sekitar 976,22 miliar dolar AS (SASAC, 2025). [92] Selain Sinohydro, perusahaan besar lain yang aktif di Indonesia termasuk Power Construction of China (POWERCHINA) dan Dongfang Electric Corporation (DEC).
Di sisi lain, Beijing juga bekerja sama dengan 102 lembaga pelaksana dari Indonesia, mulai dari instansi pemerintah, BUMN, bank, perusahaan swasta, hingga organisasi masyarakat sipil. Di antara mereka, 28 persen adalah BUMN, 27 persen perusahaan swasta, dan 20 persen lembaga pemerintah. Pemerintah Indonesia (tanpa spesifikasi kementerian) tercatat menjalankan 26 proyek, mulai dari distribusi vaksin COVID-19 dan bantuan gempa bumi, hingga pembangunan fasilitas sanitasi. Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengerjakan sembilan proyek, berkolaborasi dengan perusahaan Tiongkok seperti Sinohydro dan DEC untuk memperluas kapasitas pembangkitan dan distribusi listrik nasional. Lembaga keuangan seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), Kementerian Perdagangan, dan Bank Rakyat Indonesia juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan proyek-proyek ini.
Tabel 3.5: Sembilan pelaksana utama proyek pembangunan yang didanai Tiongkok di Indonesia, 2000–2023
Pelaksana |
Jumlah proyek |
Pemerintah Indonesia |
26 |
|
Perusahaan Listrik Negara (PLN) |
9 |
|
PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) |
9 |
|
World Health Organization (WHO) |
9 |
|
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
6 |
China MCC17 Group Co. |
5 |
|
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
5 |
Kementerian Perdagangan |
5 |
ZTE Corporation |
5 |
Catatan: Tabel ini menunjukkan jumlah proyek yang melibatkan sembilan
pelaksana teratas dari proyek pembangunan yang didanai Tiongkok di
Indonesia. Hanya entitas yang melaksanakan lima proyek atau lebih yang
dimasukkan.
Sumber: AidData’s Global Chinese Development
Finance Dataset, Versi 3.0 untuk 2000–2021 (Custer et al., 2023;
Dreher et al., 2022). Dilengkapi dengan riset pustaka terbatas dan
peninjauan artikel media untuk mengidentifikasi proyek tambahan dan
detail terkait tahun 2022–2023.
Salah satu tanda meningkatnya koordinasi dan keselarasan antara pihak Tiongkok dan Indonesia adalah keberadaan 52 usaha patungan ( joint ventures atau JV) [93] dan kendaraan tujuan khusus ( special purpose vehicles atau SPV) [94] yang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan yang didanai Tiongkok di Indonesia. Salah satu contoh paling mencolok adalah PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), JV antara entitas Indonesia dan Tiongkok yang memimpin pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
Secara teori, JV dan SPV menawarkan sejumlah keuntungan. Mekanisme ini memungkinkan perusahaan kecil atau yang memiliki keahlian khusus untuk memperluas pasar dengan lebih efisien, membagi risiko dan sumber daya, serta mempermudah transfer teknologi dan pengetahuan yang dapat memicu inovasi. Namun, di sisi lain, kemitraan lintas negara semacam ini menuntut keterampilan negosiasi dan penyelesaian sengketa yang kuat (Miller et al., 1997), serta kemampuan memahami dan menjembatani perbedaan insentif, prioritas, dan strategi antarnegara. Risiko dapat meningkat jika terdapat ketimpangan kekuatan, seperti dalam beberapa JV atau SPV antara Tiongkok dan Indonesia, karena besarnya sumber daya yang dimiliki Tiongkok dapat memberi pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Apabila anggotanya merupakan BUMN, mekanisme ini juga berpotensi menyembunyikan sebagian kewajiban di luar neraca pemerintah, yang dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas (IMF, 2020).
Di sektor sosial, Tiongkok kerap bermitra dengan organisasi Islam lokal seperti NU CARE-LAZISNU [95] dan Muhammadiyah, maupun lembaga multilateral seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menjalankan program bantuan kemanusiaan. Mitra di sektor ini memiliki jaringan distribusi yang luas dan efektif, terutama untuk penyaluran bantuan darurat ke wilayah-wilayah terpencil. Kolaborasi semacam ini juga memberi keuntungan reputasi bagi Tiongkok, karena dapat “meminjam” kredibilitas lembaga yang sudah dipercaya masyarakat, sekaligus membangun citra positif di tingkat lokal.
Gambar 3.6: Penerima dan pelaksana proyek pembangunan yang didanai
Tiongkok di Indonesia, 2000–2023
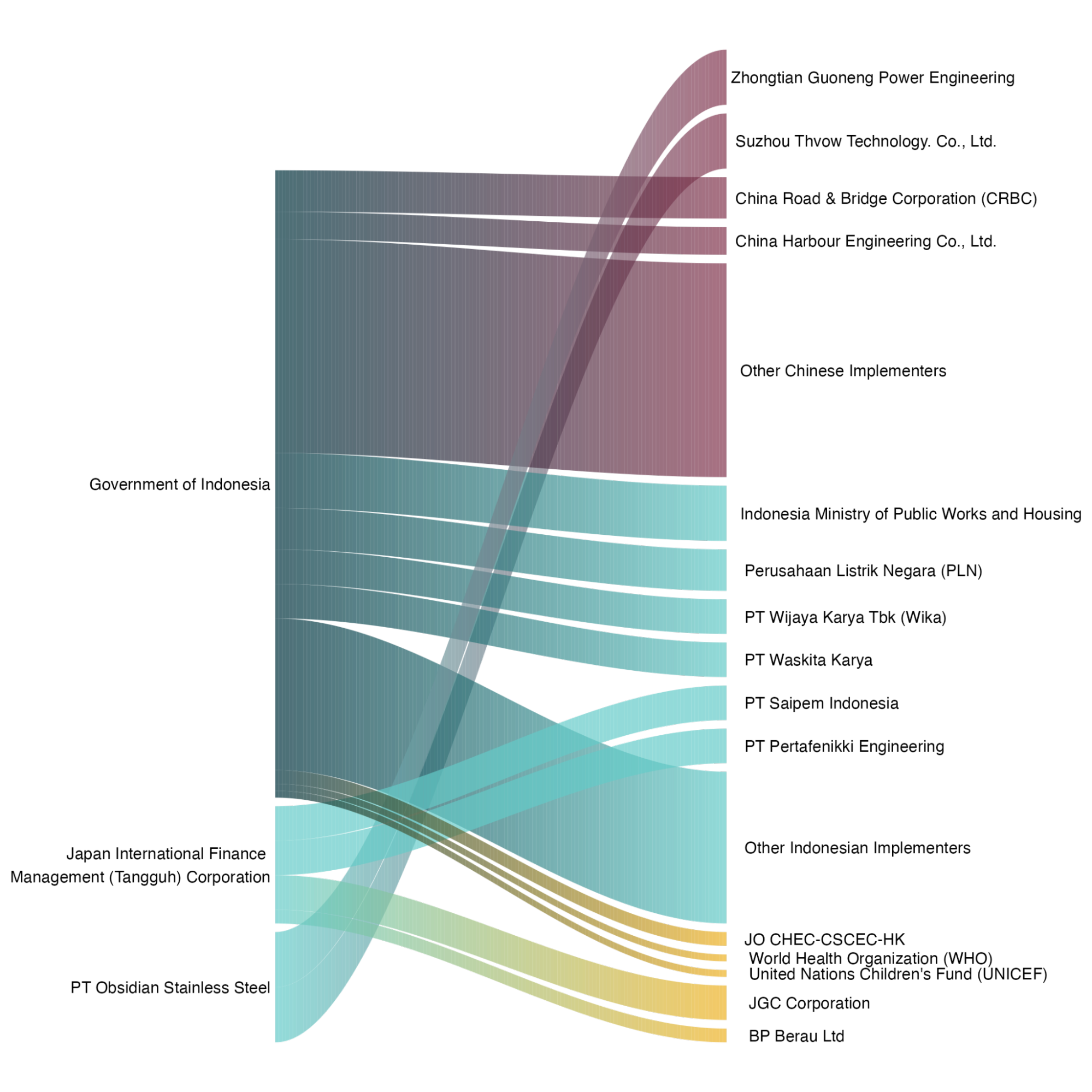
|
|
|
Pemerintah Indonesia |
|
|
|
|
Penerima-penerima lain |
|
|
|
|
Dari Indonesia |
|
|
|
|
Dari RRT |
|
|
|
|
Pelaksana lain |
|
Catatan: Ketebalan garis dalam gambar ini didasarkan pada jumlah
proyek. Gambar ini menggambarkan tren umum dalam hubungan antara
penerima utama proyek pembangunan yang didanai Tiongkok di Indonesia
dan para pelaksana proyeknya. Gambar ini tidak mewakili keseluruhan
data mengenai penerima dan pelaksana proyek.
Sumber: Global
Chinese Development Finance Dataset, Versi 3.0 untuk 2000–2021
(Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022) dari AidData. Dilengkapi
dengan riset pustaka terbatas dan peninjauan artikel media untuk
mengidentifikasi proyek tambahan dan detail lainnya untuk tahun
2022–2023.
Jika dilihat dari berbagai peran di sisi penyedia ( supply-side ), para pelaksana proyek menunjukkan cakupan sektor yang lebih beragam dibandingkan lembaga pembiayaan utama maupun lembaga pembiayaan bersama (lihat Tabel 3.7 di bawah). Meski demikian, bidang-bidang prioritas yang menonjol tetap sejalan dengan jenis proyek pembangunan yang paling sering didanai Beijing.
Konsentrasi terbesar pelaksana proyek ada pada infrastruktur fisik, mulai dari energi dan utilitas, konstruksi dan real estat , transportasi, hingga industri ekstraktif dan pertambangan, serta peningkatan kapasitas industri seperti sektor manufaktur. Pola ini sejalan dengan salah satu motivasi utama Beijing dalam pembiayaan pembangunan luar negeri dan Belt and Road Initiative (BRI): membuka akses terhadap bahan mentah, pasokan energi, dan pasar ekspor untuk barang dan jasa Tiongkok, sekaligus memperkuat konektivitas di dalam negeri maupun lintas negara (Mathew & Custer, 2023; Hillman & Sacks, 2021).
Tabel 3.7: Pemasok proyek pembangunan yang didanai Tiongkok di Indonesia menurut sektor dan peran, 2000–2023
Tabel dapat diurutkan dengan mengeklik kolom. Pada layar kecil, gulir secara horizontal untuk melihat kolom tersembunyi.
Sektor entitas |
Pendana |
Ko-pemdana |
Pelaksana |
|---|---|---|---|
Pertanian |
0 |
1 |
7 |
Konstruksi dan real estat |
3 |
1 |
44 |
Pendidikan |
3 |
0 |
16 |
Energi dan utilitas |
8 |
0 |
29 |
|
Industri ekstraktif dan pertambangan |
2 |
0 |
16 |
Jasa keuangan |
21 |
201 |
8 |
Makanan, minuman, dan tembakau |
0 |
0 |
0 |
Pemerintahan |
14 |
1 |
37 |
Industri |
1 |
2 |
25 |
Sosial |
0 |
1 |
7 |
Telekomunikasi |
3 |
1 |
6 |
Transportasi |
3 |
0 |
15 |
Penyediaan air dan sanitasi |
0 |
0 |
3 |
Catatan: Tabel ini mencantumkan jumlah penyandang dana, ko-penyandang
dana, dan pelaksana proyek pembangunan yang didanai Tiongkok di
Indonesia berdasarkan sektor. Suatu entitas dapat menjalankan lebih dari
satu peran.
Sumber: Global Chinese Development Finance Dataset,
Versi 3.0 untuk tahun 2000–2021 (Custer et al., 2023; Dreher et
al., 2022), dari AidData. Dilengkapi dengan riset meja terbatas dan
tinjauan artikel media untuk mengidentifikasi proyek tambahan dan detail
untuk tahun 2022–2023.
3.1.1 Pandangan terhadap pelaksana proyek asal Tiongkok di Indonesia
Selama dua dekade terakhir, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah membiayai dan melaksanakan proyek infrastruktur, baik fisik maupun digital, dalam skala besar, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Proyek-proyek ini berpotensi membawa perubahan besar bagi pasar dan masyarakat, namun juga menyimpan risiko bagi komunitas di sekitarnya.
Di lapangan, pelaksana proyek yang mengejar target penyelesaian secepat mungkin sering kali mengesampingkan protokol yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, atau tata kelola. Kurangnya transparansi dan persaingan dalam proses pemilihan perusahaan pelaksana proyek yang didanai RRT juga dapat memicu insentif negatif, termasuk kemungkinan terjadinya praktik keuangan yang dipertanyakan. Bab 4 akan membahas lebih dalam berbagai risiko dan konsekuensi tersebut pada tingkat portofolio proyek pembangunan yang didanai RRT di Indonesia. Sementara itu, bagian ini akan menyoroti analisis dari sudut pandang pelaksana proyek tertentu.
Pertanyaannya, seberapa besar risiko bekerja sama dengan suatu entitas di sisi penawaran proyek pembangunan? Untuk menilai hal ini, kami menggunakan basis data sanksi, daftar hitam ( debarment ), dan penangguhan dari Bank Dunia (n.d.) [96] serta Asian Development Bank (n.d.). [97] Jika suatu entitas tengah dikenai sanksi, atau pernah mengalaminya, hal tersebut tidak otomatis melarang mereka bekerja sama langsung dengan pemerintah atau perusahaan swasta di Indonesia. Meski begitu, data sanksi ini dapat menjadi alat penting untuk menilai reputasi entitas tersebut di mata dua lembaga keuangan antar-pemerintah ini. [98]
Tabel 3.8: Pelaksana asal Tiongkok di Indonesia yang dikenai sanksi atau pembatalan oleh Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia, 2000–2025 [99]
Nama lembaga |
Dikenai sanksi/dilarang oleh Bank Dunia atau Asian Development Bank? |
|
Chengdu Engineering Corp., Ltd. (CEC) |
Ya, sanksi tidak langsung sebagai afiliasi dari PowerChina, yang dilarang oleh ADB karena pelanggaran sanksi. |
|
China Construction Botswana Co. Ltd. |
Ya, sanksi tidak langsung sebagai afiliasi dari CSCEC, yang dilarang oleh Bank Dunia karena pelanggaran sanksi (Reuters, 2009). |
|
China Construction Eighth Engineering Division Corp., Ltd.
(CCEED)
|
Ya, sanksi tidak langsung sebagai afiliasi dari CSCEC, yang dilarang oleh Bank Dunia karena pelanggaran sanksi (Reuters, 2009). |
|
China Construction Fourth Engineering Division Corporation
Ltd.
|
Ya, sanksi tidak langsung sebagai afiliasi dari CSCEC, yang dilarang oleh Bank Dunia karena pelanggaran sanksi (Reuters, 2009). |
|
China Gezhouba Group Cement Co., Ltd. [aff. CEEC, Energy China] |
Ya, sanksi tidak langsung sebagai afiliasi dari CEEC dan Energy China, yang dilarang oleh Bank Dunia atas dasar penipuan dan korupsi. |
|
China Gezhouba Group Company Ltd. (CGGC) |
Ya, sanksi tidak langsung sebagai afiliasi dari CEEC dan Energy China, yang dilarang oleh Bank Dunia atas dasar penipuan dan korupsi. |
|
China Harbour Engineering Co., Ltd. (CHEC) [aff. CCCC] |
Ya, secara langsung dilarang oleh Bank Dunia pada tahun 2011. |
|
China Railway International Group Co Ltd (CRIG) |
Ya, sanksi tidak langsung sebagai afiliasi dari CRCC, yang dilarang oleh Bank Dunia pada tahun 2019. |
|
China Road and Bridge Corporation (CRBC) |
Ya, secara langsung dilarang oleh Bank Dunia, bersama dengan enam perusahaan lain dan satu individu, selama delapan tahun, dimulai pada 12 Januari 2009. |
|
China State Construction Engineering Corp Ltd. (CSCEC) |
Ya, secara langsung dilarang oleh Bank Dunia karena pelanggaran sanksi (Reuters, 2009). |
CSCEC Road and Bridge Group |
Ya, secara langsung dilarang oleh Bank Dunia karena pelanggaran sanksi (Reuters, 2009). |
|
Energy China |
Ya, sanksi tidak langsung sebagai afiliasi dari CEEC dan Energy China, yang dilarang oleh Bank Dunia atas dasar penipuan dan korupsi. |
|
Guangdong Power Engineering Corp (GDSBD) |
Ya, sanksi tidak langsung sebagai afiliasi dari CEEC dan Energy China, yang dilarang oleh Bank Dunia atas dasar penipuan dan korupsi. |
JO CHEC-CSCEC-HK |
Ya, sanksi tidak langsung sebagai afiliasi dari CSCEC, yang dilarang oleh Bank Dunia karena pelanggaran sanksi (Reuters, 2009). |
|
Power Construction Corporation of China (PowerChina) |
Ya, secara langsung dilarang oleh ADB karena pelanggaran sanksi. |
Catatan: Informasi mengenai sanksi diperoleh dari basis data daring
milik Bank Dunia dan Asian Development Bank terkait perusahaan yang
dikenai sanksi dan dilarang, serta dari siaran pers tambahan yang
dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut.
Sumber: Global Chinese
Development Finance Dataset milik AidData, Versi 3.0 untuk tahun
2000–2021 (Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022). Dilengkapi
dengan riset tambahan terbatas untuk mengidentifikasi proyek dan
rincian tambahan untuk tahun 2022–2023.
Kami mencocokkan 439 penyedia yang diketahui terlibat dalam proyek-proyek yang dibiayai oleh RRT di Indonesia, termasuk pemberi dana utama, mitra pendanaan bersama, dan pelaksana proyek, dengan basis data sanksi milik Bank Dunia (n.d.) dan Asian Development Bank (n.d.) untuk melihat apakah entitas-entitas tersebut sedang atau pernah dikenai larangan atau penangguhan (lihat Tabel 3.8 di atas). Hasilnya, empat belas dari lima belas entitas yang terkena sanksi dan beroperasi di Indonesia adalah perusahaan milik negara Tiongkok. Satu entitas lainnya merupakan usaha patungan ( joint venture ) antara Hutama Karya (BUMN konstruksi Indonesia), China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), dan China Harbor Engineering Company (CHEC).
Untuk memahami bagaimana kinerja dan kontribusi pelaksana proyek yang terkena sanksi atau larangan ini dibicarakan di ruang publik, kami menelusuri artikel-artikel di Factiva Dow Jones News and Analytics Database. Menariknya, hanya sedikit pemberitaan media yang secara spesifik membahas profil perusahaan-perusahaan ini, proyek-proyek yang mereka tangani di Indonesia, atau dampaknya bagi masyarakat lokal. [100] Temuan ini cukup kontras dengan hasil telaah serupa di Filipina pada 2024, di mana proyek-proyek pembangunan yang didanai RRT mendapat liputan media lokal dan perhatian publik yang jauh lebih intens (Custer et al., 2024).
Minimnya liputan atau dangkalnya pembahasan dalam pemberitaan terkait proyek-proyek dan pelaksana yang dibiayai RRT di Indonesia bisa jadi mencerminkan rendahnya visibilitas aktivitas-aktivitas ini atau kurangnya kepedulian publik terhadap relevansi sanksi di masa lalu dengan kinerja saat ini. Alternatifnya, kondisi ini mungkin mencerminkan perbedaan iklim media antara Indonesia dan Filipina. Beberapa pakar lokal yang diwawancarai untuk riset ini menilai, meskipun kebebasan pers di Indonesia membaik pasca-Suharto, tantangan besar masih dihadapi para jurnalis. [101] Analisis lebih lanjut mengenai bagaimana Tiongkok memanfaatkan media milik negara, jalur diplomasi, dan media sosial untuk memengaruhi narasi seputar proyek-proyek pembangunannya di Indonesia akan dibahas dalam laporan mendatang pada akhir 2025.
Salah satu contoh yang menarik adalah pemberitaan lokal terkait China State Construction Engineering Corp Ltd. (CSCEC). Perusahaan ini dikenai sanksi oleh Bank Dunia pada 2009 karena terlibat kolusi dalam penetapan harga saat mengikuti lelang proyek pembangunan jalan di Filipina (Reuters, 2009). Namun, reputasi tersebut tampaknya tidak banyak memengaruhi pemberitaan media di Indonesia terkait proyek-proyek CSCEC, yang tercatat aktif di Indonesia sejak setidaknya 2005. Liputan media mencatat beragam proyek CSCEC, mulai dari kerja sama dengan PT Hexa Prima Mekanikal untuk membangun infrastruktur energi (IDX Channel, 2024), pembangunan pabrik anoda baterai litium untuk PT Indonesia BTR New Energy Material (Perwata, Agustus 2024), hingga kegiatan yang lebih bersifat soft diplomacy seperti acara bersepeda untuk mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan (Sebayang, 2022). Bahkan, CSCEC juga mendapat sorotan positif saat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kawasan Ekonomi Khusus Batang Industropolis untuk membangun Two Countries Twin Park , [102] yang dipuji sebagai peluang penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi (Antara, 2025).
3.2 Sisi permintaan: Siapa penerima utama proyek investasi RRT di Indonesia?
Sisi pasokan dari pembiayaan pembangunan Beijing, sebagaimana dibahas di Bagian 3.1, hanyalah satu bagian dari keseluruhan cerita. Proyek-proyek yang dibiayai atau dijalankan oleh pihak Tiongkok tentu memerlukan mitra penerima yang siap dan bersedia terlibat. Dalam periode 2000 hingga 2023, tercatat ada 206 penerima proyek pembangunan yang didanai oleh Tiongkok di Indonesia, dan 87 persen di antaranya merupakan lembaga atau organisasi asal Indonesia.
Jika dilihat dari sektor penerima, hampir setengahnya, tepatnya 47 persen, terkait dengan infrastruktur fisik, mencakup konstruksi dan properti, energi dan utilitas, ekstraksi dan pertambangan, serta transportasi. Sektor telekomunikasi juga masuk dalam kelompok besar ini (Gambar 3.9). Selain itu, penerima lain yang cukup menonjol berada di sektor industri (15 persen), jasa keuangan (11 persen), pemerintahan (10 persen), dan pendidikan (7 persen).
Gambar 3.9: Penerima pendanaan Tiongkok di Indonesia menurut sektor, 2000–2023
Catatan: Gambar ini menggambarkan jumlah penerima langsung dan tidak
langsung—dari sisi permintaan—atas pembiayaan pembangunan
Tiongkok di Indonesia berdasarkan sektor.
Sumber: Global Chinese
Development Finance Dataset, Versi 3.0 untuk 2000–2021 (Custer
et al., 2023; Dreher et al., 2022). Dilengkapi dengan riset
kepustakaan terbatas dan tinjauan artikel media untuk mengidentifikasi
proyek tambahan dan rincian terkait untuk tahun 2022–2023.
Beijing paling sering menggandeng mitra dari sektor swasta Indonesia (lihat Tabel 3.10 di bawah), khususnya di bidang ekstraksi dan pertambangan, telekomunikasi, serta jasa keuangan. Mitra dari sektor publik juga cukup dominan, meliputi kementerian teknis, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, bank komersial, hingga universitas negeri. Menariknya, ada 13 organisasi dan kelompok Islam, termasuk masjid, LSM berbasis agama, dan lembaga Pendidikan, yang masuk dalam daftar penerima. Upaya Beijing membangun hubungan dengan kelompok mitra ini memiliki arti strategis, terutama sebagai bentuk diplomasi keagamaan untuk meraih simpati komunitas Muslim dan meredam kritik internasional terhadap kebijakan domestiknya terkait hak asasi manusia etnis Uighur di Provinsi Xinjiang (Rakhmat, 2022).
Hubungan ini tidak sebatas pada pemberian dana, tetapi juga diwujudkan melalui program beasiswa bagi pelajar Muslim serta undangan kunjungan ke Tiongkok bagi para pemimpin organisasi Islam yang berpengaruh.
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan dari RRT cenderung memprioritaskan penerima yang memiliki kedekatan bahasa, budaya, atau ikatan diaspora dengan Tiongkok daratan (Custer et al., 2024). Pola serupa juga tampak di Indonesia, meski tidak sejelas di Filipina. [103] Dari seluruh penerima langsung pendanaan Tiongkok, tercatat 44 di antaranya memiliki keterkaitan yang kuat dengan bahasa, budaya, atau diaspora Tionghoa. Ini termasuk universitas-universitas Indonesia yang menjadi tuan rumah Confucius Institutes, perusahaan teknologi asal Tiongkok, serta usaha patungan (joint venture/SPV) yang menjalankan program pelatihan bahasa Mandarin sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.
Selain itu, ada 34 penerima langsung yang memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan atau individu asal Tiongkok, mencakup perusahaan dan JV/SPV dengan pemegang saham mayoritas dari Tiongkok. Sinar Mas Group menjadi salah satu contoh menonjol. Sebagai salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, [104] Sinar Mas didirikan oleh Eka Tjipta Widjaja, yang bermigrasi dari Tiongkok saat masih anak-anak.
Tabel 3.10: Penerima proyek pembangunan yang didanai Tiongkok di Indonesia, 2000-2023
Catatan: Gambar ini menggambarkan jumlah dan jenis entitas yang
menerima pendanaan pembangunan dari Tiongkok di Indonesia.
Sumber:
AidData’s Global Chinese Development Finance Dataset, Versi 3.0
untuk 2000–2021 (Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022).
Dilengkapi dengan riset meja terbatas dan peninjauan artikel media
untuk mengidentifikasi proyek tambahan dan detail untuk tahun
2022–2023.
Beijing memiliki rekam jejak dalam menargetkan wilayah subnasional yang kaya sumber daya alam dan strategis secara politik sebagai prioritas dalam pembiayaan pembangunan globalnya (Escobar et al., 2025). Pola ini juga tampak jelas di Indonesia. Sebanyak 68 persen penerima asal Indonesia berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (lihat Tabel 3.11 di bawah). [105] Angka ini tidak mengejutkan, mengingat mayoritas lembaga keuangan, kantor pusat perusahaan, dan kementerian pemerintah berada di ibu kota historis tersebut.
Selain Jakarta, sejumlah provinsi lain juga muncul sebagai prioritas bagi penyandang dana Tiongkok. Di antaranya adalah Jawa Timur (14 penerima), Jawa Tengah (7 penerima), Jawa Barat (9 penerima), Sumatera Utara (11 penerima), dan Sumatera Selatan (8 penerima). [106] Preferensi ini sejalan dengan temuan lain terkait pembiayaan pembangunan luar negeri RRT, yaitu kecenderungan mengalirkan dana ke basis konstituen presiden (Dreher et al., 2022). Tiga presiden Indonesia terakhir—Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Susilo Bambang Yudhoyono—sama-sama memiliki ikatan keluarga yang kuat dengan Pulau Jawa.
Signifikansi Jawa makin terlihat ketika kita melihat bagaimana provinsi-provinsinya menjadi tujuan berbagai bentuk diplomasi publik RRT, yang bertujuan membangun kedekatan dengan para pemimpin daerah dan masyarakat lokal. Dalam analisis ini, distribusi subnasional dari instrumen-instrumen standar diplomasi publik Beijing—seperti Institut Konfusius, Lokakarya Luban, dan perjanjian kota kembar—menunjukkan bahwa Jawa adalah salah satu target utama. Empat provinsi dan dua daerah khusus ibu kota di pulau ini secara kolektif menyerap 28 inisiatif diplomasi publik dari RRT, atau sekitar 60 persen dari seluruh portofolio mereka di Indonesia.
Tabel 3.11: Penerima proyek pembangunan yang didanai Tiongkok dan diplomasi publik Tiongkok menurut wilayah, 2000–2023
Tabel dapat diurutkan dengan mengeklik kolom. Pada layar kecil, gulir secara horizontal untuk melihat kolom tersembunyi.
Wilayah |
Provinsi |
Jumlah penerima |
Jumlah inisiatif diplomasi |
Jawa |
Banten |
7 |
0 |
| Jawa | Jawa Tengah |
7 |
4 |
| Jawa | Jawa Timur |
14 |
11 |
| Jawa | DKI Jakarta |
181 |
2 |
| Jawa | DI Yogyakarta |
2 |
1 |
| Jawa | Jawa Barat |
9 |
10 |
Kalimantan |
Kalimantan Tengah |
1 |
0 |
| Kalimantan | Kalimantan Timur |
2 |
0 |
| Kalimantan | Kalimantan Utara |
1 |
0 |
| Kalimantan | Kalimantan Selatan |
1 |
2 |
| Kalimantan | Kalimantan Barat |
1 |
4 |
Kepulauan Maluku |
Maluku |
1 |
1 |
Bali |
Bali |
3 |
4 |
Nusa Tenggara |
Nusa Tenggara Timur |
0 |
1 |
| Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Barat |
1 |
0 |
Papua |
Papua |
1 |
0 |
| Papua | Papua Barat |
1 |
0 |
Sulawesi |
Sulawesi Tengah |
2 |
0 |
| Sulawesi | Gorontalo |
1 |
0 |
| Sulawesi | Sulawesi Utara |
3 |
0 |
| Sulawesi | Sulawesi Selatan |
4 |
2 |
Sumatra |
Bengkulu |
1 |
0 |
| Sumatra | Jambi |
1 |
0 |
| Sumatra | Sumatra Utara |
11 |
1 |
| Sumatra | Riau |
2 |
2 |
| Sumatra | Kepulauan Riau |
1 |
1 |
| Sumatra | Sumatra Selatan |
8 |
1 |
| Sumatra | Sumatra Barat |
1 |
1 |
Catatan: Tabel ini menunjukkan jumlah organisasi dari suatu wilayah
subnasional yang disebut sebagai penerima proyek pembiayaan
pembangunan Tiongkok. Inisiatif diplomasi publik mencatat jumlah
penerima dari wilayah yang sama yang menerima satu atau lebih dari
hal-hal berikut: Institut atau Kelas Konfusius, perjanjian
kota/provinsi kembar, atau Lokakarya Luban.
Sumber:
AidData’s Global Chinese Development Finance Dataset, Versi 3.0
untuk tahun 2000–2021 (Custer et al., 2023; Dreher et al.,
2022); AidData Global Chinese Public Diplomacy Dataset, 2021.
Dilengkapi dengan riset pustaka terbatas dan peninjauan artikel media
untuk mengidentifikasi proyek tambahan dan detail terkait untuk tahun
2022–2023.
3.2.1 Perusahaan dan lembaga mana yang paling terdampak oleh keterlibatan Beijing?
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan perusahaan patungan (JV/SPV) di empat sektor utama, transportasi, energi dan utilitas, ekstraktif dan pertambangan, serta jasa keuangan, menjadi magnet besar bagi pembiayaan pembangunan Tiongkok. Salah satu contohnya adalah Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan yang menggarap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang menerima pendanaan lebih besar daripada gabungan tiga penerima dana terbesar berikutnya. BUMN besar lainnya seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Bank Rakyat Indonesia, dan Garuda Indonesia (maskapai penerbangan nasional) juga masuk jajaran penerima dana terbesar.
BUMN atau lembaga pemerintah Indonesia memang kerap tercatat sebagai peminjam resmi atau penerima langsung pembiayaan pembangunan dari Tiongkok. Namun, hal ini bukan berarti mereka sepenuhnya bebas menentukan arah proyek. Sejak 2018 hingga 2024, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memegang peran penting dalam memberikan arahan strategis dan mengelola risiko proyek. Setiap usulan proyek harus melalui tinjauan Komite Pengarah Bersama Indonesia–Tiongkok ( Joint Steering Committee/JSC ) sebelum BUMN atau kementerian terkait bisa menandatangani perjanjian pinjaman atau membentuk perusahaan patungan. Setelah mendapat lampu hijau dari JSC, Kementerian Keuangan akan menilai risiko fiskal, dan jika perlu, mengeluarkan jaminan pemerintah ( sovereign guarantee ) sebelum utang resmi tercatat di neraca BUMN tersebut.
Meski koordinasi nasional terbilang ketat, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah tidak selalu mulus. Beberapa pakar yang diwawancarai dalam penelitian ini menyoroti bahwa pemerintah daerah kerap merasa tersisih dan kurang mendapat informasi memadai soal proyek-proyek yang dibiayai Tiongkok di wilayah mereka. Proses di tingkat pusat pun tidak sepenuhnya steril dari pengaruh tertentu. Contohnya dapat dilihat pada dukungan Tiongkok terhadap Institut Teknologi Del, sebuah yayasan pendidikan tinggi di Sumatra Utara yang didirikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Widodo. Pada 2018, Institut Del menerima sumbangan buku dan meja dari Kedutaan Besar Tiongkok. Lalu pada 2024, universitas-universitas Tiongkok diundang untuk menjalin kerja sama riset dengan lembaga tersebut.
Menariknya, penerima dana terbesar dalam nilai dolar tidak selalu menjadi pihak dengan jumlah proyek terbanyak. Fenomena ini bukan hal baru, mengingat Tiongkok memang sering membiayai proyek sosial dan pendidikan berskala kecil sebagai bentuk goodwill, bersamaan dengan proyek-proyek raksasa di bidang pembangkitan listrik, ekstraksi mineral strategis, dan transportasi massal. Hanya sekitar 7 persen penerima yang terlibat dalam lima proyek atau lebih, sementara dua pertiga lainnya hanya mengelola satu proyek (lihat Tabel 3.13).
Meski begitu, ada enam entitas yang berhasil “menembus pola” ini dan berkali-kali menerima suntikan dana pembangunan Tiongkok dalam jumlah besar. Mereka adalah Pemerintah Indonesia (kementerian tidak disebutkan), Perusahaan Listrik Negara, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Bank Rakyat Indonesia, Garuda Indonesia, serta dua perusahaan telekomunikasi swasta: Smart Telecom dan Smartfren. Jika kedua nama terakhir digabungkan dengan induknya, Sinar Mas Group, maka posisinya akan naik menjadi penerima dana terbesar keempat. [107] Selain BUMN, konglomerasi swasta besar juga ikut meraup pembiayaan Tiongkok, seperti Grup Bakrie (Bumi Resources, Bakrie Telecom, dan Bakrie Autoparts) serta anak usaha CT Corp milik Chairul Tanjung (Trans Retail Indonesia dan Trans Media Corpora).
Tabel 3.12: Lima belas penerima utama pendanaan Tiongkok di Indonesia berdasarkan nilai proyek, 2000–2023
Nama entitas |
Tipe entitas |
Sektor |
Pendanaan RRT, juta dolar AS |
|
Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) |
Usaha patungan/Lembaga tujuan khusus |
Transportasj |
22.525 |
Pemerintah Indonesia |
Pemerintah negara |
Pemerintah |
8.478 |
|
Perusahaan Listrik Negara (PLN) |
BUMN |
Energi dan utilitas |
7.494 |
Bumi Resources Tbk (Bumi) |
Sektor swasta |
Ekstraksi dan penambangan |
3.981 |
|
Japan International Finance Management (Tangguh) Corporation |
Usaha patungan/Lembaga tujuan khusus |
Layanan keuangan |
3.667 |
|
Sumber Segara Primadaya (S2P) |
Usaha patungan/Lembaga tujuan khusus |
Energi dan utilitas |
3.446 |
Garuda Indonesia |
BUMN |
Transportasi |
2.456 |
|
OKI Pulp and Paper Mills (OKI) |
Usaha patungan/Lembaga tujuan khusus |
Industri |
2.271 |
|
Smart Telecom (Smartel) + Smartfren |
Sektor swasta |
Telekomunikasi |
2.229 |
Aneka Tambang Tbk |
BUMN |
Ekstraksi dan penambangan |
2.061 |
Sinar Mas Group |
Sektor swasta |
Layanan keuangan |
1.896 |
|
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
Bank BUMN |
Layanan keuangan |
1.809 |
|
Shenhua Guohua Power Jawa Bali |
Usaha patungan/Lembaga tujuan khusus |
Energi dan utilitas |
1.742 |
|
Huadian Bukit Asam Power (HBAP) |
Usaha patungan/Lembaga tujuan khusus |
Energi dan utilitas |
1.536 |
|
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) |
Bank BUMN |
Layanan keuangan |
1.489 |
Catatan: Tabel ini memeringkat 15 penerima pendanaan pembangunan Tiongkok teratas. Smart Telecom (Smartel) dan Smartfren, keduanya merupakan anak perusahaan telekomunikasi dari Grup Sinar Mas (yang juga dicantumkan secara terpisah), telah digabungkan dalam tabel ini. Sumber: AidData’s Global Chinese Development Finance Dataset, Versi 3.0 untuk tahun 2000–2021 (Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022). Dilengkapi dengan riset pustaka terbatas dan peninjauan artikel media oleh tim peneliti untuk mengidentifikasi proyek tambahan dan detail terkait tahun 2022–2023.
Tabel 3.13: Lima belas penerima utama pendanaan pembangunan Tiongkok di Indonesia berdasarkan jumlah proyek, 2000–2023
Tabel dapat diurutkan dengan mengeklik kolom. Pada layar kecil, gulir secara horizontal untuk melihat kolom tersembunyi.
Nama entitas |
Tipe entitas |
Jumlah proyek |
Pendanaan RRT, Juta dolar AS |
|---|---|---|---|
Pemerintah Indonesia* |
Pemerintah negara |
77 |
8,478 |
|
Perusahaan Listrik Negara (PLN)* |
BUMN |
19 |
7,494 |
|
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)* |
Bank BUMN |
10 |
1,489 |
|
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* |
Bank BUMN |
8 |
1,809 |
Solusi Tunas Pratama (STP) |
Sektor swasta |
8 |
62,5 |
|
World Health Organization (WHO) |
Organisasi antarpemerintah |
8 |
5,94 |
Garuda Indonesia* |
BUMN |
6 |
2.456 |
|
Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) |
BUMN |
6 |
229 |
|
Smart Telecom (Smartel) + Smartfren Telecom Tbk* |
Sektor swasta |
6 |
2.229 |
|
Medco Energi Internasional Tbk |
Sektor swasta |
5 |
102,6 |
MNC Cable Mediacom (MKM) |
Sektor swasta |
5 |
335 |
MNC Finance (MNCF) |
Sektor swasta |
5 |
20,97 |
Pertamina (Persero) |
BUMN |
5 |
493 |
|
Radana Bhaskara Finance Tbk (formerly PT HD Finance Tbk) |
Sektor swasta |
5 |
41,05 |
Trans Retail Indonesia |
BUMN |
5 |
279 |
Catatan: Tabel ini memeringkat 15 penerima pendanaan pembangunan
Tiongkok teratas berdasarkan jumlah proyek. Entitas yang diikuti tanda
asterisk juga tercantum dalam daftar 15 entitas teratas dengan nilai
pendanaan Tiongkok terbesar ( Tabel 3.12 di atas). Smart Telecom
(Smartel) dan Smartfren, keduanya anak perusahaan telekomunikasi dari
Grup Sinar Mas, telah digabungkan dalam tabel ini.
Sumber:
AidData’s Global Chinese Development Finance Dataset, Versi 3.0
untuk tahun 2000–2021 (Custer et al., 2023; Dreher et al.,
2022). Dilengkapi dengan riset pustaka terbatas dan peninjauan artikel
media untuk mengidentifikasi proyek tambahan dan detail terkait tahun
2022–2023.
4. Hasil dan Dampak
Wawasan utama dalam bab ini:
- Dalam portofolio Beijing, proyek-proyek di sektor energi dan transportasi menjadi yang paling berisiko, dengan tingkat keterlambatan pelaksanaan tinggi serta sorotan negatif terkait isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
- Lebih dari 40 persen portofolio pembiayaan pembangunan Beijing di Indonesia, setara dengan 30 miliar dolar AS, bergantung pada pelaksana yang kami nilai memiliki risiko tinggi.
- Beijing menghadapi tantangan besar untuk mengubah pembiayaan ini menjadi keuntungan reputasi. Tingkat persetujuan publik terhadapnya cenderung menurun, sementara kalangan elit semakin waspada terhadap pengaruhnya.
- Masyarakat Indonesia tampaknya tengah mendefinisikan ulang makna demokrasi yang “memberikan hasil”, dengan menempatkan pembangunan ekonomi di atas hak-hak politik,sebuah pendekatan yang selaras dengan narasi dan tawaran nilai yang diusung Beijing.
Kesediaan Tiongkok membiayai proyek infrastruktur berskala besar membawa peluang sekaligus risiko. Di satu sisi, investasi ini bisa mempercepat tercapainya tujuan pembangunan: memperluas akses layanan dasar, meningkatkan produktivitas pertanian dan industri, serta memperkuat konektivitas melalui perbaikan jalan, pelabuhan, dan jaringan kereta api. Namun di sisi lain, proyek-proyek tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak kecil, seperti merusak ekosistem yang sensitif, menggusur masyarakat miskin dan komunitas adat, hingga melemahkan tata kelola dengan memperbesar peluang korupsi dan mengurangi transparansi.
Seiring Indonesia bergerak menuju keanggotaan OECD, ada peluang untuk mendorong akuntabilitas yang lebih kuat melalui mekanisme seperti OECD’s Common Reporting Standard (CRS), yang dapat meningkatkan transparansi dalam pembiayaan pembangunan.
Bab ini membahas kinerja Beijing sebagai mitra pembangunan di Indonesia, sejauh mana komitmen yang telah dijanjikan benar-benar terealisasi, bagaimana mereka mengelola risiko terhadap kepentingan publik dari proyek-proyek tersebut, serta tanda-tanda awal yang dapat memberi gambaran mengenai hasil jangka panjangnya. Untuk menjawab hal ini, kami menggunakan data tingkat proyek dari AidData terkait pembiayaan pembangunan oleh RRT, [108] dipadukan dengan riset meja dan informasi tambahan tentang langkah mitigasi risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang diterapkan dalam proyek-proyek yang dibiayai Beijing.
4.1. Sejauh mana Tiongkok merealisasikan investasi yang dijanjikan tepat waktu dan sesuai komitmen?
Investasi pembiayaan pembangunan yang digelontorkan Beijing di Indonesia kerap digambarkan, baik oleh pejabat pemerintah maupun media, sebagai langkah transformatif yang mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, memperlancar arus perdagangan, dan mendorong produktivitas ekonomi. Namun, semua potensi itu hanya bisa terwujud jika Beijing mampu menepati komitmennya, yakni mengubah janji pendanaan menjadi hasil nyata di lapangan.
Karena RRT cenderung membiayai proyek-proyek infrastruktur berskala besar, kompleks secara teknis, dan sensitif secara politik, proses pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan berat dan memakan waktu panjang. Dalam bagian ini, kami menilai sejauh mana Beijing mampu menindaklanjuti komitmennya dari dua sudut pandang: pertama, rata-rata waktu yang dibutuhkan sejak komitmen pendanaan disampaikan hingga proyek benar-benar terealisasi (bagian 4.1.1); dan kedua, seberapa sering terjadi penangguhan atau pembatalan proyek (bagian 4.1.2).
4.1.1 Dari janji ke pelaksanaan: Seberapa cepat aliran dana terjadi?
Beijing sering mendapat pujian karena dinilai mampu merampungkan proyek infrastruktur dengan cepat. Namun, cerita di Indonesia ternyata jauh lebih beragam. Konsistensi pelaksanaan proyek yang tepat waktu dan sesuai komitmen awal bervariasi cukup tajam. Rata-rata, proyek yang dibiayai RRT di Indonesia memerlukan sekitar 2,5 tahun sejak komitmen pendanaan dibuat hingga proyek selesai diserahkan. Dari waktu tersebut, 155 hari dihabiskan dari komitmen hingga pelaksanaan dimulai, dan 706 hari dari awal pelaksanaan hingga rampung. Angka ini menunjukkan bahwa proses di Indonesia berjalan lebih lambat dibandingkan negara ASEAN sebanding, seperti Filipina (lihat Custer et al., 2024). Rincian rata-rata waktu tunggu untuk setiap fase proyek dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah.
Rata-rata ini, tentu saja, menyamarkan perbedaan mencolok di tingkat daerah. [109] Misalnya, di Bengkulu, Gorontalo, dan Jambi, proyek-proyek yang dibiayai RRT rata-rata memakan waktu lebih dari lima tahun sejak komitmen hingga selesai. Faktor seperti aksesibilitas lokasi dan kualitas infrastruktur lokal mungkin berperan dalam memperlambat progres, namun alasan ini tidak sepenuhnya menjelaskan lambatnya penyelesaian proyek di daerah yang lebih mudah diakses seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang masing-masing membutuhkan waktu sekitar tiga tahun. Sebaliknya, Papua Tengah mencatat kecepatan luar biasa, dengan proyek yang dimulai dan selesai hanya dalam hitungan minggu. [110] Aceh dan Yogyakarta juga relatif cepat, dengan waktu penyelesaian rata-rata kurang dari satu tahun.
Jenis keterlambatan pun berbeda-beda di tiap provinsi. Di Kepulauan Riau (830 hari) dan Kalimantan Selatan (457 hari), misalnya, hambatan utama terjadi pada jeda waktu antara komitmen pendanaan awal, yang sering dimulai dengan penandatanganan MoU atau perjanjian, dan dimulainya kegiatan proyek. Ada pula daerah yang memulai proyek dengan cepat, tetapi melambat di tahap pelaksanaan. Kalimantan Timur menjadi contoh menonjol: meski rata-rata hanya 139 hari dari komitmen hingga proyek dimulai, lima proyek di provinsi ini membutuhkan rata-rata 3.877 hari untuk benar-benar diselesaikan.
Tabel 4.1: Rata-rata waktu antar tahap proyek pembangunan yang didanai RRT di Indonesia, 2000–2022
Tabel dapat diurutkan dengan mengeklik kolom. Pada layar kecil, gulir secara horizontal untuk melihat kolom tersembunyi.
Provinsi |
Janji → pelaksanaan (hari) |
Pelaksanaan → penyelesaian (hari) |
Janji → penyelesaian (hari) |
Proyek dengan data waktu yang tidak lengkap |
|---|---|---|---|---|
Indonesia, keseluruhan |
155 |
706 |
678 |
381 |
Aceh |
136 |
248 |
312 |
3 |
Bali |
163 |
545 |
591 |
4 |
Banten |
400 |
1332 |
1027 |
16 |
Bengkulu |
126 |
1952 |
2078 |
0 |
Jawa Tengah |
150 |
1188 |
1132 |
6 |
Kalimantan Tengah |
- |
- |
- |
1 |
Papua Tengah |
16 |
6 |
21 |
0 |
Sulawesi Tengah |
188 |
638 |
654 |
11 |
Jawa Timur |
142 |
1010 |
816 |
18 |
Kalimantan Timur |
139 |
3877 |
970 |
5 |
Nusa Tenggara Timur |
0 |
0 |
0 |
1 |
Gorontalo |
276 |
1562 |
1838 |
1 |
DKI Jakarta |
286 |
612 |
505 |
17 |
Jambi |
276 |
1562 |
1838 |
0 |
Lampung |
120 |
1290 |
864 |
1 |
Maluku |
- |
- |
- |
1 |
Kalimantan Utara |
334 |
- |
- |
3 |
Maluku Utara |
124 |
874 |
1210 |
6 |
Sulawesi Utara |
305 |
1495 |
1002 |
5 |
Sumatra Utara |
101 |
768 |
663 |
15 |
Papua |
0 |
0 |
0 |
1 |
Riau |
- |
2821 |
995 |
3 |
Kepulauan Riau |
830 |
611 |
1441 |
2 |
Kalimantan Selatan |
457 |
976 |
1126 |
4 |
Sulawesi Selatan |
60 |
1040 |
838 |
2 |
Sumatra Selatan |
81 |
991 |
877 |
7 |
Sulawesi Tenggara |
97 |
1144 |
1241 |
2 |
DI Yogyakarta |
139 |
14 |
188 |
1 |
Jawa Barat |
280 |
1415 |
1126 |
19 |
Kalimantan Barat |
179 |
1624 |
1328 |
4 |
Nusa Tenggara Barat |
0 |
0 |
592 |
2 |
Papua Barat |
- |
1588 |
630 |
5 |
Sumatra Barat |
- |
- |
1317 |
3 |
Catatan: Mengingat keterbatasan informasi yang tersedia untuk publik,
tidak semua proyek yang dibiayai RRT memiliki geokode pada tingkat
provinsi. Beberapa proyek tidak memiliki tanggal pelaksanaan atau
penyelesaian; dalam kasus-kasus tersebut, rata-rata waktu dari
komitmen hingga penyelesaian tidak sepenuhnya selaras. Tanda strip
menunjukkan provinsi-provinsi yang hanya memiliki informasi tanggal
secara parsial, sehingga tidak memungkinkan perhitungan rata-rata
durasi untuk satu atau lebih tahapan.
Sumber: AidData’s
Global Chinese Development Finance Dataset, Version 3.0 (Custer et
al., 2023; Dreher et al., 2022).
Seperti dibahas di Bab 2, Beijing mendanai proyek-proyek pembangunan di berbagai sektor. Hal ini membuat jenis proyek yang dibangun sama pentingnya, bahkan terkadang lebih berpengaruh daripada lokasi pembangunannya, dalam menentukan seberapa cepat proyek yang dibiayai RRT bisa dimulai dan diselesaikan. Tabel 4.2 di bawah merinci rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan pada tiap tahap utama siklus proyek—mulai dari komitmen, pelaksanaan, hingga penyelesaian—untuk masing-masing sektor.
Secara umum, Beijing tampak mampu meraih hasil cepat di sektor-sektor dengan cakupan sempit atau dalam situasi darurat. Sebaliknya, proyek infrastruktur skala besar justru cenderung memakan waktu lebih lama. Sektor yang berkaitan erat dengan infrastruktur fisik dan digital—seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi—memiliki jeda lebih dari 1.000 hari dari komitmen hingga penyelesaian. Hal ini wajar, mengingat kompleksitas yang menyertainya: mulai dari pembebasan lahan, kajian dampak lingkungan, koordinasi antar-kontraktor, hingga kesiapan kapasitas lokal untuk menyerap investasi besar. Sebaliknya, proyek-proyek bantuan pangan atau tanggap darurat biasanya memiliki sifat jangka pendek dan urgensi tinggi, sehingga dapat diselesaikan jauh lebih cepat.
Salah satu contoh nyata adalah proyek unggulan Beijing, Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Diumumkan pada 2015, proyek ini tertunda akibat serangkaian hambatan—mulai dari pembebasan lahan dan peninjauan lingkungan hingga dampak pandemi COVID-19 (lihat Kotak 2 di Bab 2). Target penyelesaian yang awalnya ditetapkan pada 2019 mundur hingga Oktober 2023. Biayanya pun melonjak dari 4,3 miliar dolar AS menjadi 7,3 miliar dolar AS (Ibrahim dan Karmini, 2023). Seorang pakar yang diwawancarai bahkan menyebut proyek ini sebagai upaya yang lebih didorong ambisi ketimbang pertimbangan ekonomi, dengan ekspektasi yang terlalu tinggi dan manfaat yang belum terbukti nyata.
Tabel 4.2: Rata-rata waktu antar tahap proyek pembangunan yang didanai RRT di Indonesia menurut sektor, 2000–2022
Tabel dapat diurutkan dengan mengeklik kolom. Pada layar kecil, gulir secara horizontal untuk melihat kolom tersembunyi.
Nama sektor |
Janji → pelaksanaan (hari) |
Pelaksanaan → penyelesaian (hari) |
Janji → penyelesaian (hari) |
Proyek dengan data waktu yang tidak lengkap |
|---|---|---|---|---|
|
Tindakan berkaitan dengan utang |
- |
2070 |
597 |
10 |
|
Pertanian, kehutanan, perikanan |
195 |
1173 |
1440 |
8 |
|
Layanan perbankan dan keuangan |
0 |
- |
1100 |
20 |
Layanan bisnis dan lainnya |
8 |
96 |
197 |
34 |
|
Bantuan mekanan untuk pembangunan/bantuan ketahanan pangan |
0 |
0 |
102 |
4 |
Pendidikan |
85 |
84 |
204 |
17 |
Tanggap darurat |
72 |
14 |
87 |
12 |
Energi |
194 |
1583 |
1566 |
39 |
|
Perlindungan lingkungan seara umum |
345 |
0 |
345 |
0 |
|
Pemerintah dan organisasi kemasyarakatab |
72 |
0 |
72 |
4 |
Kesehatan |
132 |
20 |
218 |
8 |
|
Industri, pertambangan, konstruksi |
319 |
1240 |
1035 |
62 |
Multisektor lain |
306 |
1158 |
710 |
13 |
|
Infrastruktur sosial dan layanan lain |
804 |
- |
- |
7 |
|
Bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi |
571 |
30 |
822 |
1 |
Telekomunikasi |
308 |
835 |
1825 |
16 |
|
Kebijakan dan regulasi dagang |
- |
- |
486 |
6 |
Pengangkutan dan pergudangan |
161 |
1696 |
1088 |
36 |
|
Tanpa alokasi/tidak didefinisikan |
0 |
776 |
776 |
25 |
Pasokan air dan santiasi |
- |
- |
714 |
2 |
Catatan: Angka nol menunjukkan waktu tunggu antar-tahap proyek yang
nyaris tak terlihat, mengindikasikan bahwa proyek-proyek ini
kemungkinan besar langsung dilaksanakan dan diselesaikan segera
setelah dikomitmenkan. Tanda strip menunjukkan sektor-sektor yang
hanya memiliki informasi tanggal secara parsial, sehingga tidak
memungkinkan perhitungan rata-rata durasi untuk satu atau lebih tahap
proyek. Tabel ini mencakup semua sektor yang memiliki setidaknya
sebagian data tanggal; sektor-sektor yang sama sekali tidak memiliki
informasi tanggal tidak disertakan.
Sumber: AidData’s
Global Chinese Development Finance Dataset, Version 3.0 (Custer et
al., 2023; Dreher et al., 2022).
Jenis pembiayaan juga berpengaruh besar terhadap cepat atau lambatnya jadwal pelaksanaan proyek. Bantuan yang sifatnya mirip hibah, seperti hibah langsung, dukungan dalam bentuk barang, atau pinjaman tanpa bunga maupun berbunga rendah, umumnya bergerak cepat dalam siklus proyek. Rata-rata, proyek-proyek di kategori ini bisa rampung dalam 294 hari, dengan jeda waktu yang relatif singkat antara komitmen, pelaksanaan, dan penyelesaian (lihat Tabel 4.3 di bawah).
Sebaliknya, bantuan yang berbentuk utang, terutama pinjaman komersial dengan tingkat konsesi rendah, cenderung memiliki jadwal yang jauh lebih panjang. Proyek di kategori ini rata-rata memerlukan waktu lebih dari 1.000 hari sejak komitmen awal hingga benar-benar selesai.
Tabel 4.3: Rata-rata waktu antar tahap proyek pembangunan yang didanai RRT di Indonesia menurut jenis aliran dana, 2000–2022
Tabel dapat diurutkan dengan mengeklik kolom. Pada layar kecil, gulir secara horizontal untuk melihat kolom tersembunyi.
Jenis aliran dana |
Janji → pelaksanaan (hari) |
Pelaksanaan → penyelesaian (hari) |
Janji → penyelesaian (hari) |
Proyek dengan data waktu yang tidak lengkap |
|---|---|---|---|---|
Seperti ODA |
95 |
129 |
294 |
54 |
Seperti OOF |
210 |
1267 |
1007 |
239 |
Kabur (keuangan resmi) |
71 |
1168 |
1013 |
31 |
Sumber: AidData’s Global Chinese Development Finance Dataset, Version 3.0 (Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022).
Poin ini menegaskan satu hal penting: lamanya masa pelaksanaan proyek tidak selalu berarti ada penundaan akibat pelaksanaan yang buruk atau kurangnya komitmen. Seperti yang dibahas di Bab 2, Beijing umumnya menerapkan model dua jalur dalam pembiayaan pembangunannya. Strateginya sering kali menggabungkan proyek infrastruktur berskala besar yang dibiayai dengan utang, dengan proyek-proyek sektor sosial yang bersifat goodwill dan dibiayai melalui bantuan. Dalam kerangka ini, wajar jika Beijing mampu merealisasikan kegiatan yang sifatnya mirip bantuan, seperti mendonasikan pasokan, mengadakan pelatihan, atau menyediakan dana darurat, lebih cepat dibandingkan pinjaman sindikasi untuk proyek komersial seperti pembangkit listrik, jalan raya, atau jalur kereta api.
4.1.2 Gagal terealisasi? Penangguhan dan pembatalan proyek
Selain kecepatan pelaksanaan, cara lain untuk menilai keseriusan tindak lanjut atas komitmen adalah dengan melihat apakah proyek yang sudah direncanakan berjalan sesuai rencana, atau justru terhenti di tengah jalan karena penangguhan atau pembatalan. Dalam portofolio pembiayaan Tiongkok, skenario seperti ini memang bisa terjadi. Di Filipina, misalnya, salah satu tetangga ASEAN Indonesia, terdapat sedikitnya enam proyek yang masing-masing mengalami penangguhan atau pembatalan (Custer et al., 2024). Jika hal ini terjadi, biasanya mengindikasikan menurunnya minat dari pihak Beijing atau adanya keraguan dari mitra lokal untuk melanjutkan proyek sesuai rencana.
Di Indonesia, angka proyek yang berkurang ternyata jauh lebih rendah. Antara tahun 2000 hingga 2022, hanya ada satu kasus yang diketahui mengalami penangguhan. Pada 2008, China Eximbank memberikan pinjaman konsesi senilai 1,8 miliar yuan (sekitar 240 juta dolar AS) untuk membantu maskapai milik negara, Merpati Nusantara Airlines, membeli 15 pesawat MA60 dari Xi’an Aircraft Industrial Corporation, Tiongkok (Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022). Proyek ini, bernama National Air Bridge Project , diharapkan dapat memperkuat konektivitas udara regional. Syarat pendanaannya cukup menguntungkan: bunga 2,5 persen, jangka waktu 14,5 tahun, dan masa tenggang lima tahun.
Namun, setelah hanya dua pesawat dikirim, proyek ini berhenti di tengah jalan, padahal 86 persen dari pinjaman sudah dicairkan. Penyebabnya datang dari dua arah: masalah pada sisi pemasok dan hambatan di sisi permintaan. China Eximbank menghentikan pencairan dana setelah Merpati gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kontrak. Sebagai bentuk tekanan, China Eximbank, China Development Bank, dan Bank of China juga menunda pencairan dana untuk proyek-proyek lain yang mereka biayai di Indonesia. Situasi ini memicu kunjungan diplomatik tingkat tinggi ke Beijing. Meski pemerintah sempat mencoba melakukan intervensi, krisis keuangan yang kian memburuk di tubuh Merpati membuat proyek ini akhirnya ditinggalkan. Keterbatasan prospek komersial, lemahnya manajemen internal, dan tekanan dari para kreditor pada akhirnya membuat pemerintah menghentikan rencana menghidupkan kembali maskapai tersebut pada 2015.
Jika dibandingkan dengan Filipina, di mana pembatalan proyek kerap terjadi karena masalah tata kelola, sengketa hukum, atau kerusuhan politik, maka portofolio Beijing di Indonesia terlihat lebih stabil dan relatif minim gejolak politik (Custer et al., 2024). Meski begitu, seorang pakar yang diwawancarai mengingatkan bahwa kondisi ini belum tentu berarti positif. Ia berpendapat bahwa proyek-proyek yang dibiayai Tiongkok sering kali dianggap terlalu besar untuk gagal . Seperti yang ia katakan, “Sulit bagi pemerintah untuk menolak proyek-proyek Tiongkok, karena proyek-proyek tersebut terlalu besar untuk dilepas atau dihentikan.” Situasi ini akan semakin kuat jika proyek tersebut masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), yang secara otomatis menempatkannya sebagai prioritas pembangunan infrastruktur berskala besar.
4.2 Bagaimana proyek-proyek investasi RRT dijalankan dan dirasakan oleh komunitas penerima di Indonesia?
Proyek-proyek pembiayaan pembangunan dari Beijing memang telah memberi sumbangan besar bagi Indonesia, mulai dari memperluas basis industri hingga meningkatkan kualitas infrastruktur. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada sejumlah kasus di mana proyek-proyek tersebut tertunda, batal direalisasikan, atau justru menimbulkan kekhawatiran di mata publik.
Di bagian ini, kami membedah lebih jauh risiko-risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola ( Environmental, Social, and Governance /ESG) yang melekat pada proyek-proyek yang dibiayai Tiongkok di Indonesia. Risiko-risiko ini, jika benar-benar terjadi, berpotensi memberi dampak besar terhadap komunitas penerima manfaat (bagian 4.2.1). Selain itu, kami juga menilai risiko yang muncul dari kecenderungan Beijing untuk lebih banyak mengontrak perusahaan-perusahaan asal Tiongkok sebagai pelaksana proyek, dengan melihatnya melalui berbagai indikator kinerja (bagian 4.2.2).
4.2.1 Indikator dini risiko ESG dalam proyek pembiayaan RRT
Investasi besar-besaran di bidang infrastruktur dan industri strategis, baik yang digagas oleh pemerintah daerah, perusahaan swasta, maupun mitra pembangunan seperti Tiongkok, dapat membawa perubahan besar pada suatu komunitas. Proyek semacam ini memang memiliki potensi transformatif, tetapi juga mengandung risiko besar, terutama terkait hasil Environmental, Social, and Governance (ESG). Untuk meminimalkan risiko tersebut, sejumlah aktor pembangunan besar seperti Bank Dunia menetapkan standar pengamanan ESG yang ketat, yang berlaku sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
Tiongkok sendiri kerap mendapat kritik karena dianggap lebih menekankan kecepatan dan efisiensi biaya ketimbang memastikan kinerja ESG yang kuat dalam pembiayaan pembangunan luar negerinya (Parks et al., 2023). Meski begitu, membedakan mana yang benar-benar fakta dan mana yang sekadar persepsi tidaklah mudah. Untuk menjembatani kesenjangan ini, Parks et al. (2023) memperkenalkan metodologi terstruktur untuk mengukur sejauh mana lembaga keuangan milik negara Tiongkok menerapkan protokol manajemen risiko ESG dalam proyek-proyek yang mereka biayai.
Kerangka kerja tersebut menggunakan 27 kriteria untuk menilai apakah suatu proyek memiliki: (i) aturan dan standar ESG yang jelas; (ii) mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan; dan (iii) ketentuan penegakan untuk menangani pelanggaran. Kriteria ini mencakup delapan pengamanan lingkungan, tujuh pengamanan sosial, dan dua belas pengamanan tata kelola. Secara keseluruhan, kerangka ini memberikan pandangan menyeluruh untuk mengevaluasi risiko ESG pada tahun 2021, tahun terakhir di mana data tersedia (lihat Lampiran Teknis untuk detail lebih lanjut).
Hasilnya, lebih dari separuh portofolio pembiayaan pembangunan global Tiongkok (berdasarkan nilai dolar) terkait dengan setidaknya satu jenis risiko ESG (Parks et al., 2023). Untuk Indonesia, angkanya sedikit lebih rendah dari rata-rata global, yakni 26 persen proyek mengandung setidaknya satu bentuk risiko ESG (Gambar 4.4). Paparan Indonesia terhadap risiko lingkungan dan sosial sedikit di bawah rata-rata global, sementara paparan terhadap risiko tata kelola tercatat jauh lebih rendah.
Gambar 4.4: Persentase portofolio pembiayaan pembangunan RRT yang menghadapi risiko ESG di Indonesia dibandingkan rata-rata global, 2000–2021
Catatan: Gambar ini membandingkan tingkat rata-rata risiko ESG untuk
seluruh penerima lainnya dalam dataset GCDF 3.0 milik AidData secara
global dengan Indonesia. Data ini hanya tersedia hingga tahun 2021.
Sumber:
Metodologi diadaptasi dari Parks et al. (2023), sebagaimana diterapkan
dalam AidData’s Global Chinese Development Finance Dataset,
Version 3.0 (Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022).
Ada beberapa alasan yang mungkin menjelaskan perbedaan tingkat risiko ini. Pertama, pemerintah Indonesia mungkin memiliki mekanisme yang relatif lebih kuat dibandingkan mitra-mitra globalnya dalam memantau dan mengelola risiko tata kelola pada proyek-proyek yang didanai dari luar negeri. Kedua, portofolio investasi Tiongkok di Indonesia mungkin lebih banyak mengarah ke sektor-sektor yang kurang rentan terhadap masalah tata kelola—misalnya proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN—dibandingkan kemitraan publik-swasta yang umumnya memiliki tantangan pengawasan lebih kompleks. Faktor lainnya, pemberi pinjaman asal Tiongkok secara bertahap memperkuat praktik ESG mereka dari waktu ke waktu (Parks et al., 2023), sehingga usia proyek-proyek Tiongkok yang relatif lebih baru di Indonesia bisa ikut berkontribusi pada profil risiko yang lebih rendah.
Namun, catatan risiko yang lebih rendah tidak selalu berarti bahwa risiko aktualnya memang kecil. Perbedaan kualitas pelaporan atau tingkat deteksi risiko juga bisa berpengaruh. Beberapa pengamat bahkan berpendapat bahwa proyek-proyek yang dibiayai Tiongkok kerap melewati proses uji tuntas lingkungan secara menyeluruh. Salah satu narasumber membandingkannya dengan investor asing lain, dan menilai bahwa Tiongkok cenderung tetap melanjutkan proyek meski tanpa penilaian lingkungan, berbeda dengan Jepang yang secara rutin menerapkan persyaratan tersebut.
Pertanyaannya, sejauh mana Beijing belajar dari pengalaman masa lalu dan meningkatkan pengamanan ESG di Indonesia? Data menunjukkan bahwa kemajuannya masih belum merata. Dalam sebagian besar tahun, jumlah proyek Tiongkok yang dikategorikan berisiko ESG relatif kecil. Tetapi ada pengecualian besar pada 2016 dan 2017, ketika sejumlah proyek skala besar memicu peringatan serius terkait risiko lingkungan, sosial, dan dalam beberapa kasus, tata kelola (lihat Tabel 4.5). Risiko ESG ini pun tidak merata di seluruh portofolio, melainkan terkonsentrasi di sektor energi dan transportasi (lihat Tabel 4.6). Hal ini memberi sinyal bahwa kepatuhan terhadap standar ESG mungkin berbeda-beda, tergantung sektor atau pelaksana proyeknya.
Proyek energi menjadi penyumbang utama catatan risiko, dengan pelanggaran yang terulang dalam enam tahun berbeda. Pelanggaran ini mencakup isu lingkungan, seperti polusi udara dan banjir, hingga risiko sosial seperti kecelakaan kerja dan penggusuran. Contohnya, warga Batam menuntut penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Kasam yang dibiayai oleh China Eximbank, setelah fasilitas tersebut melepaskan abu dalam jumlah besar yang memicu penyakit pernapasan dan iritasi kulit (Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022). Kasus lain adalah proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi Sorik Marapi, di mana pada 2021 terjadi ledakan tekanan tinggi gas hidrogen sulfida yang menewaskan lima orang dan melukai 24 lainnya (ibid). Tragedi ini menjadi pengingat keras akan pentingnya manajemen risiko dan kesiapan tanggap darurat.
Tabel 4.5: Proyek pembangunan yang didanai RRT di Indonesia dengan risiko ESG yang baru teridentifikasi, 2000–2021
Tahun |
Minimal risiko 1 ESG |
Lingkungan |
Sosial |
Tata kelola |
Jumlah komponen ESG |
|---|---|---|---|---|---|
2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2008 |
5 |
1 |
1 |
4 |
6 |
2009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012 |
2 |
1 |
2 |
0 |
3 |
2013 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2016 |
3 |
2 |
3 |
0 |
5 |
2017 |
7 |
7 |
7 |
0 |
14 |
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019 |
1 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2020 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Catatan: Metodologi diadaptasi dari Parks et al. (2023), sebagaimana diterapkan dalam AidData’s Global Chinese Development Finance Dataset, Version 3.0 (Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022) untuk seluruh proyek di Indonesia. Data ini hanya tersedia hingga tahun 2021.
Sektor transportasi juga menyumbang sejumlah proyek yang masuk kategori berisiko tinggi. Salah satunya adalah proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung senilai 5,29 miliar dolar AS yang dibiayai bersama oleh China Development Bank (Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022). Proyek ini menuai kritik tajam karena dinilai memiliki penilaian lingkungan yang cacat, adanya korban jiwa di kalangan pekerja, serta gangguan yang dirasakan masyarakat sekitar (ibid). Selain itu, proyek ini juga dikaitkan dengan terjadinya banjir besar, terganggunya sistem drainase, dan kerusakan pada rumah-rumah warga di sekitarnya (ibid).
Sektor lainnya, seperti industri, pertambangan, dan konstruksi, memang mencatat jumlah risiko yang lebih sedikit. Meski demikian, kekhawatiran terkait ESG tetap muncul, khususnya menyangkut kondisi tenaga kerja dan protes dari komunitas yang terdampak langsung oleh proyek. Untuk risiko tata kelola, catatan kasus relatif jarang dan hanya sekali teridentifikasi, yaitu pada proyek energi tahun 2008 yang melibatkan dugaan penggelapan dana dalam proses pembebasan lahan. Rendahnya frekuensi kasus semacam ini bisa jadi bukan berarti masalahnya tidak ada, melainkan karena penyimpangan prosedural lebih sulit terdeteksi atau jarang terdokumentasikan.
Tabel 4.6: Risiko ESG dalam proyek yang didanai RRT di Indonesia menurut sektor, 2000–2021
Tahun janji |
Sektor |
Risiko ESG |
2008 |
Energi |
E, S, G |
2012 |
Transportasi |
E, S |
2012 |
Energi |
S |
2013 |
Energi |
S |
2016 |
Energi |
E, S |
2016 |
Industri, pertambangan, konstruksi |
S |
2017 |
Energi |
E, S |
2017 |
Transportasi |
E, S |
2019 |
Industri, pertambangan, konstruksi |
E, S |
2020 |
Energi |
E |
Catatan: Tabel ini menunjukkan risiko ESG yang terdeteksi berdasarkan
tahun dan kemudian berdasarkan sektor di Indonesia. Tahun-tahun yang
tidak tercantum dalam tabel tidak memiliki proyek dalam sampel kami
yang menunjukkan risiko ESG pada tahun tersebut. Data ini hanya
tersedia hingga tahun 2021.
Sumber: Metodologi diadaptasi dari
Parks et al. (2023), sebagaimana diterapkan dalam AidData’s
Global Chinese Development Finance Dataset, Version 3.0 (Custer et
al., 2023; Dreher et al., 2022) untuk seluruh proyek di Indonesia.
4.2.2 Paparan terhadap Risiko Kinerja dalam Proyek yang Dibiayai Tiongkok
Kemampuan pelaksana proyek asal Tiongkok dalam menuntaskan pembangunan yang dibiayai oleh RRT di Indonesia, tepat waktu sekaligus bertanggung jawab, ternyata sangat bervariasi. Karena itu, memilih pelaksana bukanlah perkara sepele. Keputusan ini dapat menentukan keberhasilan sebuah proyek sekaligus memengaruhi kesejahteraan masyarakat yang terdampak, terutama dalam hal pembangunan dan pemanfaatan lahan.
Dalam bagian ini, kami membandingkan kinerja perusahaan-perusahaan Tiongkok berdasarkan tiga dimensi risiko utama: (i) ketepatan waktu pelaksanaan dari awal hingga selesai; (ii) tingkat paparan terhadap risiko ESG; dan (iii) rekam jejak pelanggaran keuangan, yang tercermin dari sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga keuangan pembangunan multilateral terkemuka.
Hasilnya, ada pelaksana yang “hanya” mengalami keterlambatan sedang, namun ada pula yang kinerjanya jauh lebih buruk. Misalnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan yang mengelola proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, tercatat mengalami keterlambatan rata-rata 1.295 hari, atau lebih dari tiga setengah tahun dari jadwal awal. Beberapa perusahaan Tiongkok lainnya, seperti Dongfang Electric Corporation (DEC), Suzhou Thvow Technology Co., Ltd., China Harbour Engineering Company (CHEC), dan China Road and Bridge Corporation (CRBC), juga menghadapi keterlambatan hingga ratusan hari (lihat Tabel 4.7 di bawah). Pola ini menunjukkan adanya tantangan berulang yang dialami oleh berbagai pelaksana, baik yang berstatus BUMN Tiongkok maupun perusahaan patungan.
Selain itu, tercatat 13 pelaksana utama proyek yang didanai RRT di Indonesia pernah dikenai sanksi (baik secara langsung maupun melalui perusahaan induk) oleh Bank Dunia atau Asian Development Bank karena praktik curang atau korupsi. Beberapa lainnya juga ditandai dalam Parks et al. (2023) sebagai pelaksana dengan risiko ESG tinggi, termasuk lemahnya perlindungan lingkungan dan dampak sosial negatif terhadap komunitas lokal. Mengingat besarnya skala dan peran pembiayaan pembangunan RRT di Indonesia, catatan kinerja seperti ini jelas tidak bisa dianggap remeh.
Tabel 4.7: Risiko kinerja dan pelaksana proyek pembangunan asal Tiongkok di Indonesia, 2000–2023
Lembaga pelaksana |
Jenis Lembaga pelaksana |
Rata-rata keterlambatan, jumlah hari |
Sanksi/larangan ADB atau WB (ya/tidak) |
Masalah ESG yang disebut Parks et al. (2023) |
AECOM |
Sektor swasta lain |
No |
E |
|
AF Dealer Consulting |
Sektor swasta lain |
No |
E |
|
Black and Veatch |
Sektor swasta lain |
No |
E |
|
|
Chengdu Engineering Corp., Ltd. (CEC) [aff. PowerChina] |
BUMN |
Yes |
None |
|
|
China Construction Eighth Engineering Division Corp., Ltd. (CCEED) [aff. CSCEC] |
BUMN |
Yes |
None |
|
|
China Construction Fourth Engineering Division Corporation Ltd. [aff. CSCEC] |
BUMN |
Yes |
None |
|
|
China Gezhouba Group Cement Co., Ltd. [aff. CEEC, Energy China] |
BUMN |
Yes |
S |
|
|
China Gezhouba Group Company Ltd. (CGGC) [aff. CEEC, Energy China] |
BUMN |
Yes |
None |
|
|
China Harbour Engineering Co., Ltd. (CHEC) [aff. CCCC] |
BUMN |
-527 |
Ya |
None |
|
China Huadian Engineering Co., Ltd. |
BUMN RRT |
Tidak |
S |
|
|
China National Electric Engineering Co., Ltd. (CNEEC) |
BUMN RRT |
Tidak |
G |
|
|
China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation |
BUMN RRT |
Tidak |
G |
|
|
China Railway International Group Co Ltd (CRIG) |
BUMN |
Ya |
None |
|
|
China Road and Bridge Corporation (CRBC) |
BUMN |
-527 |
Ya |
None |
|
China State Construction Engineering Corp Ltd. (CSCEC) |
BUMN |
Ya |
None |
|
CSCEC Road and Bridge Group |
BUMN |
Ya |
None |
|
|
Dongfang Electric Corporation (DEC) |
BUMN RRT |
-384.5 |
Tidak |
G |
|
Doosan Heavy Industries and Construction |
Sektor swasta lain |
Tidak |
E |
|
|
Energy China [China Energy Equipment Corp. Ltd. (CEEC)] |
BUMN |
Ya |
None |
|
|
Environmental Resources Management (ERM) |
Sektor swasta lain |
Tidak |
E |
|
|
Guangdong Power Engineering Corp (GDSBD) [aff. CEEC] |
BUMN |
Ya |
E,S |
|
|
Harbin Boiler Company Ltd. (HBC) |
BUMN RRT |
Tidak |
E,S |
|
|
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
Lembaga pemerintah penerima |
-247 |
Tidak |
S |
JGC Corporation |
Sektor swasta lain |
Tidak |
S |
|
JO CHEC-CSCEC-HK |
Usaha patungan/lembaga tujuan khusus |
Ya |
None |
|
|
Korea Electric Power Corporation (KEPCO) |
BUMN lain |
Tidak |
E |
|
|
Perusahaan Listrik Negara (PLN) |
BUMN penerima |
Tidak |
S |
|
|
Power Construction Corporation of China (PowerChina) |
BUMN |
Ya |
E,S |
|
Pöyry PLC |
Sektor swasta lain |
Tidak |
E |
|
PT Connusa Energindo |
Sektor swasta penerima |
Tidak |
E |
|
PT Hutama Karya |
Sektor swasta lain |
Tidak |
E |
|
|
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) |
Usaha patungan/lembaga tujuan khusus lain |
-1295 |
Tidak |
E,S |
PT Lintas Marga Sedaya |
Usaha patungan/lembaga tujuan khusus lain |
Tidak |
E,S |
|
PT Penta Adi Samudera |
BUMN penerima |
Tidak |
G |
|
PT Pertafenikki Engineering |
Sektor swasta penerima |
Tidak |
S |
|
PT Pertafenikki Engineering |
Sektor swasta penerima |
Tidak |
S |
|
PT Praba Indopersada |
Sektor swasta penerima |
Tidak |
S |
|
PT Saipem Indonesia |
Sektor swasta penerima |
Tidak |
S |
|
PT Saipem Indonesia |
Sektor swasta penerima |
Tidak |
S |
|
|
PT. Priamanaya Djan International |
Sektor swasta penerima |
-785 |
Tidak |
G |
|
Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute Corp., Ltd. (SDEPCI) |
Sektor swasta RRT |
-263 |
Tidak |
E,S |
|
Suzhou Thvow Technology. Co., Ltd. |
Sektor swasta RRT |
-730 |
Tidak |
E,S |
|
Tokyo Electric Power Services Co., Ltd. (TEPSCO) |
Sektor swasta lain |
Tidak |
E |
|
Tronoh |
Sektor swasta lain |
-785 |
Tidak |
G |
|
Zelan Holdings (M) Sdn Bhd (Zelan) |
Sektor swasta lain |
-785 |
Tidak |
G |
|
Zhejiang Kaishan Compressor Co., Ltd (Kaishan) |
Sektor swasta lain |
Tidak |
E,S |
|
|
Zhongtian Guoneng Power Engineering |
BUMN RRT |
-730 |
Tidak |
E,S |
Catatan: Daftar lembaga pelaksana ini terbatas hanya pada entitas yang
ditandai sebagai terkena sanksi (secara langsung atau tidak langsung
melalui perusahaan induknya) atau menunjukkan tingkat paparan risiko
ESG yang lebih tinggi dalam proyek mereka. Rata-rata keterlambatan
dihitung berdasarkan jumlah hari penyimpangan dari jadwal pelaksanaan
atau penyelesaian yang direncanakan.
Sumber: Informasi sanksi
diperoleh dari registri daftar hitam perusahaan di Bank Dunia dan
Asian Development Bank, serta penelitian tambahan untuk
mengidentifikasi kasus sanksi lain yang tercantum dalam siaran pers
lembaga tersebut dan dilaporkan dalam artikel pihak ketiga. Metodologi
risiko ESG diadaptasi dari Parks et al. (2023) sebagaimana diterapkan
dalam AidData’s Global Chinese Development Finance Dataset,
Version 3.0 (Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022).
Hal ini memunculkan pertanyaan penting: seberapa besar sebenarnya porsi portofolio pembiayaan pembangunan Beijing di Indonesia yang melibatkan pelaksana dengan rekam jejak berisiko—baik karena paparan risiko ESG maupun sanksi atas praktik keuangan? Jawabannya, nilainya mencapai miliaran dolar. Berdasarkan perhitungan kami, sekitar 43 persen atau setara 30 miliar dolar AS dari total komitmen Beijing kepada Indonesia pada periode 2000–2023 disalurkan melalui perusahaan yang pernah terlibat dalam kasus ESG atau memiliki riwayat sanksi (lihat Tabel 4.8 di bawah).
Beberapa contoh yang paling menonjol antara lain pendanaan sebesar 4,9 miliar dolar AS untuk China Energy Equipment Engineering, Ltd. (CEEC) dan afiliasinya; 1,9 miliar dolar AS untuk China Road and Bridge Corporation (CRBC); serta 2,4 miliar dolar AS untuk Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute Corp. (SDEPCI).
Perusahaan-perusahaan ini bukan hanya menerima dana dalam jumlah besar, tetapi juga mendapatkan proyek secara berulang. Beberapa di antaranya, seperti China Harbour Engineering, China Road and Bridge Corporation, dan PowerChina, pernah dikenai sanksi atas praktik bisnis yang dipertanyakan dan/atau ditandai memiliki risiko ESG. Secara keseluruhan, kelompok perusahaan ini memegang porsi signifikan dari total portofolio proyek Tiongkok di Indonesia.
Tabel 4.8: Sepuluh pelaksana berisiko tinggi asal RRT berdasarkan jumlah dan nilai proyek, 2000–2023
Lembaga pelaksana |
Jumlah proyek |
Nilai proyek, miliar dolar AS |
|
Perusahaan Listrik Negara (PLN) |
12 |
5,25 |
|
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
10 |
1,59 |
|
China Road and Bridge Corporation (CRBC) |
6 |
1,9 |
|
Power Construction Corporation of China (PowerChina) |
5 |
1,38 |
|
China Harbour Engineering Co., Ltd. (CHEC) [aff. CCCC] |
4 |
0,75 |
JGC Corporation |
4 |
3,45 |
|
Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute Corp., Ltd. (SDEPCI) |
4 |
2,41 |
|
Dongfang Electric Corporation (DEC) |
4 |
1,57 |
|
Energy China [China Energy Equipment Corp. Ltd. (CEEC)] |
3 |
4,9 |
|
Guangdong Power Engineering Corp (GDSBD) [aff. CEEC] |
3 |
0,67 |
Catatan: Perusahaan-perusahaan ini memiliki rekam jejak paparan risiko ESG atau sanksi sebelumnya. Informasi sanksi diperoleh dari registri perusahaan yang dilarang oleh Bank Dunia dan Asian Development Bank, serta ditambah dengan penelitian meja untuk mengidentifikasi kasus sanksi tambahan yang dicatat dalam siaran pers lembaga-lembaga tersebut dan dilaporkan dalam artikel pihak ketiga. Metodologi risiko ESG diadaptasi dari Parks et al. (2023) sebagaimana diterapkan dalam AidData’s Global Chinese Development Finance Dataset, Version 3.0 (Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022).
Ketergantungan yang terus berlanjut pada perusahaan-perusahaan dengan risiko tinggi ini menunjukkan bahwa Beijing tidak selalu menjadikan kinerja masa lalu, baik yang diukur melalui keterlambatan, isu ESG, maupun riwayat sanksi, sebagai faktor yang mendiskualifikasi. Dalam banyak kasus, prioritas strategis, efisiensi biaya, atau hubungan politik tampaknya lebih diutamakan ketimbang pertimbangan risiko ketika Tiongkok mengambil keputusan kontraktual luar negeri. Tabel 4.8 di bawah ini menampilkan sepuluh pelaksana proyek Tiongkok teratas, baik dari sisi jumlah proyek maupun total nilai pembiayaan.
Risiko ini juga dipengaruhi oleh lembaga keuangan yang menyalurkan dana pembangunan Beijing (lihat Tabel 4.9). Beberapa bank, seperti Industrial and Commercial Bank of China dan China Development Bank, memang hanya memiliki sebagian kecil proyek yang ditandai dengan kekhawatiran ESG (sekitar 6–12 persen), namun proyek-proyek tersebut justru menyumbang porsi besar dari total pembiayaan mereka (32–45 persen). Sebaliknya, lembaga seperti China Construction Bank dan Agricultural Bank of China menunjukkan tingkat paparan yang tinggi, baik dari jumlah proyek maupun nilainya, lebih dari 80 persen portofolio mereka terkait dengan proyek-proyek berisiko.
Power Construction Corporation of China (PowerChina) bahkan tercatat sebagai salah satu lembaga pembiayaan utama sekaligus pelaksana proyek yang pernah dikenai sanksi, menegaskan adanya batas yang kabur antara peran sebagai penyandang dana dan kontraktor dalam sebagian proyek yang didukung Tiongkok.
Secara keseluruhan, pola ini mengindikasikan bahwa risiko ESG bukanlah masalah yang terbatas pada segelintir pelaksana “bermasalah” saja, melainkan mencerminkan ekosistem pembiayaan yang lebih luas, di mana proyek-proyek berisiko tinggi tetap mendapatkan dukungan dari bank-bank milik negara Tiongkok.
Tabel 4.9: Pendana utama asal Tiongkok untuk proyek pembangunan Indonesia dan risiko kinerja, 2000–2022
Tabel dapat diurutkan dengan mengeklik kolom. Pada layar kecil, gulir secara horizontal untuk melihat kolom tersembunyi.
BUMN |
Jumlah proyek |
Nilai total, miliar dolar AS |
Persen proyek yang dikaitkan dengan risiko |
Persen nilai total yang dikaitkan dengan risiko |
|---|---|---|---|---|
China Development Bank (CDB) |
57 |
30,74 |
12% |
32% |
PowerChina |
2 |
17,41 |
0% |
|
|
Export-Import Bank of China (China Eximbank) |
55 |
16,59 |
9% |
20% |
|
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) |
102 |
16,36 |
6% |
45% |
Bank of China (BOC) |
63 |
11,01 |
8% |
12% |
|
China Construction Bank Corporation (CCB) |
13 |
6,05 |
31% |
80% |
|
Agricultural Bank of China (ABC) |
3 |
4,36 |
67% |
86% |
|
China Investment Corporation (CIC) |
2 |
3,19 |
0% |
|
|
Shandong Xinhai Technology Co. Ltd. (Xinhai) |
1 |
2,98 |
0% |
|
|
Taiyuan Iron and Steel Co. Ltd. (Tisco) |
1 |
2,98 |
0% |
|
ICBC Indonesia |
20 |
2,6 |
5% |
43% |
|
China CITIC Bank Corporation Limited |
4 |
2,45 |
50% |
72% |
|
ICBC Financial Leasing Co., Ltd. (ICBC Leasing) |
2 |
2,14 |
0% |
|
|
Unspecified Chinese Government Institution |
80 |
1,79 |
0% |
|
|
State Development and Investment Corporation Power (SDIC Power) |
1 |
1,72 |
0% |
|
|
Bank of China (Cabang Jakarta) |
8 |
1,55 |
13% |
72% |
|
Bank of China (Cabang Singapura) |
1 |
1,26 |
100% |
89% |
|
China Merchants Bank Co., Ltd. |
1 |
1,26 |
100% |
89% |
Tai Fung Bank Limited |
1 |
1,26 |
100% |
89% |
|
China Energy Engineering Corp (CEEC) |
1 |
1,21 |
0% |
|
|
China International Development Cooperation Agency (CIDCA) |
2 |
0,66 |
0% |
|
|
Bank of China (Hong Kong) Limited (BOCHK) |
6 |
0,57 |
0% |
|
|
Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited (ICBC (Asia)) |
2 |
0,26 |
0% |
|
ZTE Corporation |
2 |
0,17 |
0% |
Catatan: Tabel ini merangkum perusahaan milik negara Tiongkok (SOE)
dengan jejak keuangan terbesar di Indonesia, berdasarkan jumlah proyek
dan total nilai komitmen. Tabel ini hanya mencakup SOE yang memiliki
sedikitnya dua proyek atau nilai komitmen total lebih dari 100 juta
dolar AS. Bayangan warna (shading) menunjukkan masing-masing kolom.
Risiko yang dimaksud mencakup risiko lingkungan, sosial, atau tata
kelola (ESG), dan sel kosong menunjukkan bahwa tidak ada proyek dari
SOE tersebut yang diasosiasikan dengan risiko ESG.
Sumber:
Klasifikasi risiko didasarkan pada metodologi penilaian risiko ESG
dari AidData, yang diadaptasi dari Parks et al. (2023) dan diterapkan
pada AidData’s Global Chinese Development Finance Dataset,
Version 3.0 (Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022).
4.3 Bagaimana pembiayaan Tiongkok memengaruhi persepsi dan hasil pembangunan di Indonesia?
Beijing membiayai proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang punya potensi mengubah wajah perekonomian, lingkungan, tata kelola, dan kehidupan masyarakat Indonesia, dengan dampak yang bisa bersifat positif maupun negatif. Namun, pengaruh Tiongkok tidak berhenti pada hasil langsung dari masing-masing proyek. Pola keterlibatan yang lebih luas juga dapat membentuk cara publik dan elite politik Indonesia memandang Tiongkok, baik sebagai kekuatan global maupun sebagai mitra pembangunan.
Dalam bagian ini, pembahasan diarahkan melampaui lingkup proyek, lembaga pembiayaan, atau kontraktor tertentu, untuk menilai bagaimana keseluruhan portofolio investasi Beijing memengaruhi persepsi di Indonesia (bagian 4.3.1) dan bagaimana hal tersebut berpotensi menentukan arah pembangunan nasional di masa depan (bagian 4.3.2).
4.3.1 Memenangkan hati dan pikiran? Persepsi dan pembiayaan
Bab-bab sebelumnya dalam laporan ini menyoroti bagaimana Beijing menerapkan model dua jalur dalam pembiayaan pembangunannya di Indonesia. Di satu sisi, ia menggunakan pembiayaan berbasis utang untuk mendukung prioritas infrastruktur besar yang dicanangkan para pemimpin Indonesia. Di sisi lain, ia menyalurkan bantuan tradisional yang menyasar komunitas lokal, demi membangun citra positif. Strategi ini dijalankan secara sengaja: pembiayaan pembangunan dari negara diarahkan untuk menarik investasi langsung asing (FDI) dari sektor swasta Tiongkok, membuka pasar baru, dan memperluas pengaruhnya. Diplomasi ekonomi Tiongkok memiliki banyak tujuan, termasuk memengaruhi opini publik dan memproyeksikan soft power (Mathew dan Custer, 2023).
Keterlibatan Tiongkok di Indonesia juga berubah seiring waktu, mengikuti dinamika strategi di bawah berbagai pemerintahan Indonesia (lihat bagian 2.2 pada Bab 2). Meski kepemimpinan nasional sangat menentukan dalam mengarahkan kepentingan Beijing, opini publik juga berperan besar, terutama di negara demokrasi elektoral seperti Indonesia, di mana pilihan rakyat dapat memengaruhi arah kebijakan pemerintah dan hubungan dengan kekuatan asing (Freedom House, 2024).
Secara teori, jika uang bisa membeli simpati, kita mungkin berharap ada lonjakan besar dalam pandangan positif publik Indonesia terhadap Tiongkok selama dua dekade terakhir, seiring meningkatnya keterlibatan ekonomi Beijing. Namun, data Gallup World Poll (2006–2024) justru menunjukkan tren yang berbeda (Gambar 4.10). Tingkat persetujuan terhadap kepemimpinan RRT sempat mencapai puncak pada 2008, lalu menurun, meski periode setelah 2008 adalah saat Indonesia justru menerima pembiayaan pembangunan dan FDI Tiongkok dalam skala yang jauh lebih besar.
Menariknya, pandangan publik ini tidak mengikuti pola pesimisme terhadap para pemimpin dalam negeri. Tingkat persetujuan terhadap pemimpin Indonesia melonjak hingga hampir 90 persen menjelang pemilihan kembali Presiden Yudhoyono pada 2009, lalu tetap relatif tinggi—di kisaran 65–80 persen—selama masa transisi kepemimpinan ke Widodo dan Subianto. Angka-angka ini bisa jadi mencerminkan kepuasan publik terhadap konsolidasi demokrasi (Yudhoyono adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat) atau kebijakan spesifik yang mereka jalankan. Ada kemungkinan, publik lebih mengaitkan manfaat pembangunan infrastruktur dengan politisi domestik dibandingkan dengan investasi dari Tiongkok.
Beijing bukan satu-satunya pihak yang menghadapi penurunan simpati publik. Sikap warga Indonesia terhadap Jepang dan Amerika Serikat juga menurun antara 2006 dan 2024. Jepang, yang kerap tampil sebagai mitra pembangunan “bintang” di mata publik, hanya meraih persetujuan dari sepertiga responden Indonesia. Namun, tingkat penerimaannya tetap konsisten lebih tinggi daripada negara lain selama 18 tahun terakhir, mungkin karena Jepang dikenal sebagai mitra pembangunan lama yang dermawan, tidak menimbulkan kontroversi, dan sudah lama hadir di Indonesia. Menariknya, popularitas Jepang tidak merosot, meski posisinya sebagai penyedia pembiayaan pembangunan terbesar untuk Indonesia telah digeser oleh RRT.
Persaingan memperebutkan simpati publik terlihat lebih ketat antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Pada 2008, 45 persen warga Indonesia menyetujui kepemimpinan AS, namun angka ini turun menjadi hanya 24 persen pada 2024. Citra AS di mata publik Indonesia juga cenderung lebih fluktuatif dibandingkan Tiongkok, ada masa ketika opini publik condong ke Washington, dan di periode lain, justru RRT yang unggul.
Gambar 4.10: Persepsi warga Indonesia terhadap kepemimpinan Tiongkok,
AS, Jepang, dan pemerintah Indonesia sendiri, 2006–2024
Catatan: Gambar ini menunjukkan persentase responden dari Indonesia yang
menyatakan menyetujui kinerja kepemimpinan Tiongkok, Jepang, dan Amerika
Serikat, serta pemerintahan mereka sendiri (responden dapat memilih
menyetujui, tidak menyetujui, atau tidak tahu). Garis putus-putus
vertikal menunjukkan tahun pemilihan presiden di Indonesia.
Sumber:
Gallup World Poll (2006–2024). Seluruh angka menggunakan bobot
yang disediakan Gallup untuk memastikan sampel yang representatif.
Untuk memahami tren ini lebih dalam, kami menjalankan model statistik untuk menguji apakah paparan terhadap pembiayaan pembangunan dari Tiongkok ( development finance /DF) maupun investasi langsung asing ( foreign direct investment /FDI) dari negara tersebut memengaruhi pandangan publik Indonesia terhadap kepemimpinan politik mereka sendiri maupun kepemimpinan Beijing. Ada empat variabel utama yang kami uji: (i) nilai dolar DF dari RRT (termasuk bantuan dan instrumen utang), (ii) jumlah proyek DF yang didanai Beijing, (iii) nilai FDI yang masuk dari Tiongkok ke Indonesia, dan (iv) jumlah proyek FDI dari Tiongkok ke Indonesia.
Kami melihat dua hasil yang menjadi fokus: (i) tingkat persetujuan masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinan RRT, dan (ii) tingkat persetujuan mereka terhadap pemerintah Indonesia. Model ini memeriksa apakah kedua dimensi opini publik tersebut bergerak seiring dengan keempat ukuran finansial tadi pada tingkat subnasional. [111] Kami juga mempertimbangkan faktor-faktor individu, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan, lokasi pedesaan atau perkotaan, dan pendapatan rumah tangga. [112] Perlu dicatat, model ini hanya mengidentifikasi ada atau tidaknya hubungan, tetapi tidak menjelaskan penyebabnya. Rincian teknis mengenai konstruksi model tersedia di Lampiran Teknis.
Jika Beijing berharap diplomasi ekonominya akan berujung pada peningkatan citra di mata publik Indonesia, hasil ini bisa dibilang mengecewakan. Tidak satu pun pengujian menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik antara tingkat paparan provinsi terhadap DF atau FDI Tiongkok dan persetujuan terhadap kepemimpinan RRT, baik positif maupun negatif. [113] Namun, ada satu temuan yang menarik: paparan terhadap proyek DF dan FDI Beijing secara konsisten berkorelasi (di semua spesifikasi model) dengan penurunan tingkat persetujuan terhadap pemerintah Indonesia di Jakarta. [114] Meski begitu, temuan ini tetap harus ditafsirkan hati-hati karena tidak signifikan secara statistik.
Singkatnya, Beijing menghadapi tantangan besar untuk mengubah sumber daya finansial besar, baik lewat DF maupun FDI, menjadi keuntungan reputasi yang jelas di mata publik Indonesia. Ada setidaknya tiga kemungkinan penjelasan.
Pertama, masyarakat Indonesia mungkin lebih terpapar pada sisi lain kebijakan Beijing yang sifatnya negatif, seperti reaksi terhadap klaim maritim di Laut Natuna atau isu perlakuan terhadap minoritas Muslim Uighur di Xinjiang, yang dapat mengikis manfaat citra dari bantuan finansial.
Kedua, meningkatnya kekhawatiran tentang ketergantungan Indonesia pada investasi Tiongkok di sektor-sektor strategis bisa menetralkan apresiasi terhadap dukungan tersebut. Survei Asian Barometer bahkan mencatat, proporsi warga Indonesia yang menganggap Tiongkok punya “pengaruh baik” menurun 28 poin persentase antara 2011 dan 2021. [115]
Ketiga, belum jelas sejauh mana sikap terhadap kelompok Tionghoa-Indonesia ikut memengaruhi persepsi terhadap Tiongkok daratan, terlepas dari strategi Beijing. Dua dekade lebih setelah kerusuhan Mei 1998, yang secara tidak proporsional menargetkan etnis Tionghoa—sentimen sinofobia dan ketegangan antar-etnis masih ada, termasuk kerusuhan sporadis dan kecurigaan terhadap loyalitas warga Tionghoa-Indonesia kepada Beijing (Sritharan dan Rizkillah, 2024; Herlijanto, 2017).
Sikap publik memang penting, namun persepsi para elite politik, swasta, dan masyarakat sipil juga tidak kalah menentukan dalam mendukung kepentingan RRT. AidData melakukan survei di lebih dari 100 negara, termasuk Indonesia, untuk memantau persepsi elite terhadap Tiongkok sebagai mitra pembangunan (Custer et al., 2025). Meski data untuk elite Indonesia belum cukup untuk dianalisis secara kuantitatif tersendiri, survei ini tetap memberi gambaran regional yang bisa dipadukan dengan temuan kualitatif dari responden Indonesia. [116]
Hasilnya, hampir 85 persen pemimpin di Asia Timur dan Pasifik yang bekerja sama dengan RRT menilai negara tersebut cukup atau sangat berpengaruh dalam membentuk prioritas domestik di negara mereka—angka yang konsisten antara survei 2020 dan 2024. Hal ini kontras dengan survei serupa pada 2014 dan 2017 yang menunjukkan pengaruh lebih rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing memang berupaya memprofesionalisasi kapasitas pelaksanaan pembangunannya (Mathew dan Custer, 2023), yang mungkin menjelaskan lonjakan besar (+40 poin persentase) dalam persepsi kegunaan dari 47 persen pada 2020 menjadi 86,7 persen pada 2024.
Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan, elite Indonesia justru melihat Beijing sebagai aktor yang lebih berpengaruh dalam membentuk agenda pembangunan nasional. Namun, jumlah mereka yang menilai pengaruh ini sebagai hal positif merosot hingga setengahnya antara 2020 dan 2024 (Gambar 4.11). Persepsi terhadap kegunaan Beijing pun ikut menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Gambar 4.11: Persepsi terhadap RRT sebagai mitra pembangunan oleh pemimpin di Indonesia, 2020 dan 2024
Catatan: Visual ini menunjukkan persentase pemimpin sektor publik,
swasta, dan masyarakat sipil di Indonesia yang disurvei pada tahun
2020 dan 2024 yang: (i) mengidentifikasi RRT sebagai cukup atau sangat
berpengaruh dalam membentuk prioritas kebijakan domestik di negara
mereka (pengaruh dalam penetapan agenda); (ii) menyatakan bahwa
pengaruh RRT cukup atau sangat positif bagi negara mereka (pengaruh
yang dipandang positif); dan (iii) menilai RRT cukup atau sangat
membantu dalam perancangan dan pelaksanaan reformasi kebijakan
(kebermanfaatan dalam pelaksanaan) selama lima tahun sebelum
masing-masing survei dilakukan. Para pemimpin hanya dapat mengevaluasi
kinerja RRT dalam hal kebermanfaatan dan kepositifan jika mereka
sebelumnya melaporkan telah menerima saran atau bantuan dari RRT dalam
lima tahun terakhir.
Sumber: Listening to Leaders Survey,
Gelombang ke-3 dan ke-4. Custer et al., 2021; Custer et al., 2025.
4.3.2 Manfaat publik atau kerugian publik? Dampak pembiayaan Tiongkok
Selama dua dekade terakhir, pembiayaan pembangunan yang diarahkan oleh negara dari Beijing dan investasi langsung asing (FDI) Tiongkok dari sektor swasta telah mengalir deras ke sektor-sektor strategis Indonesia, mulai dari energi dan industri ekstraktif hingga transportasi dan telekomunikasi, dalam skala yang jarang ditandingi oleh aktor eksternal lain. Baik pendukung maupun pengkritiknya sama-sama menunjuk pada proyek-proyek tertentu sebagai sumber manfaat besar atau, sebaliknya, sumber masalah bagi masyarakat, institusi, dan lingkungan fisik Indonesia. Meski demikian, pengaruh yang lebih luas dari keterlibatan ekonomi Tiongkok terhadap arah pembangunan Indonesia masih belum sepenuhnya terpetakan.
Di bagian ini, kami memanfaatkan serangkaian model statistik [117] untuk menilai apakah, dan sejauh mana, portofolio pembiayaan pembangunan ( development finance /DF) dan investasi FDI dari RRT berkaitan dengan berbagai hasil penting di bidang ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia.
4.3.2.1 Pembiayaan RRT dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia
Tiongkok adalah kekuatan ekonomi yang sulit dibantah. Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menaruh harapan besar pada kemampuan RRT dalam menyediakan pembiayaan pembangunan dan mendorong investasi langsung asing (FDI) dari sektor swastanya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata (Custer et al., 2024). Beijing sendiri tidak segan memperkuat narasi tersebut melalui berbagai saluran, termasuk media penyiaran milik negara (Burgess et al., 2024). Meski begitu, pertanyaan besarnya tetap sama: apakah modal Tiongkok benar-benar mampu memenuhi ekspektasi tersebut?
Untuk menjawabnya, kami meneliti hubungan antara pembiayaan Tiongkok, baik dilihat dari nilai dolar maupun jumlah proyek DF dan FDI, dengan empat indikator ekonomi utama: produktivitas domestik dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB), pertumbuhan ekonomi masyarakat (PDRB per kapita), indikator sosial-ekonomi dasar (tingkat pengangguran dan persentase kemiskinan), serta persepsi publik Indonesia terhadap prospek ekonomi mereka (ketahanan pangan, kepercayaan pada perekonomian, dan iklim ketenagakerjaan).
Hasilnya, FDI sektor swasta dari Tiongkok tampak memiliki keterkaitan paling kuat dengan pertumbuhan jangka pendek. Baik jumlah maupun nilai proyek FDI Tiongkok menunjukkan korelasi positif dan signifikan terhadap peningkatan PDRB (lihat Tabel 4.12). Artinya, provinsi yang menerima lebih banyak FDI Tiongkok cenderung mengalami lonjakan produktivitas ekonomi dibandingkan provinsi yang menerima lebih sedikit investasi serupa. Sementara itu, pembiayaan pembangunan yang diarahkan oleh negara dari RRT juga menunjukkan hubungan positif dengan PDRB, meskipun korelasinya tidak signifikan secara statistik.
Dampak jangka panjang modal Tiongkok terhadap tingkat pengangguran, kemiskinan, ketahanan pangan, dan sentimen ekonomi masyarakat menunjukkan pola yang beragam. Pembiayaan pembangunan dari Beijing, misalnya, berkorelasi dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah, hubungan ini konsisten dan dalam beberapa tahun terakhir bahkan signifikan secara statistik. Temuan ini menantang anggapan umum bahwa Beijing lebih mengandalkan tenaga kerja dan pemasok dari negaranya sendiri ketimbang lokal, dan justru sejalan dengan pengamatan pada Bab 3 bahwa pelaksana proyek dari Indonesia berperan cukup besar dalam pembiayaan pembangunan Beijing.
Dalam beberapa model, pembiayaan pembangunan dari Tiongkok juga terlihat memberikan kontribusi positif terhadap persepsi masyarakat terkait kondisi ekonomi lokal, seperti keamanan kerja, iklim ekonomi, dan ketahanan pangan, namun hasil ini cenderung tidak stabil dan tidak signifikan secara statistik.
Sementara itu, pengaruh FDI Tiongkok terhadap tingkat pengangguran memperlihatkan dinamika yang lebih kompleks. Pada awalnya, proyek-proyek FDI berkorelasi positif dengan penurunan pengangguran dan kemiskinan pada tahun pertama. Namun, keuntungan ini berbalik arah dalam beberapa tahun berikutnya, bahkan menjadi signifikan secara statistik. Hal serupa terlihat pada persepsi publik: provinsi yang awalnya mendapat FDI Tiongkok dalam jumlah besar melaporkan kepercayaan ekonomi lokal yang lebih tinggi, tetapi sentimen itu menurun tajam pada tahun kelima. Persepsi terhadap ketahanan pangan juga meningkat setahun setelah komitmen proyek FDI baru, namun efek ini menghilang seiring berjalannya waktu.
Tabel 4.12: Pembiayaan pembangunan dan FDI Tiongkok serta hasil ekonomi di Indonesia, 2001–2023
Pada layar kecil, gulir secara horizontal untuk melihat kolom tersembunyi.
|
|
Agregat ekonomi yang diamati secara umum |
Pengalaman ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia |
||||||
|
Masukan |
Jeda |
Produk domestik regional bruto (PDRB) |
PDRB per kapita |
Tingkat pengangguran |
Tingkat kemiskinan |
Ketahanan pangan |
Kondisi ekonomi lokal |
Iklim pekerjaan lokal |
|
Jumlah DF |
5 thn |
(+) |
(+) |
(-) |
(+) |
(+) |
(+) |
(+) |
|
Proyek DF |
5 thn |
(+) |
(+) |
(-) |
(+) |
(+) |
(+) |
(+) |
|
Jumlah FDI |
5 thn |
(+) |
(+) |
(+) |
(+) |
(+) |
(-) |
(-) |
|
Proyek FDI |
5 thn |
(+) |
(+) |
(+) |
(+) |
(+) |
(-) |
(-) |
Catatan: Model ini menggunakan data provinsi-tahun. Selain empat jenis
pembiayaan Tiongkok sebagai variabel input (variabel independen),
model ini juga mencakup variabel kontrol demografis dan efek tetap
untuk tahun dan provinsi. Tanda +/- menunjukkan arah hubungan. Sel
berwarna hijau menunjukkan bahwa hubungan antara jenis pembiayaan
Tiongkok dan hasil yang diamati signifikan pada tingkat konvensional
(p < 0,001, < 0,01, atau < 0,05). Karena adanya variasi dalam
ketersediaan data, jumlah observasi, provinsi yang disertakan, dan
tahun yang dicakup berbeda antar model. Spesifikasi tambahan
dijalankan dengan jeda waktu 1 dan 3 tahun. Lihat Lampiran Teknis
untuk detail lebih lanjut.
Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik,
2025); Gallup World Poll (Gallup, 2025).
4.3.2.2 Pembiayaan RRT dan dampaknya terhadap lingkungan Indonesia
Terlepas dari janji keuntungan ekonomi, banyak warga Indonesia tetap mengaitkan investasi Tiongkok dengan kerusakan lingkungan yang nyata. Dalam survei tahun 2024, lebih dari 40 persen responden menyatakan bahwa proyek pembangunan yang dibiayai Tiongkok merusak lingkungan dan ekosistem setempat (Rakhmat et al., 2024). Pandangan serupa juga diungkapkan oleh sejumlah pakar Indonesia yang kami wawancarai. Salah satu narasumber bahkan menegaskan bahwa pendapatan dari proyek-proyek tersebut dinikmati pemerintah pusat, sementara masyarakat lokal justru menanggung beban kerusakan lingkungan, tanpa memperoleh manfaat yang berarti, termasuk lapangan pekerjaan. [118]
Lalu, apakah jejak ekonomi Tiongkok benar-benar meninggalkan dampak lingkungan yang bisa diukur? Untuk mencari jawabannya, kami menggunakan teknik statistik yang sama seperti pada bagian sebelumnya, guna menilai apakah dan sejauh mana modal Tiongkok, baik jumlah maupun nilai proyek DF dan FDI, berkaitan dengan empat indikator lingkungan. Dua indikator pertama berbasis citra satelit, yaitu kehilangan vegetasi dan emisi karbon dioksida di seluruh provinsi Indonesia. Dua indikator berikutnya berbasis survei, yakni tingkat ketidakpuasan publik terhadap kualitas udara dan air.
Salah satu temuan paling jelas dari data adalah adanya hubungan antara masuknya investasi langsung Tiongkok dan kehilangan vegetasi yang terdeteksi (diukur dengan Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI) dalam satu tahun setelah komitmen proyek baru. Secara logis, temuan ini dapat dipahami mengingat dominasi FDI Tiongkok pada proyek-proyek infrastruktur fisik dan digital (lihat Bab 2), yang sering melibatkan pembukaan lahan hutan atau menghasilkan polusi yang mengancam cadangan vegetasi. Meski begitu, hubungan negatif ini tidak bertahan lama, signifikansi statistiknya hilang, bahkan arahnya berbalik, pada tahun-tahun berikutnya.
Di sisi lain, provinsi-provinsi yang lebih banyak menerima FDI Tiongkok memang menunjukkan tren peningkatan emisi karbon dioksida dari waktu ke waktu, tetapi hubungan ini tidak signifikan secara statistik pada tingkat konvensional.
Menariknya, meskipun survei publik di awal bagian ini menunjukkan kekhawatiran luas terhadap potensi dampak lingkungan negatif dari proyek Tiongkok, sentimen itu tidak selalu sejalan dengan keluhan spesifik terkait kualitas udara dan air di wilayah masing-masing (lihat Tabel 4.13).
Tabel 4.13: Pembiayaan pembangunan dan FDI Tiongkok serta hasil sosial dan tata kelola di Indonesia, 2001–2023
Pada layar kecil, gulir secara horizontal untuk melihat kolom tersembunyi.
|
|
Indikator lingkungan yang diamati secara umum |
Persepsi perubahan lingkungan menurut masyarakat Indonesia |
|||
|
Masukan |
Jeda |
NDVI |
Karbon dioksida |
Ketidakpuasan terhadap kualitas air |
Ketidakpuasan terhadap kualitas udara |
|
Jumlah DF
|
5 thn |
(+) |
(-) |
(-) |
(+) |
|
Proyek DF |
5 thn |
(+) |
(+) |
(-) |
(-) |
|
Jumlah FDI |
5 thn |
(+) |
(+) |
(+) |
(+) |
|
Proyek FDI |
5 thn |
(+) |
(+) |
(+) |
(+) |
Catatan: Model ini menggunakan data per provinsi per tahun. Selain empat jenis pembiayaan dari Tiongkok sebagai variabel input (variabel independen), model ini juga mencakup variabel kontrol demografis serta efek tetap untuk tahun dan provinsi. Tanda +/- menunjukkan arah hubungan. Sel biru menunjukkan hubungan yang lemah namun signifikan secara statistik antara jenis pembiayaan RRT dan indikator hasil yang dimaksud (p < 0,1). Karena variasi dalam ketersediaan data, jumlah observasi, provinsi yang disertakan, dan tahun yang dicakup berbeda-beda dalam setiap model. Spesifikasi tambahan dijalankan dengan jeda waktu 1 dan 3 tahun. Lihat Lampiran Teknis untuk informasi lebih lanjut. Sumber: NASA untuk Normalized Difference Vegetation Index (Pedelty et al., 2007) dan karbon dioksida (Tim Ilmiah OCO-2/OCO-3 et al., 2022), Gallup World Poll (Gallup, 2025).
Mengingat kecenderungan Beijing untuk menggabungkan pembiayaan pembangunan negara dengan investasi dari sektor swasta (lihat Bab 2), wajar jika muncul asumsi bahwa kedua jenis pembiayaan ini akan menghasilkan dampak lingkungan yang serupa di tingkat provinsi. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Menariknya, pembiayaan pembangunan dari Beijing, baik dari sisi nilai maupun jumlah proyek, justru cenderung berkorelasi dengan tingkat ketidakpuasan yang lebih rendah terhadap kualitas air dan udara lokal setelah lima tahun. Sebaliknya, jumlah dan proyek FDI menunjukkan korelasi yang berlawanan, yakni tingkat ketidakpuasan yang lebih tinggi pada kedua indikator tersebut. Pada tahun pertama dan ketiga, proyek FDI bahkan menunjukkan nilai negatif, sebelum berubah menjadi positif di tahun kelima. Meski begitu, tidak ada hasil yang signifikan secara statistik, sehingga temuan ini tetap perlu ditafsirkan secara hati-hati.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam bab ini, tidak semua proyek pembangunan yang dibiayai Tiongkok membawa tingkat risiko yang sama. Variasi ini bisa menutupi fakta bahwa sebagian aktivitas memiliki dampak lingkungan yang besar di tingkat lokal. Salah satu contoh yang paling jelas adalah Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang telah dibahas di Bab 2. [119] Pembangunan kawasan ini dimulai pada 2013 dan rampung pada 2017, mengubah bentang pesisir yang sebelumnya didominasi hutan menjadi kompleks industri raksasa dengan fasilitas peleburan, pembangkit listrik, pelabuhan, dan infrastruktur pendukung lainnya, serta memicu dampak lingkungan yang besar (Nindita dan Feng, 2025a).
Berbagai studi independen menempatkan IMIP di posisi teratas sebagai salah satu proyek dengan tingkat kehilangan vegetasi paling parah di antara inisiatif yang didukung Tiongkok (Pramono et al., 2022; Brown dan Harris, 2024). [120] Citra satelit mengonfirmasi percepatan deforestasi di wilayah ini, dengan penurunan tajam pada tutupan hijau (Gambar 4.14). Selain itu, IMIP dilaporkan berkontribusi terhadap erosi, sedimentasi, serta berkurangnya stok ikan lokal. Warga setempat mengeluhkan polusi udara, masalah kesehatan, dan berkurangnya akses terhadap hutan maupun tanah leluhur mereka (Nindita dan Feng, 2025a). Perbedaan antara laporan lokal ini dan temuan statistik kami kemungkinan mencerminkan kenyataan bahwa dampak lingkungan yang sangat terlokalisasi, seperti pencemaran air dan udara, bisa saja luput dari pengamatan jika data dikumpulkan pada level provinsi.
Gambar 4.14: Tren vegetasi di Sulawesi Tengah, 2010–2020
Catatan: Gambar ini menampilkan rata-rata tahunan kehijauan dan
kepadatan vegetasi (Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI)
di Provinsi Sulawesi Tengah. Nilai NDVI diskalakan dengan faktor
10.000: nilai 6.400 setara dengan NDVI sebesar 0,64. Nilai yang lebih
tinggi menunjukkan vegetasi yang lebih lebat dan sehat. Garis
putus-putus vertikal menunjukkan waktu dimulainya dan berakhirnya
pembangunan Kawasan Industri Morowali.
Sumber: Long-Term Data
Record milik NASA berdasarkan Advanced Very High Resolution
Radiometer, sebuah sensor satelit yang memantau kondisi permukaan
lahan (Pedelty et al., 2007).
4.3.2.3 Pembiayaan RRT dan dampaknya terhadap aspek sosial dan tata kelola di Indonesia
Pendanaan dari Tiongkok memang menawarkan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, di sisi lain, ada risiko munculnya tantangan sosial dan tata kelola, terutama jika proyek dijalankan dengan proses yang tidak transparan dan minim akuntabilitas di tingkat lokal. Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang dibahas di Bab 2, menjadi contoh bagaimana kesepakatan infrastruktur semacam ini bisa berjalan dalam kerangka regulasi yang kabur, dengan pengawasan politik yang lemah (Nicola et al., 2023). [121] Kekhawatiran publik terhadap pengaruh RRT terhadap norma demokrasi dan sosial pun memperkuat dinamika ini (Rakhmat dan Purnama, 2024; Sampurna, 2018).
Untuk melihat lebih jauh apakah dan bagaimana modal dari Tiongkok, baik dari sisi jumlah maupun nilai proyek pembiayaan pembangunan (DF) dan investasi langsung asing (FDI), berkaitan dengan hasil sosial dan tata kelola, kami membangun model statistik dengan spesifikasi yang sama seperti di bagian-bagian sebelumnya. Empat indikator yang digunakan mewakili penilaian para pakar di bidang pembangunan sosial dan tata kelola: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Pembangunan Manusia Subnasional (SHDI), Indeks Korupsi Subnasional (SCI), dan akses layanan kesehatan per provinsi. Selain itu, kami juga menggunakan empat indikator persepsi warga terkait demokrasi, partisipasi sipil, pembangunan pemuda, dan korupsi, yang bersumber dari survei Gallup World Poll dan Asian Barometer, serta data objektif dari Global Data Lab dan Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS).
Hasilnya menunjukkan gambaran yang beragam. Paparan terhadap pembiayaan pembangunan dari RRT cenderung berkorelasi dengan persepsi publik yang lebih positif terhadap partisipasi sipil, tetapi di sisi lain dihubungkan dengan penilaian yang lebih negatif terhadap pembangunan pemuda. Sementara itu, prospek dari FDI justru terlihat lebih suram: investasi jenis ini secara signifikan terkait dengan penurunan partisipasi sipil dalam jangka pendek. Tidak ada hubungan signifikan secara statistik antara kedua bentuk pendanaan ini dan akses terhadap layanan kesehatan, meskipun Beijing gencar mempromosikan inisiatif Health Silk Road dan berperan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.
Dalam hal tata kelola, kedua bentuk pembiayaan ini juga menunjukkan hasil yang berbeda. Pembiayaan pembangunan dari Beijing secara konsisten berkorelasi dengan persepsi publik yang lebih positif terhadap kondisi demokrasi di Indonesia (Tabel 4.15). Hal ini mungkin terjadi karena pembiayaan DF sering diselaraskan dengan prioritas politik domestik, sehingga dapat dimanfaatkan politisi untuk membangun citra bahwa mereka menepati janji kampanye. Sebaliknya, paparan terhadap FDI dari Tiongkok justru berkorelasi dengan penurunan tajam tingkat demokrasi subnasional dalam jangka pendek, meskipun efek ini melemah dari waktu ke waktu dan kehilangan signifikansi statistik. Selain itu, FDI Tiongkok juga menunjukkan hubungan yang konsisten, dan secara normatif positif, dengan meningkatnya persepsi terhadap korupsi, meskipun temuan ini juga tidak signifikan secara statistik.
Tabel 4.15: Pembiayaan pembangunan dan FDI Tiongkok serta hasil sosial dan tata kelola di Indonesia, 2001–2023
Pada layar kecil, gulir secara horizontal untuk melihat kolom tersembunyi.
|
|
Ukuran yang dinilai oleh para ahli |
Ukuran persepsi warga negara |
|||||||
|
Masukan |
Jeda |
IDI |
SHDI |
Korupsi |
Kesehatan |
Demokrasi |
Keterlibatan masyarakat |
Pengembangan Generasi Muda |
Persepsi korupsi |
|
Jumlah DF |
5 thn |
(-) |
(-) |
(-) |
(-) |
(+) |
(+) |
(-) |
(+) |
|
Proyek DF |
5 thn |
(-) |
(-) |
(-) |
(-) |
(+) |
(+) |
(-) |
(-) |
|
Jumlah FDI |
5 thn |
(-) |
(-) |
(-) |
(-) |
(-) |
(-) |
(-) |
(+) |
|
Proyek FDI |
5 thn |
(-) |
(-) |
(+) |
(+) |
(-) |
(-) |
(+) |
(+) |
Catatan: Model ini menggunakan data per provinsi per tahun. Selain
empat jenis pembiayaan Tiongkok sebagai variabel input (variabel
independen), model ini juga mencakup variabel kontrol demografis serta
efek tetap untuk tahun dan provinsi. Data survei tentang apakah
Indonesia merupakan negara demokrasi (“Democracy”) dari
Asian Barometer tersedia pada tingkat nasional, karena survei ini
tidak secara konsisten mengidentifikasi responden berdasarkan wilayah
subnasional. Tanda +/- menunjukkan arah hubungan. Sel berwarna hijau
menunjukkan bahwa hubungan antara jenis pembiayaan RRT dan indikator
hasil yang diamati signifikan pada tingkat konvensional (p < 0.001,
< 0.01, atau < 0.05). Sel berwarna biru menunjukkan hubungan
yang lebih lemah (p < 0.1). Karena adanya variasi dalam
ketersediaan data, jumlah observasi, provinsi yang termasuk, dan tahun
yang dicakup berbeda-beda antar model. Spesifikasi tambahan juga
dijalankan dengan jeda waktu 1 dan 3 tahun. Lihat Lampiran Teknis
untuk detail lebih lanjut.
Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik,
2025); Global Data Lab (Crombach dan Smits, 2024; Global Data Lab.,
2024; Smits dan Permanyer, 2019); Gallup World Poll (Gallup, 2025),
Survei Asian Barometer (2024).
Indonesia menghadirkan sebuah paradoks yang cukup mencolok. Sejak pertengahan 2010-an, semakin banyak warga yang meyakini bahwa negaranya adalah demokrasi dan merasa puas dengan kualitas institusinya (Gambar 4.16). Namun, ukuran objektif yang disusun para ahli justru menunjukkan tren sebaliknya, sebuah pergeseran dari demokrasi menuju otokrasi (Nord et al., 2025). Meski Indonesia masih menyelenggarakan pemilu multipartai, Laporan Demokrasi 2025 dari V-Dem Institute menyoroti kekhawatiran serius terhadap perlindungan kebebasan sipil, termasuk kebebasan berekspresi dan berserikat, serta kualitas pelaksanaan pemilu yang benar-benar bebas dan adil (ibid).
Apa yang menjelaskan kesenjangan antara persepsi publik dan penilaian objektif ini? Bisa jadi, warga Indonesia tengah mengubah cara pandang mereka tentang makna demokrasi dan manfaat yang seharusnya diberikan sistem tersebut. Survei Asian Barometer, misalnya, mencatat bahwa sejak pertengahan 2000-an, sekitar 80 persen responden di Indonesia cenderung memprioritaskan pembangunan ekonomi dibandingkan demokrasi (Gambar 4.17). Menariknya, kecenderungan ini justru menguat dalam beberapa tahun terakhir.
Banyak faktor mungkin mendorong preferensi ini, termasuk keinginan akan pertumbuhan ekonomi yang stabil ketimbang mempertahankan institusi demokrasi liberal. Sulit untuk memastikan apakah, dan sejauh mana, hubungan ekonomi yang semakin intensif dengan Beijing ikut memengaruhi perubahan norma ini. Namun, terlihat jelas bahwa fokus RRT pada pembangunan ekonomi, bukan demokrasi, sejalan dengan preferensi publik yang dominan di Indonesia sekaligus arah politik negara ini. Pola yang muncul juga menunjukkan bahwa seiring melemahnya demokrasi di Indonesia, hubungan dengan Tiongkok semakin erat, sementara publik makin memprioritaskan pertumbuhan ekonomi di atas demokrasi.
Gambar 4.16: Sikap warga Indonesia terhadap demokrasi dan penilaian atas demokrasi nasional, 2002–2023
Catatan: Garis putus-putus merah mencerminkan persentase warga
Indonesia yang menyatakan preferensi kuat atau moderat terhadap
pembangunan ekonomi dibandingkan demokrasi ketika ditanya, “Jika
Anda harus memilih antara demokrasi dan pembangunan ekonomi, mana yang
lebih penting bagi Anda?” Semua jawaban lainnya dikodekan
sebagai nol. Garis putus-putus hijau menunjukkan Liberal Democracy
Index dari Varieties of Democracy, yang mengukur sejauh mana hak
individu, kebebasan sipil, dan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan
eksekutif dijunjung tinggi dalam sebuah demokrasi elektoral. Liberal
Democracy Index yang awalnya diskalakan dari 0 hingga 1, dikalikan
dengan 100 agar sesuai dengan skala persentase 0–100 dari hasil
survei, sehingga perbandingan menjadi lebih mudah. Dua garis
putus-putus vertikal menandai peluncuran Prakarsa Sabuk dan Jalan
(2013) dan awal pandemi COVID-19 (2020), yang disertakan untuk
menempatkan tren ini dalam konteks peristiwa global utama.
Sumber:
Varieties of Democracy (Coppedge et al., 2025; Pemstein et al., 2025);
Asian Barometer Survey (2024).
Gambar 4.17: Demokrasi atau pembangunan? Opini publik Indonesia dan peran Tiongkok yang berkembang, 2000–2023
Catatan: Grafik paling atas menampilkan pembiayaan pembangunan
Tiongkok tahunan ke Indonesia, berdasarkan Global Chinese Development
Finance Dataset versi 3.0 dari AidData. Grafik tengah menunjukkan
Liberal Democracy Index dari Varieties of Democracy, yang diskalakan
dari 0–1 lalu dikalikan 100. Grafik paling bawah menunjukkan
persentase warga Indonesia, berdasarkan survei Asian Barometer, yang
memprioritaskan pembangunan ekonomi dibandingkan nilai-nilai demokrasi
ketika diminta memilih di antara keduanya.
Sumber: Dreher et al.,
2022; Custer et al., 2023; Varieties of Democracy (Coppedge et al.,
2025; Pemstein et al., 2025); Asian Barometer Survey (2024).
5. Kesimpulan
Sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan politik utama di Asia Tenggara, Indonesia menjadi magnet investasi bagi Tiongkok. Dalam dua dekade terakhir, Beijing telah mengucurkan dana besar ke Indonesia: membiayai 400 proyek pembangunan senilai sekitar 69,6 miliar dolar AS melalui pembiayaan yang diarahkan negara (2000–2023) dan menyalurkan sekitar 94,1 miliar dolar AS dalam bentuk investasi asing langsung (FDI) dari sektor swasta (2010–2023). Angka ini menempatkan Indonesia jauh di atas negara-negara tetangganya di kawasan, baik dari sisi jumlah FDI maupun pembiayaan pembangunan yang diterima dari Tiongkok. Posisi ini memberi Beijing pengaruh ekonomi yang signifikan, sekaligus memperkuat daya tawarnya di ranah politik, sebagai salah satu sumber utama FDI dan pembiayaan pembangunan bagi Indonesia.
Skala investasi Tiongkok yang luar biasa ini tentu menjanjikan peluang besar bagi Indonesia. Para pemimpin politik dalam negeri dihadapkan pada tuntutan untuk mewujudkan janji kampanye mereka, terutama terkait pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pembangunan infrastruktur, dan Beijing telah membuktikan dirinya sebagai mitra yang siap membantu. Namun, seperti yang diuraikan dalam laporan ini, pola operasi Beijing cenderung menyerupai pemberi pinjaman komersial ketimbang donor tradisional. Antusiasme RRT dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur berskala besar, bahkan ketika melibatkan pelaksana dengan rekam jejak yang bermasalah, menunjukkan bahwa menjalin kemitraan dengan Tiongkok menuntut strategi manajemen risiko yang matang.
Laporan ini, Antara Risiko dan Imbal Hasil: Siapa yang Diuntungkan dari Investasi Tiongkok di Indonesia? , mencoba menjembatani kesenjangan informasi penting mengenai apa yang sebenarnya diinvestasikan Beijing, di mana lokasinya, dan apa dampaknya. Melalui analisis sistematis terhadap aliran dana, jaringan kemitraan, dan hasil dari dua dekade investasi Tiongkok di Indonesia, kami memisahkan mitos dari fakta. Di bagian penutup ini, kami merangkum temuan-temuan utama penelitian ini untuk membantu publik dan para pengambil kebijakan di Indonesia menimbang secara lebih jernih manfaat sekaligus risiko dari keterlibatan ekonomi dengan Tiongkok.
5.1 Prioritas yang terungkap: Proyek apa, kapan, dan di mana?
Tiongkok bukan sejak awal menjadi mitra pembangunan utama Indonesia atau sumber FDI terbesarnya. Pada awal 2000-an, Jepang masih memegang posisi sebagai donor terbesar sebelum akhirnya RRT melampaui mitra bilateral maupun multilateral lainnya pada periode 2011–2018. Pola pembiayaan ini bergerak dinamis, dengan lonjakan moderat di era Presiden Megawati, fluktuasi tajam di era Presiden Yudhoyono, hingga mencapai rekor tertinggi pada masa pertama pemerintahan Presiden Widodo. Setelah itu, pandemi COVID-19 memicu penurunan signifikan. Tren FDI Tiongkok pun mengikuti pola pasar modal global, turun pada 2015, melambat saat pandemi, lalu kembali meningkat pada 2023.
Beijing menerapkan strategi “dua jalur” yang memadukan investasi infrastruktur berskala besar dengan potensi keuntungan komersial, dan proyek-proyek kecil yang bertujuan membangun citra positif. Sektor energi, transportasi, serta kapasitas pengolahan nikel untuk industri baja nirkarat dan baterai kendaraan listrik (EV) menjadi fokus utama pembiayaan pembangunan dari Tiongkok. Di luar sektor ekonomi, pemerintah RRT juga menyalurkan bantuan berupa dana, pangan, tim pencarian dan penyelamatan, tenaga medis untuk respons bencana alam, serta mendukung proyek sosial, pendidikan, dan kesehatan.
RRT piawai memanfaatkan sumber daya negara untuk membangun infrastruktur strategis dan menjalin hubungan di tingkat lokal, yang kemudian membuka jalan bagi masuknya FDI swasta Tiongkok. Perusahaan-perusahaan Tiongkok bahkan menyumbang 98 persen investasi baru di sektor mineral dan setengah dari total modal untuk investasi logam. Bahkan ketika nilainya relatif kecil, mereka mampu memosisikan diri sebagai pemain dominan, termasuk di sektor-sektor khusus seperti produk kayu, keramik, dan kaca. Dari sisi wilayah, Pulau Jawa dan Sumatra menjadi tujuan utama pembiayaan pembangunan Beijing, sementara FDI sektor swasta bisa dilacak hingga ke tingkat provinsi. Jika dilihat dari pembiayaan pembangunan yang diarahkan negara, belanja per kapita RRT paling tinggi terlihat di provinsi-provinsi kaya sumber daya seperti Papua Barat dan Sulawesi Tengah.
5.2 Jaringan pengaruh: Siapa saja aktornya, apa perannya, dan mengapa?
Di tahun-tahun awal, pembiayaan pembangunan dari Beijing banyak bergantung pada lingkaran kecil bank kebijakan dan bank komersial milik negara yang seragam di Tiongkok. Dari 2008 hingga awal peluncuran Belt and Road Initiative, RRT bahkan menjadi kreditor negara terbesar bagi ekonomi berkembang. Namun, ketika beberapa negara peminjam mulai kesulitan membayar utang dan pelaksanaan proyek tersendat, Beijing menjadi lebih berhati-hati, sekaligus defensif, dalam menanggapi pemberitaan media tentang proyek yang dinilai kurang matang dan membebani negara penerima dengan utang.
Belakangan, Beijing mulai mengandalkan skema pinjaman sindikasi. Mekanisme ini memungkinkan bank kebijakan dan bank komersial milik negara berbagi risiko serta modal dengan jejaring pendana bersama yang lebih luas, termasuk bank-bank komersial Barat dan bahkan lembaga multilateral. Pola ini juga terlihat di Indonesia. Sebanyak 58 lembaga keuangan Tiongkok tercatat menjadi pemberi dana utama proyek infrastruktur besar, memanfaatkan jejaring 208 bank dari 34 negara untuk menekan risiko.
Meski sering dipersepsikan sebagai proyek “serba Tiongkok”, kenyataannya pembiayaan pembangunan Beijing di Indonesia melibatkan jaringan luas yang berisi 213 lembaga pemerintah, BUMN dan bank, perusahaan swasta, serta organisasi masyarakat sipil dari 12 negara. Memang, BUMN Tiongkok menjadi pelaksana terbesar, tetapi hampir setengah pelaksana justru berasal dari Indonesia, baik perusahaan independen maupun pihak yang tergabung dalam usaha patungan (joint ventures/JV) atau kendaraan tujuan khusus (special purpose vehicles/SPV). Di ranah sosial, proyek-proyek RRT juga memanfaatkan kredibilitas serta jaringan organisasi Islam dan universitas di Indonesia untuk membangun kedekatan dengan masyarakat.
Namun, ada satu kerentanan besar yang kami temukan: sekitar 40 persen portofolio proyek (senilai 30 miliar dolar AS) bergantung pada pelaksana berisiko tinggi. Sebanyak 15 pelaksana di Indonesia pernah atau sedang dikenai sanksi oleh Bank Dunia atau ADB akibat praktik keuangan yang meragukan, atau memiliki hubungan dengan perusahaan induk yang disanksi. Sebagian juga memiliki catatan risiko ESG tinggi. Perusahaan-perusahaan ini bukan hanya menerima pendanaan besar, tetapi juga kerap kembali dipercaya menggarap proyek. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan, Beijing mungkin lebih mengutamakan faktor strategis, efisiensi biaya, atau hubungan politik dibanding rekam jejak dan mitigasi risiko.
Dari sisi penerima, mayoritas (87 persen) adalah lembaga atau organisasi Indonesia. Walau proyek RRT tersebar di berbagai provinsi, sebagian besar penerima terkonsentrasi di DKI Jakarta. Beberapa penerima dengan volume pendanaan dan jumlah proyek tertinggi antara lain Pemerintah Indonesia (kementerian tidak disebutkan), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Garuda Indonesia. Menariknya, ada pula 13 organisasi dan kelompok Islam, termasuk masjid, LSM berbasis agama, dan institusi Pendidikan, yang menjadi penerima proyek RRT. Bentuknya beragam, mulai dari beasiswa untuk mahasiswa Muslim hingga undangan kunjungan ke Tiongkok bagi pemimpin keagamaan, yang sejalan dengan praktik diplomasi berbasis agama.
5.3 Menimbang untung-rugi: Realisasi, biaya, dan manfaat?
Banyak pemimpin negara-negara di Selatan Global sering memuji kecepatan Beijing dalam mengeksekusi proyek, menganggapnya sebagai daya tarik utama dibandingkan mitra alternatif. Namun, di lapangan, reputasi ini tidak selalu sesuai kenyataan. Di Indonesia, Beijing rata-rata membutuhkan 2,5 tahun untuk mengubah komitmen pendanaan menjadi proyek yang benar-benar terealisasi. Bahkan, di Bengkulu, Gorontalo, dan Jambi, waktu tunggunya bisa lebih dari lima tahun. Sebaliknya, Papua Tengah, Aceh, dan Yogyakarta menjadi pengecualian, karena proyek di sana dapat selesai kurang dari satu tahun sejak peletakan batu pertama.
Penting untuk memahami jenis proyek yang rentan menghadapi hambatan, apalagi jika ingin mengelola ekspektasi atau membandingkannya dengan mitra lain. Bantuan pangan atau tanggap darurat, misalnya, biasanya dapat disalurkan dengan cepat. Namun, proyek infrastruktur besar, seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi, sering memakan waktu lebih dari 1.000 hari dari tahap komitmen hingga penyelesaian. Wajar saja, mengingat kompleksitas yang melibatkan pembebasan lahan, penilaian dampak lingkungan, koordinasi antar kontraktor, dan kesiapan infrastruktur lokal.
Beijing juga kerap mensyaratkan penggunaan perusahaan Tiongkok, sambil menghindari proses pengadaan yang terbuka dan kompetitif. Karena itu, penting untuk melihat rekam jejak pelaksana. Variasinya cukup lebar: PT Kereta Cepat Indonesia China, yang mengerjakan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, tercatat mengalami keterlambatan rata-rata 1.295 hari atau lebih dari tiga setengah tahun. Perusahaan lain seperti Dongfang Electric Corporation, Suzhou Thvow Technology Co., Ltd., China Harbour Engineering Company, dan China Road and Bridge Corporation juga mencatat keterlambatan ratusan hari.
Kemauan Beijing membiayai infrastruktur raksasa jelas membuka peluang besar bagi Indonesia, tapi juga mengandung risiko. Investasi ini bisa mempercepat pencapaian target pembangunan, namun tak jarang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat lokal. Menggunakan model statistik, kami menilai hubungan antara modal Tiongkok, baik FDI dari sektor swasta maupun pembiayaan pembangunan oleh negara, dengan berbagai hasil ekonomi, sosial, tata kelola, dan lingkungan di tingkat provinsi. Hasilnya beragam.
Sesuai klaim Beijing bahwa dukungannya membantu pemimpin Indonesia membangun infrastruktur demi pertumbuhan, efek paling nyata memang terlihat di sektor ekonomi. Kedua jenis modal Tiongkok berkorelasi positif dengan produktivitas daerah. Pembiayaan pembangunan dari Beijing bahkan berkorelasi dengan penurunan tingkat pengangguran, yang berlawanan dengan kritik bahwa proyek Tiongkok hanya mengandalkan tenaga kerja dan pemasok dari negaranya sendiri. Sebaliknya, FDI Tiongkok cenderung kurang efektif dalam mengurangi pengangguran atau memperbaiki persepsi publik terhadap kondisi ekonomi.
Namun, bayangan kerusakan lingkungan masih kuat. Lebih dari 40 persen responden survei 2024 percaya proyek Tiongkok merusak lingkungan dan ekosistem lokal (Rakhmat et al., 2024). Memang, risiko ESG cenderung tinggi di sektor energi dan transportasi, meskipun secara agregat tidak ada korelasi yang jelas antara modal Tiongkok dan polusi atau hilangnya vegetasi. Ini mungkin karena dampak negatif yang signifikan sering kali muncul di lokasi proyek tertentu, seperti pada kasus Kereta Cepat Jakarta–Bandung dan Kawasan Industri Morowali yang memicu banjir atau polusi, pembangkit listrik batu bara Tanjung Kasam di Batam yang menimbulkan masalah kesehatan, dan proyek panas bumi Sorik Marapi yang menyebabkan cedera serta korban jiwa akibat lemahnya protokol keselamatan.
Tantangan terbesar Beijing adalah mengubah investasi menjadi keuntungan reputasi. Sejak 2008, dukungan publik di Indonesia terhadap pemimpin Tiongkok terus menurun, meski arus modal dari RRT justru melonjak. Salah satu alasannya, masyarakat cenderung mengatribusikan manfaat infrastruktur kepada politisi lokal. Survei warga dan elite juga mengindikasikan kekhawatiran bahwa pengaruh ekonomi RRT tidak selalu positif bagi Indonesia.
Meski begitu, Beijing masih punya peluang untuk memperluas pengaruh. Narasinya yang menempatkan pembangunan ekonomi di atas demokrasi sejalan dengan tren opini publik Indonesia dan arah politik negara ini. Meskipun skor demokrasi liberal Indonesia menurut para pakar menurun, survei masyarakat menunjukkan kepuasan yang meningkat terhadap kualitas demokrasi, bersamaan dengan kecenderungan publik untuk lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Ada kemungkinan, warga Indonesia kini tengah mendefinisikan ulang makna demokrasi dalam kerangka manfaat langsung bagi kesejahteraan mereka.
6. Daftar Pustaka
Adhiguna, Putra. (2024). 0.4% of global battery production capacity: Indonesia’s battery and EV developments are far out of step with its nickel exploitation promise. Analysis Outline. Energy Shift Institute. February 2024. https://energyshift.institute/wp-content/uploads/2024/02/Energy-Shift_Indonesia-nickel-and-battery_Feb2024.pdf
Alfian. (2009). PLN to secure $761m in loans from Chinese banks in June. May 26, 2009. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/news/2009/05/26/pln-secure-761m-loans-chinese-banks-june.html-0
Ali, M. and F. Wulandari. (2008). Blackout on Indonesia’s Java due to coal disruption. February 21, 2008. Reuters. https://www.reuters.com/article/markets/companies/blackout-on-indonesias-java-due-to-coal-disruption-idUSSP173185/
Anam, K. (2022). KRAS Gandeng BUMN China Operasikan Blast Furnace Complex. September 30, 2022. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/market/20220930125044-17-376263/kras-gandeng-bumn-china-operasikan-blast-furnace-complex
Antara. (March 2025). TCTP Batang Indonesia-China berpotensi ciptakan 10.000 lapangan kerja. https://jabar.antaranews.com/rilis-pers/4726533/tctp-batang-indonesia-china-berpotensi-ciptakan-10000-lapangan-kerja
Antara. (October 2013). APP dapat pinjaman 1,8 miliar dolar AS. October 3, 2013. https://www.antaranews.com/berita/398730/app-dapat-pinjaman-18-miliar-dolar-as
Antara. (June 2012). Japan seeks to increase geothermal cooperation with Indonesia. June 22, 2012. https://en.antaranews.com/news/83042/japan-seeks-to-increase-geothermal-cooperation-with-indonesia
Antara. (October 2006). Presiden Yudhoyono ke China 27-31 Oktober. October 18, 2006. https://www.antaranews.com/berita/44694/presiden-yudhoyono-ke-china-27-31-oktober
ASEAN Briefing. (2022). Indonesia to Ban Bauxite Export from June 2023: An Explainer. ASEAN Briefing Doing Business in Indonesia. Retrieved from: https://www.aseanbriefing.com/doing-business-guide/indonesia/sector-insights/indonesia-to-ban-bauxite-export-from-june-2023-an-explainer
Asian Barometer Survey. (2024). Asian Barometer Survey Waves 3, 4, 5, 6. Center for East Asia Democratic Studies, National Taiwan University. Retrieved from https://www.asianbarometer.org/data?page=d10 .
Asian Development Bank. (n.d.) Publicly Disclosed Debarment or Suspension. Retrieved from: https://sanctions.adb.org/sanctions/published
Asian Development Bank. (2023). Loan agreement (Ordinary Operations): [Supporting Essential Health Actions and Transformation Program] . https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/54224/54224-001-lna-en.pdf
Asia Maritime Transparency Initiative. (2024). Seismic Strife: China and Indonesia Clash Over Natuna Survey. October 28, 2024. https://amti.csis.org/seismic-strife-china-and-indonesia-clash-over-natuna-survey/
Brown, D. and J. Harris. (2024). From Forests to Electric Vehicles: Quantifying and Addressing the Environmental Toll of Indonesian Nickel. Mighty Earth. May 2024. https://mightyearth.org/wp-content/uploads/2024/05/FromForeststoEVs.pdf
Brummitt, C. and N. Chatterjee. (2015). Indonesia Scraps Bullet Train, Seeks Fresh China, Japan Bids. https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-03/indonesia-scraps-bullet-train-seeks-new-bids-from-china-japan
Burgess, B., Henares, T. J. G., Kim, E. Y., Mathew., D., Solis, J. A., and N. Sritharan. (2024). Investing in Narratives: How Beijing promotes its development projects in the Philippines. Williamsburg, VA: AidData at William & Mary. https://www.aiddata.org/publications/investing-in-narratives
Cabinet Secretariat of Indonesia. (2025, January 16). President Prabowo Subianto expresses optimism for 8% economic growth . https://setkab.go.id/en/president-prabowo-subianto-expresses-optimism-for-8-economic-growth
Cahyafitri, R. (2014, July 1). Tangguh LNG price raised after deal. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/news/2014/07/01/tangguh-lng-price-raised-after-deal.html
Cai, D. (2023, October 2). China Belt and Road: Indonesia opens Whoosh high-speed railway . BBC News. https://www.bbc.com/news/world-asia-66979810
China Power. (2017, August). How Much Trade Transits the South China Sea? Updated January 25, 2021. CSIS. Accessed May 14, 2025. https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/
Chinese Embassy. (2004). “China and Indonesia.” April 22, 2004. http://id.china-embassy.gov.cn/indo/zgyyn/sbgxgk/200404/t20040422_2347161.htm
Chinese Embassy. (2009). Bentang Utama Jembatan SURAMADU Tersambung. April 1, 2009. http://id.china-embassy.gov.cn/indo/sgdt/200904/t20090402_2039859.htm
Coppedge, M., Gerring, J., Knutsen, C. H., Lindberg, S. I., Teorell, J., Altman, D., Angiolillo, F., Bernhard, M., Cornell, A., Fish, M. S., Fox, L., Gastaldi, L., Gjerløw, H., Glynn, A., Good God, A., Grahn, S., Hicken, A., Kinzelbach, K., Krusell, J., Marquardt, K. L., McMann, K., Mechkova, V., Medzihorsky, J., Natsika, N., Neundorf, A., Paxton, P., Pemstein, D., von Römer, J., Seim, B., Sigman, R., Skaaning, S.-E., Staton, J., Sundström, A., Tannenberg, M., Tzelgov, E., Wang, Y.-t., Wiebrecht, F., Wig, T., Wilson, S., and Ziblatt, D. (2025). V-Dem [Country-Year/Country-Date] Dataset v15. Varieties of Democracy (V-Dem) Project. https://doi.org/10.23696/vdemds25.
Costa, F. and Forte, R. (2022, December). A Review of the Literature on International Joint Ventures: A Bibliometric Study for the Period 1975-2019. Studies in Business and Economics 17(3):35-56. DOI:10.2478/sbe-2022-0044 https://www.researchgate.net/publication/367502055_A_Review_of_the_Literature_on_International_Joint_Ventures_A_Bibliometric_Study_for_the_Period_1975-2019
Crombach, L., and Smits, J. (2024). The Subnational Corruption Database: Grand and petty corruption in 1,473 regions of 178 countries, 1995–2022 [Data set]. Figshare. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.7061534.v1 .
Custer, S., Horigoshi, A., Boer, B., and Marshall, K. (2025). Listening to leaders 2025: Development cooperation over a decade of disruption . Williamsburg, VA: AidData at William & Mary. https://www.aiddata.org/publications/listening-to-leaders-2025-development-cooperation-over-a-decade-of-disruption
Custer, S., Burgess, B., Solis, J. A., Sritharan, N. and D. Mathew. (2024). Beijing’s Big Bet on the Philippines: Decoding two decades of China’s financing for development . Williamsburg, VA: AidData at William & Mary. https://www.aiddata.org/publications/beijings-big-bet-on-the-philippines-decoding-two-decades-of-chinas-financing-for-development
Custer, S., Dreher, A., Elston, T.B., Escobar, B., Fedorochko, R., Fuchs, A., Ghose, S., Lin, J., Malik, A., Parks, B.C., Solomon, K., Strange, A., Tierney, M.J., Vlasto, L., Walsh, K., Wang, F., Zaleski, L., and Zhang, S. (2023). Tracking Chinese Development Finance: An Application of AidData’s TUFF 3.0 Methodology. Williamsburg, VA: AidData at William & Mary.
Custer, S., Sethi, T., Knight, R., Hutchinson, A., Choo, V., and Cheng, M. (2021). Listening to leaders 2021: A report card for development partners in an era of contested cooperation . Williamsburg, VA: AidData at William & Mary. https://www.aiddata.org/publications/listening-to-leaders-2021
Custer, S., Schon, J., Horigoshi, A., Mathew, D., Burgess, B., Choo, V., Hutchinson, A., Baehr, A., and K. Marshall (2021). Corridors of Power: How Beijing uses economic, social, and network ties to exert influence along the Silk Road . Williamsburg, VA: AidData at William & Mary. https://www.aiddata.org/publications/corridors-of-power
Darmawan, A.R. (2024). Has Indonesia fallen into China’s nine-dash line trap? November 12, 2024. The Interpreter. The Lowy Institute. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/has-indonesia-fallen-china-s-nine-dash-line-trap
Darmawan, A.R. (2020). Jakarta should be wary of Beijing’s South China Sea proposals. The Interpreter. The Lowy Institute. August 28, 2020. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/jakarta-should-be-wary-beijing-s-south-china-sea-proposals
Detik. (2006). RI-Cina Teken Kontrak Proyek Energi US$3,56 Miliar. DetikFinance. October 28, 2006. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-700393/ri-cina-teken-kontrak-proyek-energi-us-3-56-miliar
detikNews. (2008, May 27). PLN Dapat Pendanaan US$ 592 Juta dari Bank of China. Detikfinance. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-946063/pln-dapat-pendanaan-us-592-juta-dari-bank-of-china
detikNews. (2008, September 3). SB Setuju Pansus Undang Mega, Taufiq dan SBY. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-999796/sb-setuju-pansus-undang-mega-taufiq-dan-sby
Detik. (2009). Menkeu Bertolak ke China Nego Pembiayaan Program 10,000 MW. DetikFinance. March 18, 2009. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1101090/menkeu-bertolak-ke-china-nego-pembiayaan-program-10-000mw
Dreher, A., Fuchs, A., Parks, B., Strange, A., and Tierney, M. (2022). Banking on Beijing: The Aims and Impacts of China's Overseas Development Program . Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/978110856449 6
The Economist. (2014). Smeltdown. January 18, 2014. https://www.economist.com/business/2014/01/18/smeltdown
Escobar, B., Malik, A. A., Zhang, S., Walsh, K., Joosse, A., Parks, B. C., Zimmerman, J., and R. Fedorochko. (2025). Power Playbook: Beijing’s Bid to Secure Overseas Transition Minerals . Williamsburg, VA: AidData at William & Mary. https://www.aiddata.org/publications/power-playbook-beijings-bid-to-secure-overseas-transition-minerals
Esterman, I. (2017). Japanese, Singaporean banks finance controversial Indonesian coal plant . March 6, 2017. Mongabay. https://news.mongabay.com/2017/03/japanese-singaporean-banks-finance-controversial-indonesian-coal-plant/
Ewe, K. (2024, February 5). Trouble inventing paradise: Beijing-based development bank faces inflection point as concerns mount over ‘New Bali’ project. TIME. https://time.com/6590390/mandalika-indonesia-aiib-development-concerns/
Fauziyah, N.N. (2024). Whoosh High-Speed Train Ambition a 'Time Bomb' for Prabowo Subianto's Administration: Senior Economist. July 10, 2024. Tempo. https://en.tempo.co/read/1892550/whoosh-high-speed-train-ambition-a-time-bomb-for-prabowo-subiantos-administration-senior-economist
Financial Times. (2025). The Opec of nickel: Indonesia’s control of a critical metal. https://www.ft.com/content/0bbbe7c7-12a1-43ba-8bef-c5c546367a0e
Financial Times. (2024). Western miner Eramet sees no profits in nickel processing. https://www.ft.com/content/e42d5e3e-30ff-4698-8348-d0e6731f2271
Fox News. (2005). Indonesia Reasserts Control Over Aid. January 13, 2005. https://www.foxnews.com/story/indonesia-reasserts-control-over-aid
Franck, M. (2010). The impact of constructing the Suramadu Bridge in the Indonesian town of Surabaya. January 2010. https://books.openedition.org/editionscnrs/12639
Freedom House. (2024) Freedom in the World 2024. https://freedomhouse.org/report/freedom-world#Data
Gallup. (2025). Gallup World Poll, 2006-2024 [Data set]. Washington, DC: Gallup Inc.
Gelpern, A., Horn, S., Morris, S., Parks, B., and Trebesch, C. (2021, March 31). How China lends: A rare look into 100 debt contracts with foreign governments . AidData at William & Mary. https://docs.aiddata.org/reports/how-china-lends.html
Global Data Lab. (2024). Subnational Human Development Index (SHDI) Database, Version 7.0. Retrieved from https://globaldatalab.org/shdi/ .
Gorton, G and Souleles, N. (2007). Special purpose vehicles and securitization. In M. Carey and R. M. Stulz (Eds.), The risks of financial institutions . University of Chicago Press. http://www.nber.org/chapters/c9619
Government of Indonesia. (2007). Law of the Republic of Indonesia number 17 of 2007 on long-term national development plan of 2005–2025 . Office of the President of the Republic of Indonesia. https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/LONG-TERM%20NATIONAL%20DEVELOPMENT%20PLAN%20OF%202005-2025%20%28EN%29.pdf
Grimm, D. J. (2014). Traversing the minefield: Joint ventures and the Foreign Corrupt Practices Act. Virginia Law and Business Review , 9(1), 91-152. https://fcpa.stanford.edu/academic-articles/20140901-traversing-the-minefield-joint-ventures-and-the-fcpa.pdf
Ha, H. T. (2023, December 14). Late to the party: Vietnam and the Belt and Road Initiative . FULCRUM. https://fulcrum.sg/late-to-the-party-vietnam-and-the-belt-and-road-initiative/
Hadi, A. (2024). Whoosh burden bleeding finances, WIKA tells House. July 9, 2024. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/business/2024/07/09/whoosh-burden-bleeding-finances-wika-tells-house.html .
Harsaputra, I. (2009). Indonesia’s longest bridge set for operation. June 10, 2009. Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/news/2009/06/10/indonesia039s-longest-bridge-set-operation.html
Harsaputra, I. and A. Faisal. (2009). Opening of Suramadu bridge could leave thousands jobless. June 11, 2009. Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/news/2009/06/11/opening-suramadu-bridge-could-leave-thousands-jobless.html
Harsaputra, I. and W. Boediwardhana. (2008). Suramadu bridge expected to be completed next year. April 7, 2008. Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/news/2008/04/07/suramadu-bridge-expected-be-completed-next-year.html
Herlijanto, J. (2017). Old Stereotypes, New Convictions: Pribumi Perceptions of Ethnic Chinese in Indonesia. Trends in Southeast Asia. No. 6. ISEAS-Yusof Ishak Institute. https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2253
Hillman, J. and D. Sacks. (2021).China’s Belt and Road: Implications for the United States. Updated March 2021. Task Force Report No. 79. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/task-force-report/chinas-belt-and-road-implications-for-the-united-states/findings
Hodge, A. and D. Septiari. (2023). Jokowi’s solar vision ignites fiery protest . The Australian Online. September 22, 2023. Retrieved from Factiva.
Home, A. (2018). China's Tsingshan rains on nickel bulls' party: Andy Home. Reuters. October 30, 2018. https://www.reuters.com/article/world/chinas-tsingshan-rains-on-nickel-bulls-party-andy-home-idUSKCN1N426X/
Hunan Electric Power Design Institute Co., Ltd. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/09/11/world-bank-group-debars-china-energy-engineering-group-hunan-electric-power-design-institute-co-ltd
Ibrahim, A., and Karmini, N. (2023, October 2). Indonesia's president launched Southeast Asia’s first high-speed railway, which was funded by China. Associated Press. https://apnews.com/article/indonesia-china-high-speed-railway-widodo-1d0be6de98724f5ecdfb799e5d826fd6
IDX Channel. (November 2024). Lini Imaji (FUTR) and China Construction (CSCEC) Cooperation in Energy Infrastructure Development. https://www.idxchannel.com/market-news/lini-imaji-futr-dan-china-construction-cscec-kerja-sama-pengembangan-infrastruktur-energi
IESR. (2017). 2 Tahun Jokowi, Sudah 11,000 MW Pembangkit Listrik Dibangun. April 2, 2017. https://iesr.or.id/2-tahun-jokowi-sudah-11-000-mw-pembangkit-listrik-dibangun-2/
Indonesia Business Post. Indonesia grapples with high costs and debt guarantees in Jakarta-Bandung high-speed rail project . September 25, 2023. https://indonesiabusinesspost.com/1686/investment-and-risk/indonesia-grapples-with-high-costs-and-debt-guarantees-in-jakarta-bandung-high-speed-rail-project
Indonesia Business Post. (2008, October 1). JICA to provide US$3 billion for MRT East-West Phase 1 Stage 1 project. Indonesia Business Post. https://indonesiabusinesspost.com/2008/investment-and-risk/jica-to-provide-us-3-billion-for-mrt-east-west-phase-1-stage-1-project
Indonesia SEZ. (n.d.). Galang Batang SEZ. Secretariat General for the National Council for Special Economic Zones. Retrieved from: https://kek.go.id/investment/distribution/kek-galang-batang
Indonesian Statistics Agency. (2025). Statistical Yearbook of Indonesia. (2004 - 2025). February 28, 2025. BPS-Statistics. (Multiple yearbooks were accessed for data analysis). https://www.bps.go.id/en/publication/2025/02/28/8cfe1a589ad3693396d3db9f/statistical-yearbook-of-indonesia-2025.html
International Monetary Fund (IMF). (2020, April). State-Owned Enterprises: The Other Government. In Fiscal Monitor , April 2020 (pp. 45-60). https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2020/04/06/fiscal-monitor-april-2020#Chapter%203
International Monetary Fund. Asia and Pacific Dept. (2024). China’s Foreign Direct Investment: Inward and Outward. IMF Staff Country Reports, 2024(276), A004. Retrieved May 13, 2025, from https://doi.org/10.5089/9798400285998.002.A004
Irham, M. and A. Ajengrastri. (2023). Rempang Eco-City: ‘We will not leave’, say the islanders fighting eviction. October 19, 2023. BBC. https://www.bbc.com/news/world-asia-67051969
Irwin-Hunt. (2024). Sumatra posts fastest FDI regional growth in 2023. fDi Intelligence. April 15 2024. Retrieved from: https://www.fdiintelligence.com/content/ee6ec696-1f40-51c8-a2ac-7542624f73db
Isaac, J. (2025, June 3). Japan backs Indonesia's Kayan hydropower project to boost renewable energy goals . Indonesia Business Post . https://indonesiabusinesspost.com/3844/energy-and-resources/japan-backs-indonesias-kayan-hydropower-project-to-boost-renewable-energy-goals
Isabella, Y. (2023, April 9). Indonesia backs hydro to power new capital city . Eco-Business. https://www.eco-business.com/news/indonesia-backs-hydro-to-power-new-capital-city/
ITA. (2023). Indonesia Critical Minerals. Market Intelligence. U.S. International Trade Administration.September 27, 2023. https://www.trade.gov/market-intelligence/indonesia-critical-minerals
The Jakarta Post. (2023). Better safe than sorry. August 9, 2023. https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/08/09/better-safe-than-sorry.html
The Jakarta Post. (2019). Indonesia to ban nickel exports from January 2020. September 2, 2019. https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/02/indonesia-to-ban-nickel-exports-from-january-2020.html
The Jakarta Post. (2010). Editorial: OECD and our homework. November 3, 2010. https://www.thejakartapost.com/news/2010/11/03/editorial-oecd-and-our-homework.html
The Jakarta Post. (2009). The Suramadu Bridge. June 10, 2009. https://www.thejakartapost.com/news/2009/06/10/the-suramadu-bridge.html
The Jakarta Post. (2008). Indonesia, China relations almost in honeymoon state: Sudrajat. April 14, 2008. https://www.thejakartapost.com/news/2008/04/14/indonesia-china-relations-almost-honeymoon-state-sudrajat.html
Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development (2020). Brown-field Toll Road Projects . https://www.join-future.co.jp/english/investments/achievement/index.php?c=investment_en_view&pk=1603170681
JBIC. (2017). Project Finance for Re-expansion of Tanjung Jati B Coal-Fired Power Plant in Indonesia. February 27, 2017. https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2016/0227-53953.html
JDIH. (2009). Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-undangan UU) No. 4 Tahun 2009. Database Peraturan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38578/uu-no-4-tahun-2009
Jong, H.N. (2023). Investors over islanders as Indonesia uses force to push development projects. September 21, 2023. Mongabay. https://news.mongabay.com/2023/09/investors-over-islanders-as-indonesia-uses-force-to-push-development-project/
Juwita, R. D. (2025, April 24). CATL slashes funding for Indonesian EV battery project by 65%. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/business/2025/04/24/catl-slashes-funding-for-indonesian-ev-battery-project-by-65.html
King, G. (2025). Six Months of Prabowo: Indonesia’s Diplomatic Charm Offensive. May 5, 2025. Center for Strategic and International Studies. https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/six-months-prabowo-indonesias-diplomatic-charm-offensive
Kompas. (2009). PLTU 10,000 MW Akan Berjalan Tanpa Masalah. March 23, 2009. https://bola.kompas.com/read/2009/03/23/1606386/pltu.10.000.mw.akan.berjalan.tanpa.masalah
Kontan. (2024). Konsumsi Nikel pada 2025 Diproyeksi Meningkat di Tengah Potensi Pemangkasan Produksi. December 30, 2024. https://industri.kontan.co.id/news/konsumsi-nikel-pada-2025-diproyeksi-meningkat-di-tengah-potensi-pemangkasan-produksi
Kontan. (2009). Baru JBIC dan World Bank yang Siap danai 10,000 MW Tahap II. January 30, 2009. https://industri.kontan.co.id/news/baru-jbic-dan-world-bank-yang-siap-danai-10.000-mw-tahap-ii
Koswaraputra, D. (2024, June 14). Indonesia: Kayan Cascade hydropower project moves forward amid partner withdrawals, environmental and displacement concerns . Business and Human Rights Resource Centre. https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/indonesia-kayan-cascade-hydropower-project-advances-amid-partner-exits-environmental-displacement-concerns/
Laksmana, E. A. (2017). Pragmatic equidistance: How Indonesia manages its great power relations. In D. Denoon (Ed.), China, the United States, and the future of Southeast Asia. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2761998
Lalisang, A.E.Y. and D.S. Candra. (2020). Indonesiaʿs Global Maritime Fulcrum and Chinaʿs Belt Road Initiative https://asia.fes.de/news/indonesias-global-maritime-fulcrum-chinas-belt-road-initiative-a-match-made-at-sea-1.html
Liputan 6. (2002). A. Dahana: Diplomasi Dansa RI-Cina Bernuansa Romantisme. Updated January 24, 2017. https://www.liputan6.com/news/read/31365/a-dahana-diplomasi-dansa-ri-cina-bernuansa-romantisme
Liu, Y., and Rayi, A. (2024, October 29). What lies ahead for China-Indonesia relations under Indonesia’s new president? APCO Worldwide. https://www.apcoworldwide.com/blog/what-lies-ahead-for-china-indonesia-relations-under-indonesias-new-president/
Lubis, A. M. and Maqoma, R. I. (2024, April 4). 8 ways to ensure Indonesia’s nickel sector is sustainable. The Conversation. Retrieved from: https://theconversation.com/8-ways-to-ensure-indonesias-nickel-sector-is-sustainable-226747
Mahardhika, L.A. and H. Wibawa. (2023). Bisnis Indonesia - Proyek strategis nasional: Konsesi lama kereta cepat. Translated by Price Waterhouse Cooper. February 17, 2023. https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/february-2023/national-strategic-project-long-concession-for-high-speed-railway.html
Market Forces. (2017). Foreign Finance to Indonesian Coal. https://www.marketforces.org.au/research/indonesia/public-finance-to-indonesian-coal/
Mathew, D. and Custer, S. 2023. Aid in the National Interest: How America’s Comparators Structure their Development Assistance. Williamsburg, VA: AidData at William & Mary. Retrieved from: https://www.aiddata.org/publications/aid-in-the-national-interest-how-americas-comparators-structure-their-development-assistance
Ministry of Energy and Mineral Resources [MEMR]. (2014, July 1). Renegosiasi berhasil, harga gas tangguh naik jadi US$ 8 mulai 1 Juli 2014. Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi. https://migas.esdm.go.id/post/Renegosiasi-Berhasil,-Harga-Gas-Tangguh-Naik-Jadi-US$-8-Mulai-1-Juli-2014
Maulia, E. and Damayanti, I. (2022). Indonesia’s Jokowi bans bauxite exports from June, China likely hurt . Nikkei Asia. 21 December 2022. Retrieved from: https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Commodities/Jokowi-announces-bauxite-export-ban-for-June-defies-WTO
MEMR. (2008). Perkembangan Program Percepatan 10,000 MW. June 16, 2008. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Republik Indonesia. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/perkembangan-program-percepatan-10000-mw
Merwin, M. (2022). Indonesia’s Nickel Export Ban: Impacts on Supply Chains and the Energy Transition. Interview with Michael Merwin. National Bureau of Asian Research. November 19, 2022. https://www.nbr.org/publication/indonesias-nickel-export-ban-impacts-on-supply-chains-and-the-energy-transition/
Miller, R., Glen, J., Jaspersen, F., and Karmokolias, Y. (1997). International joint ventures in developing countries. Finance and Development , 34(1), 7-10. https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1997/03/pdf/miller.pdf
Minister of Trade of Indonesia. (2025). Neraca Perdagangan Dengan Mitra Dagang. Satu Data. https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/neraca-perdagangan-dengan-mitra-dagang
Ministry of Trade of Indonesia. (2013). Circular of the Director General of Foreign Trade Number 04/M-DAG/ED/12/2013. The Extension of Export Approval of Mining Products. Retrieved from: https://faolex.fao.org/docs/pdf/ins133221.pdf
Ministry of Trade of Indonesia. (2012). Regulation of the Minister of Trade No. 29/M-DAG/PER/5/2012. Concerning Provisions on the Export of Mining Goods.
Nabbs-Keller, G. (2020). The contending domestic and international imperatives of Indonesia’s China challenge. Australian Journal of Defence and Strategic Studies, 2(2). https://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:ea2ec32
Nabbs-Keller, G. (2011). Growing Convergence, Greater Consequence: The Strategic Implications of Closer Indonesia-China Relations. Security Challenges , 7 (3), 23–41. http://www.jstor.org/stable/26467106
Nicola, A., Sarwono, A., Muzzamil, S., and Akbarani, I. (2023). Corruption risk assessment of infrastructure projects in Indonesia. Transparency International Indonesia. https://ti.or.id/wp-content/uploads/2023/12/Laporan-ICRAT_ENG.pdf
Nindita, H. and Z. Feng. (2025a). How China’s investment in Indonesia’s nickel industry is impacting local communities. April 7, 2025. Global Voices. https://globalvoices.org/2025/04/07/how-chinas-investment-in-indonesias-nickel-industry-is-impacting-local-communities/#:~:text=In%202013%2C%20Indonesia, agreement%20for%20the%20industrial%20park
Nindita, H. and Z. Feng. (2025b). Workplace risks loom over Indonesia’s Chinese-funded nickel and steel smelters . April 16, 2025. https://globalvoices.org/2025/04/16/workplace-risks-loom-over-indonesias-chinese-funded-nickel-and-steel-smelters/
Nord, M., Altman, D., Angiolillo, F., Fernandes, T., Good God, A., and Lindberg, S. I. (2025). Democracy report 2025: 25 years of autocratization – Democracy trumped? V-Dem Institute, University of Gothenburg. https://v-dem.net/documents/54/v-dem_dr_2025_lowres_v1.pdf
OCO-2/OCO-3 Science Team, Payne, V., and Chatterjee, A. (2022). OCO-2 Level 2 bias-corrected XCO₂ and other select fields from the full-physics retrieval aggregated as daily files (Retrospective processing V11.1r). Greenbelt, MD, USA: Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center.
OECD. (n.d.a). Foreign direct investment (FDI). Organisation for Economic Cooperation and Development. https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/foreign-direct-investment-fdi/indicator-group/english_9a523b18-en#:~:text=Foreign%20Direct%20Investment%20(FDI)%20flows,earnings%2C%20and%20intercompany%20debt%20transactions
OECD. (n.d.b). FDI Statistics Explanatory Note. Retrieved from: https://www.oecd.org/daf/inv/FDI-statistics-explanatory-notes.pdf
Offshore Magazine. (2002). China’s CNOOC to buy Repsol’s Indonesian assets for $585 million. January 18, 2002. https://www.offshore-mag.com/home/article/16768001/chinas-cnooc-to-buy-repsols-indonesian-assets-for-585-million
Oster, S. (2006, September 20). CNOOC finally strikes deal to import Indonesian gas. The Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/SB115883491134169915
Otto, B. (2015, September 2). Indonesia cancels plans for first high-speed train. The Wall Street Journal . https://www.wsj.com/articles/indonesia-cancels-plans-for-first-high-speed-train-1441340797
Parks, B. C., Malik, A. A., Escobar, B., Zhang, S., Fedorochko, R., Solomon, K., Wang, F., Vlasto, L., Walsh, K. and Goodman, S. (2023) Belt and Road Reboot: Beijing’s Bid to De-Risk Its Global Infrastructure Initiative. Williamsburg, VA: AidData at William & Mary. https://www.aiddata.org/publications/belt-and-road-reboot
Pedelty, J. A., Devadiga, S., Masuoka, E., et al. (2007). Generating a long-term land data record from the AVHRR and MODIS instruments. Proceedings of IGARSS 2007 (pp. 1021–1025). Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Pedersen, J.D. (2021). India’s foreign aid policy: Aid recipient and aid donor. In: The Interface of Domestic and International Factors in India’s Foreign Policy. Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003122302-5/india-foreign-aid-policy-j%C3%B8rgen-dige-pedersen
Pemstein, D., Marquardt, K. L., Tzelgov, E., Wang, Y.-t., Medzihorsky, J., Krusell, J., Miri, F., and von Römer, J. (2025). The V-Dem measurement model: Latent variable analysis for cross-national and cross-temporal expert-coded data (V-Dem Working Paper No. 21, 10th ed.). University of Gothenburg: Varieties of Democracy Institute.
People’s Daily. (2002). China, Indonesia Hold First Energy Forum. Updated September 25, 2002. https://en.people.cn/200209/25/eng20020925_103867.shtml
Perusahaan Listrik Negara (PLN). (2015). PLN Annual Report 2015. https://web.pln.co.id/statics/uploads/2019/11/ARPLN2015.pdf
Pewarta. (2024, December 16). 20 Years of Hard Work and Building Dreams, CSCEC-4 Leaves a Mark on China-Indonesia Cooperation. https://www.pewarta.co.id/2024/12/20-tahun-kerja-keras-dan-membangun-impian-cscec-4-tinggalkan-jejak-dalam-kooperasi-china-dan-indonesia.html
Perwata. (2024, August 9). Jokowi Attends Inauguration of China-Funded Factory Construction Project, Praises China Construction Fourth Engineering Division Corp Ltd. (CSCEC-4) https://www.pewarta.co.id/2024/08/jokowi-hadiri-peresmian-proyek-pembangunan-pabrik-yang-didanai-china-beri-pujian-ke-china-construction-fourth-engineering-division-corp-ltd-cscec-4.html
Pramono, A.H., Manessa, M.D.M., Indrawan, M., Sari, D.A., Fuad, H.A.H., Khasanah, N., Pratiwi, K., Siregar, R.S.E., Winarni, N.L., Supriatna, J., Haryanto, B., Gallagher, K.P., Ray, R., Simmons, B.A., and H. Yogaswara. (2022). China’s Belt and Road Initiative in Indonesia: Mapping and Mitigating Environmental and Social Risks. Boston University. GCI Working Paper 21. July 2022. https://www.bu.edu/gdp/files/2022/07/GCI_WP_021_FIN.pdf
Pratama, R. A. (2022). Kontroversi Blast Furnace Krakatau Steel dari Lahir hingga ke DPR. February 17, 2022. KataData. https://katadata.co.id/indepth/telaah/620e7c2d0db95/kontroversi-blast-furnace-krakatau-steel-dari-lahir-hingga-ke-dpr
Purba, K. (2023). ‘Debt trap’ danger looms in Jakarta-Bandung high-speed train project. April 17, 2023. Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/04/17/debt-trap-danger-looms-in-jakarta-bandung-high-speed-train-project.html
Qin, J. (2005, April 25). Indonesia now a strategic partner. ChinaDaily.com. https://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-04/25/content_437349.htm
R20. (n.d.) Nahdlatul Ulama Declaration. G20 Religion Forum. https://g20religion.org/nahdlatul-ulama/
Rahayu, R. (2025). Rempang Eco City Excluded from Prabowo’s List of 77 National Strategic Projects. April 29, 2025. Tempo. https://en.tempo.co/read/2001632/rempang-eco-city-excluded-from-prabowos-list-of-77-national-strategic-projects
Rakhmat, M. Z., and Purnama, Y. (2024). Kandidat calon presiden dan China: Peta interaksi 3 calon presiden 2024 dengan China. Celios. https://celios.co.id/mapping-the-interactions-of-three-2024-indonesian-presidential-candidates-with-china/
Rakhmat, M., et al. (2024). China–Indonesia survey: Insights into Indonesian perceptions of China [Report]. Center of Economic and Law Studies. https://www.celios.co.id
Rakhmat, Z. (2022). China’s Digital Silk Road in Indonesia: Progress and implication. July 28, 2022. LSE IDEAS Strategic Update. https://lseideas.medium.com/chinas-digital-silk-road-in-indonesia-progress-and-implication-b6996172262a
Rakhmat, M. Z. (2022). Getting nods from the Muslims: China’s Muslim diplomacy in Indonesia. International Journal of China Studies, 13 (2), 237–264. https://ejournal.um.edu.my/index.php/IJCS/article/view/45503
Reuters. (2025). South Korea's LG Energy Solution pulls out from Indonesia EV battery investment. April 21, 2025.
Reuters. (2017). Indonesia, China consortium sign $4.5 billion loan for rail project. May 15, 2017. https://www.reuters.com/article/economy/indonesia-china-consortium-sign-45-billion-loan-for-rail-project-idUSKCN18B0RW/ .
Reuters. (2013, October 16). China's Shandong Nanshan to set up $5 bln aluminium complex in Indonesia . https://www.reuters.com/article/business/chinas-shandong-nanshan-to-set-up-5-bln-aluminium-complex-in-indonesia-idUSL3N0I626M/
Reuters. (January 2009). World Bank bars seven firms including four from China. https://www.reuters.com/article/idUSTRE50E0GX/
Reuters. (2025, February 5). Chinese firms control around 75% of Indonesian nickel capacity, report finds. https://www.reuters.com/markets/commodities/chinese-firms-control-around-75-indonesian-nickel-capacity-report-finds-2025-02-05/
Reuters. (2024, November 14). Indonesian president says he will safeguard sovereignty in South China Sea. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-president-says-he-will-safeguard-sovereignty-south-china-sea-2024-11-14/
Ribeiro, H., Holman, J., and L. Tang. (2021). Rising EV-grade nickel demand fuels interest in risky HPAL process. March 3, 2021. Commodity Insights Blog. S&P Global. https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/blog/metals/030321-nickel-hpal-technology-ev-batteries-emissions-environment-mining
Rondonuwu, O. (2015, August 26). China, Japan battle to build Indonesia's first bullet train. Yahoo! Finance. https://sg.finance.yahoo.com/news/china-japan-battle-build-indonesias-first-bullet-train-045027947--finance.html?guccounter=1
RSF. (n.d.). Indonesia. 2025 World Press Freedom Index . https://rsf.org/en/country/indonesia
Sambodo, M. T., and Oyama, T. (2010). The electricity sector before and after the Fast Track Program. Economics and Finance in Indonesia, 58 (3), 285–308. https://www.lpem.org/repec/lpe/efijnl/201013.pdf
Sampurna, R. H. (2018). Is China a threat to Indonesia: A discourse analysis of major Indonesian newspapers’ coverage on the China issues. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(1), 209–231. https://doi.org/10.15575/jispo.v8i1.4317 .
SASAC. (2025). China's Local State-Owned Enterprises Maintained Steady Operations in 2024. February 21, 2025. http://en.sasac.gov.cn/2025/02/21/c_18863.htm
Sebayang, R. (2022). China-RI CSCEC Staff Exchange Views on Environmentally Friendly Construction. 26 May 2022. IDN Times. https://www.idntimes.com/business/economy/rehia-indrayanti-br-sebayang/staf-cscec-china-ri-tukar-pandangan-soal-konstruksi-ramah-lingkungan .
Seneca ESG. (2023, September 20). PowerChina, Japan’s Sumitomo to develop USD17.bn hydropower plant in Indonesia . Seneca ESG. https://senecaesg.com/insights/powerchina-japans-sumitomo-to-develop-usd17-bn-hydropower-plant-in-indonesia/
Sengupta, D. (2023). Nanshan Aluminum to spin-off Indonesian business, leading Nanshan International to emerge as a separate entity. AL Circle. 10 October 2023. Retrieved from: https://www.alcircle.com/news/nanshan-aluminium-to-spin-off-indonesian-business-leading-nanshan-international-to-emerge-as-a-separate-entity-101616
Shanghai Nonferrous Metals Network. (2022, April 15). The total investment is nearly 6 billion US dollars! Ningde era and Indonesia join hands to build power battery industry chain project. https://news.metal.com/newscontent/101806191/the-total-investment-is-nearly-6-billion-us-dollars-ningde-era-and-indonesia-join-hands-to-build-power-battery-industry-chain-project/
Sharma, Y. (2022). Confucius Institutes reappear under new names – Report. University World News. 30 June 2022. Retrieved from: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20220630152610783
Sidik, S. (2020). Selamatkan Ekonomi RI, BRI Restruktrisasi Kredit Rp 190 T. October 6, 2020. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/market/20201006142302-17-192248/selamatkan-ekonomi-ri-bri-restruktrisasi-kredit-rp-190-t
Sihaloho, M.J. (2016). Ini Gaya Diplomasi Megawati Taklukkan Hati Jiang Zemin Saat Negosiasi LNG Tangguh. May 25, 2016. BeritaSatu. https://www.beritasatu.com/ekonomi/366650/ini-gaya-diplomasi-megawati-taklukkan-hati-jiang-zemin-saat-negosiasi-lng-tangguh
Smith, A.L. (2000). “Indonesia’s Foreign Policy under Abdurrahman Wahid: Radical or Status Quo State?” Contemporary Southeast Asia , vol. 22, no. 3, 2000, pp. 498–526. JSTOR , http://www.jstor.org/stable/25798509 . Accessed 15 Apr. 2025.
Smits, J., and Permanyer, I. (2019). The Subnational Human Development Database. Scientific Data, 6, Article 190038. https://doi.org/10.1038/sdata.2019.38 .
Soeriaatmadja, W. (2023). Indonesia promises better relocation package for islanders after clashes over Chinese project. The Straits Times. September 17 2023. Retrieved from Factiva. https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-promises-better-relocation-package-for-islanders-after-clashes-over-chinese-project
Sori, R. (2009,Maret 27). Dua setengah tahun MOU dana 10.000 MW RI-China belum cair juga. IESR. https://iesr.or.id/dua-setengah-tahun-mou-dana-10-000-mw-ri-china-belum-cair-juga/
Sritharan, N., and Rizkallah, P. (2024, April 5). Navigating Sinophobia amid Indonesia’s economic ascent. 9DASHLINE . https://www.9dashline.com/article/navigating-sinophobia-amid-indonesias-economic-ascent
Shofa, J.N. (2024). Indonesia Secures $903 million Japanese loan to extend MRT Project. May 13, 2024. Jakarta Globe. https://jakartaglobe.id/news/indonesia-secures-903-million-japanese-loan-to-extend-mrt-project
Strangio, S. (2025). China’s Xi Hails Ties With Indonesia Ahead of Southeast Asia Tour. The Diplomat. 14 April, 2025. Retrieved from: https://thediplomat.com/2025/04/chinas-xi-hails-ties-with-indonesia-ahead-of-southeast-asia-tour/
Strangio, S. (2022). Indonesia to Ban Exports of Bauxite From June 2023. The Diplomat. 22 December 2022. Retrieved from: https://thediplomat.com/2022/12/indonesia-to-ban-exports-of-bauxite-from-june-2023/
Stuart, M. R. and Maughn R. D. (2012) International Joint Ventures, A Practical Approach. https://www.dwt.com/-/media/files/publications/2012/05/international-joint-ventures-a-practical-approach/files/international-joint-ventures-article_stewart/fileattachment/international-joint-ventures-article_stewart.pdf
Sukma, R. (2009). Indonesia-China Relations: The Politics of Reengagement . Living with China, 89–106. doi:10.1057/9780230622623_6;
Susanty, F. (2017). S. Korea looks to develop RI infrastructure. November 13, 2017. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/news/2017/11/13/s-korea-looks-develop-ri-infrastructure.html
Tang, W. (2018, October 14). World Bank, ADB commit $1B each for disaster recovery . The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/news/2018/10/14/world-bank-adb-commit-1b-in-loans-each-for-disaster-recovery.htm
Tempo. (2024). 21 Tahu Jembatan Suramadu, Beriut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun. June 10, 2024. https://www.tempo.co/politik/21-tahun-jembatan-suramadu-berikut-7-fakta-pembangunan-jembatan-berbiaya-rp-4-5-triliun-50597
Tempo. (2023). Ekonom Ini Perkirakan Balik Modal Kereta Cepat Whoosh 80 Tahun Sesuai Masa Konsesi. October 19, 2023. https://www.tempo.co/ekonomi/ekonom-ini-perkirakan-balik-modal-kereta-cepat-whoosh-80-tahun-sesuai-masa-konsesi-130798
Tempo. (2022). Kerugian Negara di Kasus Krakatau Steel Ditaksir Mencapai Rp 6,9 Triliun. July 18, 2022. https://www.tempo.co/hukum/kerugian-negara-di-kasus-krakatau-steel-ditaksir-mencapai-rp-6-9-triliun-321453
Tempo. (2002). Megawati, the Dance and LNG. April 2, 2002. https://magz.tempo.co/read/economy/4704/megawati-the-dance-and-lng
Thee, K. W. (2012). The Impact of the Global Financial Crisis on the Indonesian Economy and the Prospects for the Resumption of Rapid and Sustained Growth. Chapter in Indonesia’s Economy since Independence (pp. 126–136). ISEAS–Yusof Ishak Institute.
Treadgold, T. (2025, January 24) Indonesia Follows The Chinese Market-Control Playbook In Nickel. Forbes. https://www.forbes.com/sites/timtreadgold/2025/01/24/indonesia-follows-the-chinese-market-control-playbook-in-nickel/
Tritto, A. (2023, April 11). How Indonesia used Chinese industrial investments to turn nickel into the new gold . Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org/research/2023/04/how-indonesia-used-chinese-industrial-investments-to-turn-nickel-into-the-new-gold?lang=en
UNDP. (2024). Bridging the Digital Divide: Skill Our Future Platforms to Empower Indonesian Youth. March 28, 2024. Press Release. https://www.undp.org/indonesia/press-releases/bridging-digital-divide-skill-our-future-platforms-empower-indonesian-youth#:~:text=Indonesia%20is%20home%20to%20a, a%20developed%20country%20in%202045 .
U.S. SBA (Small Business Administration). (2018). Understanding Joint Ventures. https://business.defense.gov/Portals/57/understanding%20joint%20ventures%20SBTW18.pdf?ver=2018-05-01-184900-317
Visscher, S. (1993). Sino-Indonesian Relations. China Information, 8 (1-2), 93–106 . https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0920203X9300800104
Weaver, L.R. (2002). Loans a ‘motivation’ for Megawati in China. March 25, 2002. CNN. https://edition.cnn.com/2002/WORLD/asiapcf/east/03/25/china.indon/
Winzenried, S. and F. Adhitya. (2014). Export ban on unprocessed minerals effective 12 January 2014– three-year reprieve for some, but uncertainty remains. PWC Indonesia Energy, Utilities and Mining Newsflash No. 50. January 2015. Retrieved from: https://www.pwc.com/id/en/publications/assets/eumpublications/newsflash/2014/eumnewsflash-50.pdf
Wood Mackenzie. (2023). The rise and rise of Indonesian HPAL - can it continue. April 4, 2023. https://www.woodmac.com/news/opinion/rise-of-indonesian-hpal/
World Bank. (n.d.) Sanctions System. Retrieved from: https://www.worldbank.org/en/about/unit/sanctions-system/about
World Bank. (June 2019). World Bank Group Debars China Railway Construction Corporation Ltd. and two subsidiaries. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/06/05/world-bank-group-debars-china-railway-construction-corporation-ltd-and-two-subsidiaries
World Bank. (September 2019). World Bank Group Debars China Energy Engineering Group. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/09/11/world-bank-group-debars-china-energy-engineering-group-hunan-electric-power-design-institute-co-ltd
World Trade Organization. (2022). Indonesia – Measures Relating to Raw Materials. WT/DS592/R. 30 November 2022. Retrieved from: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/592r_e.pdf
XL Axiata. (2024). https://www.xlaxiata.co.id/en/news/xl-axiata-and-smartfren-announce-idr-104-trillion
Yeung, C. (2024). The Belt and Road Initiative 10 Years Later: China’s Transition to ‘Small and Beautiful’. March 19, 2024. Asia Pacific Foundation of Canada. https://www.asiapacific.ca/publication/china-belt-and-road-initiative-10-years-later
Yudhoyono, S.B. (2025). Memimpin di Tengah Krisis: Kisah SBY dan Tsunami Aceh. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=oKvryPDy0e4
Yu, C.J. and Tang, M. (1992). International Joint Ventures: Theoretical Considerations. Managerial and Decision Economics , Vol. 13, No. 4, pp. 331-342. Wiley. https://www.jstor.org/stable/2487765
Zhou, T. (2019). Migration in the Time of Revolution: China, Indonesia, and the Cold War . Cornell University Press. http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctvfc51sh
[1] Menurut cendekiawan Tiongkok, Xiang Haoyu (2023), RRT memiliki tipologi berbagai bentuk kemitraan diplomatik. Dari seluruh tipologi tersebut, “kemitraan strategis” merupakan bentuk yang paling umum, mencakup sekitar 80 negara, termasuk Indonesia. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) merupakan organisasi antarpemerintah kawasan yang terdiri atas sepuluh negara di Asia Tenggara: Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
[2] Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) merupakan organisasi antarpemerintah kawasan yang terdiri atas sepuluh negara di Asia Tenggara: Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
[3] AIIB merupakan bank pembangunan multilateral yang dipimpin Beijing
[4] Seorang pakar Indonesia dalam wawancara ini mencatat perubahan persepsi terhadap kualitas teknologi Tiongkok. Pada awal 2000-an, mitra lokal mempertanyakan kualitas pembangkit listrik tenaga batu bara yang dibiayai Tiongkok karena hasilnya selalu lebih rendah dari kapasitas yang dijanjikan. Namun, menurut pakar tersebut, kondisi ini telah berubah seiring meningkatnya kualitas teknologi Tiongkok. Ia menyatakan bahwa jika memilih merek yang tepat, “beberapa teknologinya setara dengan milik Jerman.”
[5] Peningkatan produksi nikel Indonesia ini bertepatan dengan penurunan tajam harga nikel, hampir separuh sejak 2022, dari 30.000 dolar AS per ton menjadi 15.640 dolar AS per ton saat ini (Treadgold, 2025). Selain itu, meskipun Indonesia berambisi untuk memperluas produksi baterai EV, hanya lima persen dari penggunaan nikelnya digunakan untuk baterai, sementara sekitar 70 persen masih digunakan untuk produksi baja tahan karat (Lubis dan Maqoma, 2024).
[6] Dalam kunjungan luar negeri pertamanya ke Beijing, Subianto menyepakati peningkatan hubungan bilateral dengan menambahkan kerja sama keamanan sebagai pilar kelima. Dalam forum bisnis pada Januari 2025, ia menekankan pentingnya kerja sama ekonomi dan perdamaian melalui pembangunan (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2025).
[7] Tiongkok telah menjadi tujuan ekspor utama Indonesia selama sembilan tahun berturut-turut dan menjadi sumber impor utama selama lima belas tahun terakhir (BPS, 2025).
[8] Masa ini juga menandai perubahan penting dalam tata kelola bantuan pembangunan di Indonesia. Sejak 2007, pemerintah Indonesia mengambil alih koordinasi bantuan internasional secara langsung. Sebelumnya, pada 1967–1991, sebagian besar bantuan asing dikoordinasikan melalui Intergovernmental Group on Indonesia yang dipimpin Belanda. Pada 1992–2007, tanggung jawab koordinasi berada pada Consultative Group on Indonesia (CGI), yang dipimpin bersama oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Beberapa pengamat berpendapat bahwa sejak tidak adanya CGI, Indonesia kehilangan mekanisme evaluasi independen atas perekonomiannya (The Jakarta Post, 2010).
[9] Angka ini tidak mencakup investasi dari Hong Kong maupun sektor-sektor seperti minyak dan gas, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, pembiayaan, dan investasi yang izinnya dikeluarkan oleh lembaga teknis/sektoral. Juga tidak termasuk investasi portofolio dan rumah tangga. Jika Hong Kong dihitung, maka totalnya mencapai 16,3 miliar dolar AS dalam 30.360 proyek.
[10] Jika termasuk Hong Kong, total investasi tersebut naik menjadi 83,5 miliar dolar AS dalam 67.332 proyek selama 2015–2024.
[11] Tujuh wawancara dilakukan dengan pakar Indonesia dari kalangan lembaga pemikir, pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi, banyak di antaranya memiliki peran di berbagai bidang. Pewawancara menggunakan panduan semi-terstruktur untuk mengeksplorasi pemahaman dan pengamatan para narasumber terhadap investasi Tiongkok di Indonesia.
[12] Total kontribusi gabungan dari keempat donor bilateral tersebut mencapai 63,3 miliar dolar AS, sementara kontribusi dari RRT mencapai 69,6 miliar dolar AS.
[13] Contohnya, Jepang memberikan pinjaman senilai 903 juta dolar AS untuk perluasan jalur Timur–Barat Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dengan bunga tetap 0,3 persen, masa pelunasan 40 tahun, dan masa tenggang 10 tahun (Shofa, 2024).
[14] Nama program tersebut adalah “ Supporting Essential Health Actions and Transformation Program .”
[15] Proyek dengan skor 4 atau 5 pada “Loan Completeness Score” AidData. Lihat metodologi AidData’s Global Chinese Development Finance Dataset, Versi 3.0 .
[16] Jepang awalnya mengajukan pembiayaan proyek ini pada 2014 dengan bunga hanya 0,1 persen (Custer et al., 2023; Dreher et al., 2022). Sebagai pesaing, Beijing menawarkan waktu implementasi lebih cepat dan pembiayaan yang lebih murah. Namun, pembengkakan biaya akhirnya menaikkan nilai proyek sebesar 1,2 miliar dolar AS, dengan tambahan pembiayaan berbunga 3,4 persen, diturunkan dari proposal awal empat persen (Reuters, 2017; Purba, 2023).
[17] Penurunan pembiayaan RRT ke Indonesia pada tahun 2021 cukup mencolok, karena untuk pertama kalinya sejak 2010 Beijing mengalokasikan kurang dari 1 miliar dolar AS dalam pembiayaan baru. Beijing hanya menggerakkan 17 proyek, yang sebagian besar berupa donasi alat medis termasuk alat pelindung diri dan vaksin buatan Tiongkok, sebuah strategi yang secara luas dikenal sebagai “diplomasi masker” atau “diplomasi vaksin.” RRT menyediakan pembiayaan proyek sebesar 853 juta dolar AS kepada Indonesia, sementara ADB, Bank Dunia, Jepang, dan Korea Selatan secara kolektif memobilisasi 6,2 miliar dolar AS dalam pembiayaan pembangunan di berbagai sektor penting (transportasi dan pergudangan, dukungan anggaran umum, kesehatan, dan pemerintahan). Perlu dicatat bahwa data ini secara khusus berfokus pada pembiayaan yang diarahkan oleh negara RRT dan tidak mencakup FDI dari sektor swasta.
[18] Karena proyek-proyek ini baru diumumkan, rincian lengkap belum tersedia untuk semuanya. Belum jelas apakah setiap proyek yang diumumkan telah berkembang menjadi komitmen formal, atau berapa porsi pembiayaan proyek yang benar-benar dijamin oleh sumber resmi Tiongkok. Oleh karena itu, angka tahun 2023 sebaiknya diperlakukan sebagai data sementara.
[19] Karena PowerChina telah membatalkan komitmennya untuk mendanai proyek Kayan Cascade, nilai tersebut tidak dimasukkan dalam estimasi data agregat tahun 2023.
[20] Meskipun proyek kereta cepat Jakarta–Bandung merupakan investasi terbesar di antara proyek-proyek tersebut, Tiongkok justru lebih sering melakukan investasi skala kecil pada pengembangan berbagai jalan tol, menggunakan skema usaha patungan (joint ventures) dan lembaga tujuan khusus (special purpose vehicles) untuk menyalurkan dana. Proyek-proyek ini menghasilkan bentuk agunan tersendiri berupa penerimaan tol, yang memungkinkan pengembalian dana pembangunan secara sistematis (Gelpern et al., 2021). Tiongkok bukan satu-satunya negara yang berinvestasi di jalan tol Indonesia, Jepang juga mulai masuk ke sektor ini (Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development, 2020).
[21] Hal ini juga dapat disebabkan oleh meningkatnya kemampuan Indonesia dalam merespons bencana berskala kecil, yang menjadi salah satu sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 (Pemerintah Indonesia, 2007).
[22] Karena proyek ini didanai melalui AIIB, nilainya tidak termasuk dalam total pembiayaan pembangunan resmi Tiongkok dalam laporan ini.
[23] Daftar proyek AIIB di Indonesia dapat diakses di sini: https://www.aiib.org/en/projects/list/year/All/member/Indonesia/sector/All/project_type/All/financing_type/All/status/Approved.
[24] Investasi langsung Hong Kong ke Indonesia dari 2021 hingga 2024 mencapai 24,8 miliar dolar AS.
[25] Untuk detail lebih lanjut, lihat Smith (2000); Sukma (2009); dan Nabbs-Keller (2020).
[26] Komunike Pers Bersama Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia: http://id.china-embassy.gov.cn/indo/zgyyn/zywx/200404/t20040422_2347233.htm
[27] Jika disesuaikan dengan dolar konstan tahun 2024: masing-masing setara dengan 724,4 juta dolar AS untuk pinjaman siaga, 362,2 juta dolar AS untuk kredit ekspor, dan 5,4 juta dolar AS untuk hibah obat-obatan.
[28] Setara 13,7 miliar dolar AS dalam dolar konstan tahun 2024.
[29] Sebagai contoh, China Eximbank dan Bank of China memberikan pinjaman untuk pembangunan pembangkit listrik dalam tiga kasus terpisah dengan total sebesar 1,77 miliar dolar AS.
[30] Setara dengan 970,4 juta dolar AS dalam dolar konstan 2024.
[31] Jika disesuaikan dengan dolar konstan 2024: setara 9,95 juta dolar AS untuk hibah dan 663,5 juta dolar AS untuk pinjaman lunak.
[32] Setara 14,1 miliar dolar AS dalam dolar konstan 2024.
[33] Janji ini disampaikan dalam Pertemuan Khusus Para Pemimpin ASEAN mengenai Dampak Gempa Bumi dan Tsunami yang diselenggarakan di Indonesia. Perdana Menteri Tiongkok menyatakan komitmennya untuk turut serta dalam rekonstruksi dan pembangunan jangka panjang Aceh serta akan memberikan “bantuan tanpa pamrih sebatas kemampuan kami dan tanpa syarat tambahan” (Sukma, 2009).
[34] Paket pinjaman ini merupakan kelanjutan dari pinjaman lunak sebesar 400 juta dolar AS yang sebelumnya dijanjikan Tiongkok pada kunjungan kenegaraan Presiden Megawati pada Maret 2002.
[35] Disetarakan dengan nilai konstan 2024, jumlah ini setara dengan 5,5 juta dolar AS dalam bentuk hibah dan 458,6 juta dolar AS dalam bentuk pinjaman.
[36] Prioritas ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025.
[37] Sebagian besar, jika tidak seluruh, pembangkit listrik yang dibangun pada masa ini berbahan bakar batu bara. Tingginya permintaan batu bara mendorong pemerintah menetapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), yang mewajibkan produsen batu bara menjual sebagian output mereka kepada pemerintah dengan harga yang diatur.
[38] Setara dengan 5,3 miliar dolar AS dalam nilai konstan 2024.
[39] Program ini diluncurkan melalui Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2006.
[40] Program ini merupakan bagian dari strategi lebih luas untuk membangun hingga 22.000 MW kapasitas baru dengan biaya sekitar 200 triliun rupiah. Dari total tersebut, 10 GW dikembangkan oleh PLN, 10 GW oleh swasta melalui skema IPP (Independent Power Producer), dan 2 GW melalui kemitraan pemerintah-swasta.
[41] Masing-masing setara dengan 665,4 juta dolar AS dan 416,6 juta dolar AS dalam nilai konstan 2024
[42] Setara dengan 665,4 juta dolar AS dalam nilai konstan 2024
[43] Setara dengan 416,6 juta dolar AS dalam nilai konstan 2024
[44] Dinyatakan sebagai 700 juta dolar AS pada saat komitmen
[45] Dinyatakan sebagai 117 juta dolar AS pada saat komitmen. Daftar lengkap proyek FTP-2 tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014, dapat diakses di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/143761/permen-esdm-no-40-tahun-2014.
[46] Proyek tersebut, dengan nilai total 2,6 miliar dolar AS, dibiayai melalui skema pembiayaan campuran sebesar 70 persen utang dan 30 persen ekuitas.
[47] Daftar lengkap proyek-proyek yang disepakati dalam forum tersebut tersedia di: https://ekonomi.bisnis.com/read/20131003/9/166900/ini-21-perjanjian-kerja-sama-indonesia-china.
[48] Setara dengan 37,3 miliar dolar AS dalam nilai konstan 2024.
[49] Setara dengan 1,4 miliar dolar AS dalam nilai konstan 2024
[50] Sebagai contoh, pinjaman senilai 721 juta dolar AS dari China Development Bank untuk membiayai tiga pembangkit listrik di Indramayu tertunda hampir setahun dan baru dicairkan pada Maret 2009, meskipun perjanjian awal ditandatangani pada Mei 2008 (Detik, 2008). Keterlambatan tersebut dilaporkan disebabkan oleh sengketa yang tidak terkait antara Merpati Airlines dan Xi’an Aircraft Industrial Corporation atas pembelian 15 pesawat MA60 (Detik, 2009; Sori, 2009). Setelah sengketa tersebut diselesaikan, menyusul kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Tiongkok, pendanaan proyek pembangkit kembali dibuka dan PLN berhasil memperoleh tambahan pinjaman sebesar 1,06 miliar setara dengan 1,4 miliar miliar dolar AS dalam dolar konstan 2024 untuk tiga proyek tambahan (Detik, 2009; The Jakarta Post, 2009).
[51] Sebagai contoh, Menteri Koordinator Perekonomian ad interim sekaligus Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyarankan agar PLN merundingkan kembali pinjaman tersebut dan mempertimbangkan konversi pinjaman ke dalam mata uang yuan Tiongkok (The Jakarta Post, 2009), dengan memanfaatkan perjanjian currency swap yang telah disepakati sebelumnya (Kompas, 2009). Berdasarkan perjanjian itu, Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk menukar 175 triliun rupiah dengan 100 miliar yuan (sekitar 15 miliar dolar AS) guna mengurangi risiko fluktuasi mata uang asing.
[52] Pada tahun 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menyimpulkan bahwa proyek tersebut sejak awal tidak didukung oleh persiapan yang memadai maupun studi kelayakan yang layak, sehingga dinilai tidak bankable dan tidak layak untuk dijadikan objek investasi (Pratama, 2022). Proyek ini dikembangkan oleh konsorsium antara PT Krakatau Engineering (anak perusahaan Krakatau Steel) dan MCC CERI. Meskipun demikian, diskusi mengenai kemungkinan pengaktifan kembali proyek ini kembali mencuat dalam beberapa tahun terakhir (Anam, 2022).
[53] Setara dengan 741 juta dolar AS menurut kurs 2011, atau 1,02 miliar dolar AS dalam nilai konstan 2024
[54] Daftar lengkap agenda NawaCita dapat ditemukan dalam Manifesto Pemilu Joko Widodo–Jusuf Kalla, tersedia di sini: https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi_Misi_JOKOWI-JK.pdf. Rencana ini juga menekankan pembangunan bandara baru dan revitalisasi pasar tradisional.
[55] Kerangka kerja tersebut, menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (2019), mewajibkan proyek-proyek baru untuk mematuhi standar lingkungan yang tinggi, melakukan alih teknologi, menerapkan praktik terbaik internasional, menggunakan tenaga kerja Indonesia, serta mengedepankan pendekatan pembangunan yang terintegrasi.
[56] Rencana Widodo memperkirakan 109 proyek, terdiri atas 35 proyek yang dikembangkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), badan usaha milik negara, dan 74 proyek oleh sektor swasta, untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional dari 88,3% menjadi 97,4% (PLN, 2015).
[57] Perjanjian Pinjaman
untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Indonesia:
https://www.cdb.com.cn/English/xwzx_715/khdt/201708/t20170829_4510.html
[58] BRICS+ mengacu pada kelompok lima anggota awal yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, dengan penambahan anggota baru yaitu Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab.
[59] Proyek tahun 2023 masih merupakan cakupan awal.
[60] Karena keterbatasan informasi yang tersedia secara publik, kami tidak dapat menemukan informasi lokasi subnasional untuk semua proyek. Tabel dan analisis dalam bagian ini merepresentasikan subkumpulan terbaik dari proyek yang memiliki data lokasi subnasional.
[61] Saat Indonesia bersiap memindahkan ibu kota politik dari Jawa ke Kalimantan, perusahaan PowerChina dari Tiongkok sempat direncanakan mendukung proyek PLTA Kayan, sebelum akhirnya proyek tersebut terhenti dan pembiayaan serta implementasinya berpindah ke Jepang (lihat Kotak 3 di atas).
[62] Sumatra memiliki beberapa kota dengan populasi di atas satu juta, seperti Medan, Palembang, Bandar Lampung, dan Pekanbaru.
[63] Konsorsium tersebut meliputi Agricultural Bank of China (ABC), China Construction Bank Corporation (CCB), China Development Bank (CDB), Export-Import Bank of China, dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).
[64] Angka-angka dalam bagian ini mungkin berbeda dari yang diterbitkan oleh BPS. Hal ini disebabkan oleh penggunaan sumber data fDi Markets berbasis proyek, yang mungkin menghasilkan sedikit kekurangan dalam menghitung total investasi masuk. Untuk penjelasan lebih rinci mengenai sumber data dan alasan penggunaannya, silakan merujuk pada Lampiran Teknis.
[65] Tren yang dijelaskan di sini mencerminkan FDI masuk baru setiap tahunnya, bukan stok atau nilai total dari seluruh FDI sebelumnya dan yang sedang berlangsung pada tahun tertentu.
[66] FDI baru dari berbagai sumber global ke Indonesia menurun dari 34,1 miliar dolar AS menjadi 20,4 miliar dolar AS (penurunan sebesar 40 persen) dari tahun 2011 ke 2012. Sebagai perbandingan, perusahaan-perusahaan Tiongkok hampir sepenuhnya menarik diri dari Indonesia, memangkas pengejaran proyek baru mereka sebesar 98 persen, menjadi hanya sedikit di atas 116 juta dolar AS. Demikian pula, dari tahun 2018 ke 2019, FDI baru dari perusahaan-perusahaan Tiongkok turun dari 6,1 miliar dolar AS menjadi sedikit di atas 1 miliar dolar AS (penurunan sebesar 83 persen), meskipun total proyek baru tetap berada di atas 17,2 miliar dolar AS.
[67] Arus keluar modal Tiongkok pada tahun 2022 dan 2023 terjadi seiring dengan menurunnya tingkat FDI masuk ke Tiongkok ke level terendah dalam sejarah, yang dipicu oleh ketidakpastian, pergeseran geopolitik, dan penurunan ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi (IMF, 2024).
[68] Meskipun demikian, kedekatan dengan sumber daya petrokimia dan mineral strategis tampaknya tidak menjelaskan geografi subnasional dari arus masuk FDI Tiongkok ke Indonesia.
[69] Ningbo Puqin Times, anak perusahaan dari pemegang saham utama CATL, Guangdong Bangpu, menandatangani perjanjian dengan PT Aneka Tambang dan PT Industri Baterai Indonesia (IBI) untuk membangun proyek rantai industri baterai tenaga, yang mencakup kegiatan penambangan dan pemurnian nikel, bahan baku baterai, manufaktur baterai, serta daur ulang baterai. Namun demikian, tidak ada jaminan atas keberlanjutan investasi tersebut.
[70] Ini mencakup PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (CCBI) [Indonesia]; Konsulat Jenderal Tiongkok [Indonesia]; Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta [Indonesia]; PT Bank ICBC Indonesia, afiliasi dari Industrial and Commercial Bank of China [Indonesia]; BOC Aviation Ltd. [Singapura]; dan The Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Ltd. (ICBC) [Taiwan].
[71] Sebagai bagian dari rebranding Hanban pada tahun 2020, Beijing memindahkan pengawasan dan pendanaan Institut Konfusius ke dalam sebuah organisasi nirlaba dan amal yang terpisah—Chinese International Education Foundation (CIEF). Para pengamat pada umumnya memandang keputusan ini sebagai langkah defensif dalam menanggapi sorotan dan kritik internasional terhadap pengaruh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas Institut Konfusius (Sharma, 2022).
[72] Untuk informasi lebih lanjut mengenai metodologi AidData dan keseluruhan Global Chinese Development Finance Dataset , Versi 3.0, silakan merujuk pada Custer et al., 2023 dan Dreher et al., 2022.
[73] Termasuk ICBC Indonesia.
[74] Termasuk Bank of China (Cabang Jakarta), Bank of China (Hong Kong) Limited (BOCHK) dan BOC Cabang Singapora.
[75] Termasuk PT Bank CCB Indonesia.
[76] CLEC sebelumnya dikenal sebagai Hanban
[77] Termasuk China CITIC Bank International Limited (sebelumnya CITIC Ka Wah Bank).
[78] Parks et al. (2023) menemukan bahwa diperkirakan “50% dari portofolio pinjaman non-darurat Tiongkok di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah saat ini disalurkan melalui skema pinjaman sindikasi—dan lebih dari 80% dari skema ini melibatkan bank komersial Barat dan lembaga multilateral.”
[79] Termasuk Sumitomo Mitsui Banking Corporation Group (SMBC Group), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Sumitomo Mitsui Indonesia, dan Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (SMTB).
[80] Termasuk PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., Bank DBS Indonesia, dan Development Bank of Singapore (DBS).
[81] Termasuk Bank of China (Hong Kong) Limited (BOCHK) dan Bank of China (Cabang Jakarta).
[82] Termasuk Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, Standard Chartered Bank (Singapura) Limited, dan Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited.
[83] Termasuk ICBC Indonesia dan ICBC Asia.
[84] Termasuk Bank BNP Paribas Indonesia dan BNP Paribas Fortis S.A./N.V.
[85] Termasuk Bank Mandiri, Bank Mandiri Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Singapura, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Hong Kong.
[86] Termasuk PT CTBC Bank Indonesia.
[87] Termasuk Citibank International PLC, Citigroup Global Markets, Inc. dan Citigroup.
[88] Termasuk PT Indonesia Eximbank.
[89] Termasuk ANZ Bank.
[90] Termasuk United Overseas Bank Indonesia (UOB Indonesia) dan United Overseas Bank of Singapore.
[91] Sebagai hasil dari Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) Tiongkok, yang merupakan kelanjutan dari strategi “Go Global” (atau “Go Out”) tahun 1999, Tiongkok secara eksplisit berupaya mengekspor kelebihan produksi konstruksi, baja, dan semen miliknya, guna memajukan kepentingan nasional dengan cara memperoleh pasar luar negeri bagi surplus tersebut (Mathew dan Custer, 2023).
[92] China Road and Bridge Corporation (CRBC), anak perusahaan dari SASAC, terlibat dalam pembangunan Jembatan Tayan di Kalimantan Barat, yang merupakan salah satu proyek infrastruktur awal yang meningkatkan konektivitas di wilayah tersebut. CRBC memasuki pasar Indonesia pada tahun 2004 untuk membangun Jembatan Suramadu (selesai pada 2009), sebelum melanjutkan dengan proyek Jembatan Tayan (2012–2015).
[93] Definisi Joint
Venture (JV) menurut U.S. Small Business Administration
adalah:
“Sebuah asosiasi antara individu dan/atau
entitas yang memiliki kepentingan dalam [...] bekerja sama untuk
terlibat dalam dan melaksanakan [...] usaha bisnis dengan tujuan
terbatas demi keuntungan bersama [...] yang untuk tujuan tersebut
mereka menggabungkan upaya, properti, uang, keterampilan, atau
pengetahuan mereka, namun tidak secara berkelanjutan atau permanen
untuk menjalankan bisnis secara umum” (SBA, 2018, hlm. 2).
[94] Sebuah Special Purpose Vehicle (SPV) didefinisikan sebagai “suatu entitas hukum yang dibentuk oleh sebuah perusahaan (yang dikenal sebagai sponsor atau originator) dengan mentransfer aset kepada SPV, untuk melaksanakan suatu tujuan tertentu atau aktivitas yang dibatasi, atau serangkaian transaksi semacam itu. SPV tidak memiliki tujuan lain selain transaksi yang menjadi alasan pembentukannya, dan tidak dapat membuat keputusan substantif; aturan yang mengatur SPV telah ditetapkan sebelumnya dan secara ketat membatasi aktivitasnya. Bahkan, tidak ada orang yang bekerja di SPV dan entitas ini tidak memiliki lokasi fisik” (Gorton dan Souleles, 2007, hlm. 1).
[95] NU CARE-LAZISNU merupakan sayap filantropi dari Nahdlatul Ulama, organisasi Muslim terbesar di dunia (R20, n.d.), yang sangat dihormati dan berpengaruh di Indonesia.
[96] Bank Dunia (n.d.) memelihara daftar perusahaan dan individu yang dikenai sanksi sebagai bagian dari upaya untuk mendorong tata kelola yang baik dan memberantas korupsi.
[97] ADB (n.d.) juga memelihara daftar serupa yang memuat entitas-entitas yang dianggap telah “terlibat dalam pelanggaran integritas, termasuk praktik yang bersifat curang, korup, koersif, kolusif, dan menghambat.”
Proses sanksi yang diterapkan oleh Bank Dunia dan ADB tidaklah bersifat mutlak maupun sempurna. Basis data masing-masing hanya mencakup entitas yang telah mereka biayai atau yang terkena larangan silang oleh bank regional lainnya. Kualitas informasi yang tersedia juga tidak konsisten dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, mekanisme ini merupakan salah satu indikator paling netral untuk mengevaluasi praktik bisnis yang korup.
[98] Proses sanksi yang diterapkan oleh Bank Dunia dan ADB tidaklah bersifat mutlak maupun sempurna. Basis data masing-masing hanya mencakup entitas yang telah mereka biayai atau yang terkena larangan silang oleh bank regional lainnya. Kualitas informasi yang tersedia juga tidak konsisten dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, mekanisme ini merupakan salah satu indikator paling netral untuk mengevaluasi praktik bisnis yang korup.
[99] Data per Maret 2025, diperoleh dari basis data daring milik Bank Dunia dan Asian Development Bank mengenai perusahaan-perusahaan yang dikenai sanksi dan dilarang beroperasi.
[100] Untuk informasi lebih lanjut, lihat Beijing’s Big Bet on the Philippines (Custer et al., Juni 2024).
[101] Indeks Kebebasan Pers Dunia 2025 oleh Reporters Without Borders (RSF) juga menemukan bahwa meningkatnya keterkaitan antara para pemilik media dan aktor-aktor politik di Indonesia telah menyebabkan “pengendalian terhadap media yang kritis serta manipulasi informasi melalui troll daring, influenser berbayar, dan media partisan,” yang pada akhirnya mendorong tingkat swasensor yang lebih tinggi dalam pemberitaan media (RSF, n.d.).
[102] Pembangunan “Two Countries, Twin Park” menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kembar di Indonesia dan Tiongkok yang “mencari sinergi” (Antara, April 2025). Inisiatif ini memungkinkan kedua negara untuk bekerja sama secara erat dalam menyelaraskan logistik, serta rantai pasok hulu dan hilir. Bentuk kerja sama semacam ini memang dapat mempermudah hambatan perdagangan internasional, namun tetap mengandung seluruh risiko yang terkait dengan mekanisme Joint Ventures (JV) dan Special Purpose Vehicles (SPV) sebagaimana telah dijabarkan dalam Bagian 3.1 di atas.
[103] Dalam wawancara, sejumlah pakar mencatat bahwa diaspora Tionghoa di Indonesia bersifat beragam, termasuk individu-individu yang lebih mendukung Taiwan dibandingkan Tiongkok daratan dan bersikap skeptis terhadap pesan-pesan yang berpihak pada Tiongkok.
[104] Anak-anak perusahaan Sinar Mas Group mencakup berbagai industri, mulai dari manufaktur kertas dan pengolahan makanan hingga teknologi komunikasi dan pengembangan properti. Konglomerat ini disebut sebagai penerima dalam berbagai proyek pembangunan yang didanai oleh Tiongkok.
[105] Namun, hal ini tidak berarti bahwa proporsi proyek yang setara juga berlokasi di ibu kota. Bagian 2.3 di atas merinci bagaimana pendanaan dari Tiongkok didistribusikan secara subnasional di Indonesia, dan Bagian 4.2 di bawah menjelaskan bagaimana proyek-proyek tersebut memengaruhi komunitas lokal.
[106] Indonesia memiliki 38 provinsi, namun hanya 28 provinsi yang tercatat sebagai lokasi kantor pusat penerima pendanaan pembangunan dari Tiongkok. Provinsi-provinsi yang tidak tercantum dalam daftar penerima tersebut adalah: Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Lampung, Maluku Utara, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, dan Sulawesi Barat.
[107] Smartel dan Smartfren baru-baru ini bergabung dengan XL Axiata dan membentuk entitas baru bernama XL Smart (XL Axiata, 2024).
[108] AidData’s Global Chinese Development Finance Dataset , Versi 3.0, mencakup 20.985 proyek di 165 negara berpendapatan rendah dan menengah (termasuk Indonesia) yang didukung oleh pinjaman dan hibah dari lembaga-lembaga sektor resmi di Tiongkok dengan total nilai sebesar 1,34 triliun dolar AS. Dataset ini melacak proyek-proyek selama 22 tahun komitmen (2000–2021). Lihat: https://www.aiddata.org/data/aiddatas-global-chinese-development-finance-dataset-version-3-0
[109] Mengingat keterbatasan informasi yang tersedia secara publik, AidData tidak dapat menghimpun data secara lengkap mengenai status dan waktu pelaksanaan seluruh proyek. Untuk Indonesia, terdapat 381 proyek pembangunan yang dibiayai oleh RRT yang tidak memiliki data waktu secara lengkap, dan beberapa provinsi, seperti Maluku dan Sumatra Barat, tidak memiliki informasi untuk satu atau lebih tahapan proyek.
[110] Mengingat keterbatasan informasi yang tersedia secara publik, AidData tidak dapat menghimpun data secara lengkap mengenai status dan waktu pelaksanaan seluruh proyek. Untuk Indonesia, terdapat 381 proyek pembangunan yang dibiayai oleh RRT yang tidak memiliki data waktu secara lengkap, dan beberapa ,provinsi seperti Maluku dan Sumatra Barat, tidak memiliki informasi untuk satu atau lebih tahapan proyek.
[111] Pendekatan subnasional, dibandingkan dengan analisis tingkat nasional, menawarkan data yang lebih terperinci serta keselarasan yang lebih dekat dengan apa yang mungkin benar-benar diamati oleh responden. Namun, tidak semua proyek pembiayaan pembangunan ( development finance /DF) dan investasi langsung asing ( foreign direct investment /FDI) dapat dipetakan secara geografis, baik karena sifat proyek tersebut maupun keterbatasan dalam data sumber. Akibatnya, analisis subnasional kami tidak mencakup seluruh proyek yang dibiayai oleh RRT. Meskipun demikian, mengingat keragaman geografis dan desentralisasi administratif di Indonesia, manfaat dari pendekatan subnasional ini tetap melebihi keterbatasannya.
[112] Dalam model statistik kami, kami menggunakan efek tetap tahun dan provinsi ( year- and province-fixed effects ), serta menerapkan jeda waktu ( lag ) selama satu, tiga, dan lima tahun terhadap variabel prediktor keuangan guna mengkaji bagaimana paparan di masa lalu memengaruhi hasil saat ini. Pendekatan ini mencerminkan urutan kausal dasar dan membantu mengurangi bias simultanitas. Kami mengakui bahwa dampak implementasi dapat muncul dalam rentang waktu yang berbeda. Karena keempat variabel prediktor ini sangat condong ke kanan ( right-skew ), kami menerapkan transformasi logaritma natural untuk mempermudah interpretasi dan lebih memenuhi asumsi linearitas serta homoskedastisitas.
[113] Efek lainnya bersifat beragam atau berubah arah seiring waktu, yang berarti tidak terdapat hubungan arah yang jelas atau konsisten yang berlaku secara menyeluruh pada data dengan jeda waktu 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun.
[114] Efek marjinal, yakni perkiraan perubahan dalam kemungkinan persetujuan atas peningkatan satu unit dalam paparan proyek, untuk proyek pembiayaan pembangunan (DF) secara konsisten bernilai negatif meskipun kecil: -0,25%, -2,24%, dan -0,88% masing-masing untuk jeda waktu satu, tiga, dan lima tahun. Jumlah proyek penanaman modal asing langsung (FDI) juga menunjukkan efek marjinal negatif: -0,36%, -1,57%, dan -0,84% masing-masing untuk jeda waktu satu, tiga, dan lima tahun. Informasi lebih lanjut mengenai metode yang digunakan dalam analisis ini tersedia dalam Lampiran Teknis.
[115] Asian Barometer menemukan bahwa proporsi warga Indonesia yang menyatakan bahwa Tiongkok memiliki “pengaruh yang baik” di Indonesia menurun dari 64,76 persen pada tahun 2011 menjadi 36,93 persen pada tahun 2021. Asian Barometer menyediakan gelombang survei yang lebih sedikit dibandingkan dengan Gallup (hanya pada tahun 2011, 2016, 2019, dan 2021).
[116] Responden yang melaporkan menerima nasihat atau bantuan dari RRT menilai keterlibatan Beijing berdasarkan tiga dimensi: pengaruhnya terhadap prioritas kebijakan di negara mereka; sejauh mana pengaruh tersebut bersifat positif atau negatif; serta tingkat kebermanfaatannya dalam perancangan dan pelaksanaan reformasi kebijakan.
[117] Model-model diuji menggunakan spesifikasi jeda waktu satu, tiga, dan lima tahun. Silakan merujuk pada Lampiran Teknis untuk melihat hasil lengkap dari semua jeda waktu tersebut.
[118] Wawancara juga menyoroti frustrasi di tingkat lokal atas tidak adanya mekanisme yang jelas untuk melaporkan dampak lingkungan yang terkait dengan investasi Tiongkok.
[119] IMIP merupakan usaha patungan yang diluncurkan pada tahun 2013 di Sulawesi Tengah oleh PT Bintang Delapan dan Tsingshan Holding Group dari Tiongkok. IMIP telah berkembang menjadi pusat utama untuk pengolahan nikel yang digunakan dalam baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik.
[120] Hampir 80.000 hektare hutan telah dibuka di seluruh wilayah Sulawesi hingga tahun 2023, dengan lebih dari 6.100 hektare dibuka hanya dalam tahun tersebut, yang sebagian besar disebabkan oleh operasi penambangan nikel di Morowali dan wilayah sekitarnya (Brown dan Harris, 2024, hlm. 31).
[121] Peraturan presiden direvisi tanpa konsultasi yang memadai, auditor negara menyoroti adanya penyimpangan keuangan dan pembengkakan biaya, serta kekhawatiran terhadap korupsi meningkat akibat keterlibatan China Development Bank, yang wakil direkturnya pernah ditangkap atas tuduhan suap (Nicola et al., 2023).